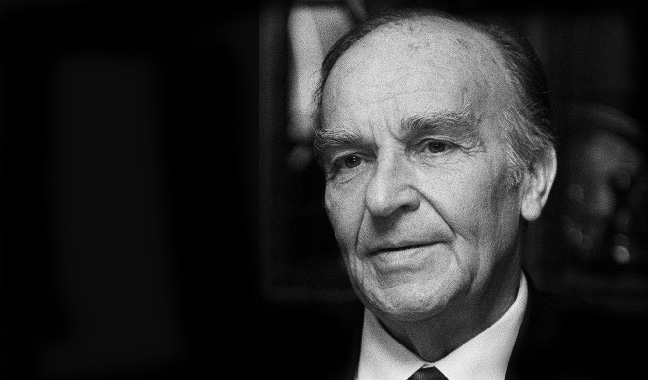Posts Tagged ‘politik islam’
BUKAN SOAL AGAMA, TAPI ATAS NAMA

“Our Freedom Can’t Wait!” Muhammad Speaks. Source: CBS (From http://www.baas.ac.uk)
Saya sebetulnya tidak setuju, dengan retorika yang kini jadi seakan kebenaran umum pada sebagian orang: “Jangan bawa-bawa agama ke dalam politik!”
Saya tidak setuju pernyataan itu dalam banyak segi. Pertama, kalimat “jangan” di situ sungguh patronizing, dan memaksakan nilai tertentu pada lawan bicara. Nilai sekularisme, nilai yang menyatakan bahwa agama dan politik adalah dua wilayah yang beda, terpisah, dan tak boleh bercampur.
Dalam nada pemaksaan tersebut, ada semacam pemutlakan: bahwa pemisahan agama dan politik (kenegaraan) adalah satu-satunya kebenaran, sumber kebaikan, dan sebaliknya, pencampuran politik dengan agama adalah sebuah keburukan dan pembawa mudharat nyata. Apa benar?
Sebelum sampai pada kesimpulan benar atau tidak preposisi itu, saya kok lebih suka mulai dengan menyorot dari segi praktik. Sederhana saja: mau dilarang-larang, di-“jangan-jangan”, nyatanya banyak orang membawa begitu saja agama ke ranah politik praktis di Indonesia. Lha, bukankah tak ada halangan bagi kelompok macam FPI, atau partai-partai macam PKS, PPP, PKB, untuk membawa-bawa agama dalam kiprah politik mereka? Percuma berpegang pada “jangan” jika memang tak ada yang dilarang dalam soal ini.
Beda soal dengan, misalnya, India. Atau Turki. Di kedua Negara itu, Sekularisme diakui secara resmi dan gamblang sebagai dasar bernegara. Ada regulasi (pengaturan) Negara untuk menjamin agar mereka tetap Sekular. Tapi, ternyata, bahkan dengan regulasi yang gamblang pun, kedua negara tersebut tak mampu membendung politik berbasis agama.
Di India, ada masanya partai kaum fundamentalis Hindu, BJP, mendominasi pemerintahan India, dan membikin banyak ketegangan dengan banyak kelompok politik di India. Turki, kita tahu, sudah dianggap mengalami Islamisasi di bawah rezim Erdogan. Lucunya, baik menurut kaum konservatif Islam di dunia (termasuk, banyak juga, di Indonesia) maupun oleh kaum Hawkish yang cenderung anti-Islam di Amerika, misalnya, sama saja rupanya: rezim Erdogan adalah rezim “Islami”. Kelompok fanboi (sebetulnya, banyak juga fangirl-nya) Erdogan memaklumi saja jika rezim Erdogan tidak/belum benar-benar menggugat secara radikal dasar negara sekular Turki.
“Politik adalah siasat,” begitu retorika lazim para ustadz untuk soal seperti Erdogan. Dan itu, kawan, adalah sebuah doktrin agama juga, dalam Islam, yang popular dalam ajaran dakwah ala Ikhwanul Muslimin. (Buat yang buru-buru mengaitkan gerakan Ikhwanul Muslimin, hey, itu bukan pendapat saya: Ikhwanul Muslimin punya sejarah panjang, dan bermula dari kehendak membebaskan dunia Islam dari kolonialisme –saya menghormati banyak pemikiran dalam gerakan tersebut, walau saya juga menampik banyak hal dari gerakan itu).
Lagipula, jangan salah, toh dari sebelum Indonesia ini resmi lahir, taruhlah seperti dipraktikkan oleh Tjokroaminoto di masa Hindia Belanda, agama telah digunakan sebagai instrumen penting kepolitikan. Tjokro menciptakan sebuah wahana penting gerakan politik kebangsaan, yakni Syarikat Islam (SI). Memangnya “Islam” di situ, apa? Nama orang? Ya, nama agama lah. Bukan hanya nama, prinsip-prinsip keagamaan pun dibawa serta dalam gerakan yang sangat penting bagi gerakan nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20 itu.
Lho, malahan, SI juga jadi rahim kelahiran Komunisme di Indonesia yang berujung pada lahirnya PKI yang sampai kini masih jadi momok bagi banyak kelompok Islam itu. Dan selama PKI berkiprah, banyak lah unsur agama dibawa-bawa, entah secara positif maupun negatif.
Teruskan saja sejarahnya, walau lintasannya sekilas-sekilas: pada masa Orba, agama juga sering dibawa-bawa, baik oleh rezim penguasa, maupun berbagai kelompok oposisi. Dalam kampanye era Orba pun demikian: paling meriah jika Pemilu, PPP dan Golkar akan “perang ayat”, menggunakan ayat-ayat Qur’an untuk menjatuhkan lawan dan menggiring suara pemilih. Menyebalkan? Nista? Atau hiburan? Katarsis? Mungkin semua itu.
Apa artinya, jika saat ini isu SARA menjerat Sang Petahana Pilkada DKI 2017, lantas kita berteriak-teriak “Jangan bawa-bawa Agama dalam politik!” Praktis, ucapan itu seakan abai pada kenyataan, keberartiannya gugur sejak diucapkan.
Mending, kita berpikir secara praktis juga: bagaimana agama bisa berperan secara positif dalam politik praktis?
Sebab, segala jurus fitnah (lewat hoax dan pelintiran), ujaran kebencian, ledakan-ledakan emosi akibat isu agama (atau, dianggap isu agama) hanyalah satu dari sekian banyak cara beragama. Dan sekian cara beragama itu akan bergantung pada gagasan pelaku masing-masing cara beragama itu tentang apa itu “beragama”.
Ketersinggungan kaum pengguna retorika Islam “keras” terhadap Ahok itu kan bukan hal baru, sudah sejak semula Ahok jadi gubernur DKI, atau bahkan sebelum itu (waktu masih jadi calon wagub bersama calon gubernur Jokowi), sebagian umat Islam seakan meradang betul ada “orang kafir” bakal memimpin umat Islam.
Pangkalnya adalah gagasan bahwa status keagamaan resmi seseorang bersifat menentukan secara mutlak kelayakan seseorang memimpin sekelompok umat manusia –kelompok umat manusia yang, coba tilik lebih dalam, dipandang juga hanya sebagai sekumpulan pemeluk resmi satu agama. Begitulah cara beragama orang-orang yang menolak Ahok (atau Jokowi, atau siapa pun) sebagai pemimpin politik atau birokrasi dengan alasan status agama sang calon.
Apa tak ada cara lain beragama? Tentu saja ada, bahkan banyak. Intinya, bisa saja seseorang pemeluk taat Islam justru meyakini agamanya menitah dirinya untuk, misalnya, “menyerahkan sesuatu pada ahlinya”. Atau, seperti Ibnu Taimiyah, yang berpendapat bahwa intisari agama adalah keadilan –maka beragama yang baik, ideal, dan “benar” adalah menegakkan keadilan di atas menegakkan status resmi agama si pemimpin dan umat.
Taimiyah berpendapat, “Lebih baik suatu negara dipimpin oleh seorang kafir tapi adil, ketimbang oleh seorang muslim yang tidak adil/zhalim.” Tentu saja, akan ada yang bisa membelokkan adagium ini ke dalam kasus Ahok, “Nah, Sang Petahana, menilik kasus-kasus penggusuran rakyat kecil di Jakarta, sudah bukan muslim, zhalim pula!” Bukan itu poinnya, Akhi, Ukhti!
Poin saya, adalah: ada cara beragama yang lebih baik daripada cara beragama yang gampang marah, terpaku hanya pada status agama resmi seorang calon gubernur dan para calon pemilih, dan gemar menebar fitnah serta sembarangan memakai podium agama seperti mimbar Jumat untuk menghujat dan menghujat dan menghujat seseorang.
Jangan bawa-bawa agama? Tidak. Demi Tuhan, bawalah agama ke arena politik! Seperti Martin Luther King dan Malcolm X membawa agama ke arena politik untuk mengilhamkan keadaan yang lebih baik bagi semua umat manusia. Seperti Nabi Muhammad SAW menggugat kesenjangan dan penindasan kelas yang dikukuhkan oleh penguasaan Agama dan sumber-sumberdaya Agama di tangan para elite saja.
Bawalah agama ke dalam politik seperti Gus Dur, Cak Nur, Gus Mus, Tjokro, Soegija, Njoman S. Pendit, Hamka, Munir, Bambang Widjoyanto dan banyak tokoh dengan kadar keagamaan berbagai-bagai yang penuh yakin menyusun Indonesia batu demi batu. Seperti Quraish Shihab berdoa di sebuah panggung politik demi menenteramkan para relawan di sebuah Pilpres, di tengah hujan fitnah dari orang-orang seperti Jonru.
Seperti KH. Zainuddin MZ berdakwah tentang kebajikan di tengah pentas Kantata Takwa. Seperti Emha dulu menggemuruhkan Lautan Jilbab di berbagai kota di Jawa, di saat jilbab dilarang rezim Soeharto dan jadi simbol perlawanan atas ketakadilan struktural masa itu. Agama bisa jadi ilham kemanusiaan. Agama, ya, Islam pun, yang banyak disangka buruk sebagai perusak dunia modern kita, bisa jadi ilham kemanusiaan dan kebangsaan kita.
Mungkin, Cak Nur (Nurcholis Madjid) memang jitu. Ia menyarankan sekularisasi Islam. Yang orang sering luput, Cak Nur pada saat yang sama, menolak sekularisme. Gagasan “sekularisasi” dari Cak Nur adalah mengolah dunia dalam logika dunia, dan tidak dengan mudah menyerahkan segalanya pada yang gaib. Antum a’lamu biumuuri dunyakum, kata Nabi SAW, Kalian lebih paham urusan-urusan duniawi kalian.
Lalu di manakah letak dan peran agama, dalam gagasan Cak Nur? Ia ada dalam ranah etis –agama menjadi sumber penilaian benar-salah dan baik-buruk bagi seseorang (atau sekelompok orang) dalam menjalani kehidupan dunia yang diarahkan menjadi keadaan lebih baik bagi manusia. Agama tidaklah memberi arahan bibit mana yang lebih unggul untuk panen jagung terbaik, tapi Agama lebih berperan, misalnya, pada membentuk kepercayaan bahwa seorang ilmuwan dan petani harus bekerja sebaik-baiknya untuk mendapatkan panen jagung terbaik demi kemaslahatan orang banyak.
Jadi, cara beragama yang lebih positif terhadap kemanusiaan itulah yang perlu masuk dan merangsek ke ruang percakapan politik dan publik saat ini. Jadikan berkompetisi saja, antara “agama” yang serba-marah-marah dengan agama yang serba berkah dan penuh rahmah dan marwah. Bawalah agama, yakni “agama” yang menjunjung tinggi keadilan, keadaban, kesejukan, ke dunia politik kita yang kotor ini. Bawalah agama yang etis.
Bukan “agama” yang penuh caci maki, gampang mengancam bunuh, serba membenci kanan kiri, dan memakai fitnah demi kemenangan. Buat saya, cara beragama penuh kebencian itu adalah penyalahgunaan agama: agama dijadikan alasan saja untuk membenci dan memenuhi hasrat perang yang pokoknya menghanguskan, menyingkirkan, menistakan orang dan kelompok yang beda. Buat saya, itulah penistaan Islam yang sesungguhnya.
BUDAYA POPULAR DAN POLITIK ISLAM
[DISCLAIMER: Sekali lagi, saya harus rajin mengarsip tulisan-tulisan saya. Ini tulisan saya, kalau tak salah, pada 1996-97. Celakanya, saya tak menemukan file asli tulisan ini, hanya file yang untuk alasan praktis yang saya lupa, telah saya hilangkan catatan kakinya. Akibatnya, beberapa pengutipan teori di sini tak menyertakan sumber bacaan. Misalnya, tulisan Ignas Kleden di Prisma itu. Mohon maaf, akan saya lengkapi suatu saat nanti. Selebihnya, ini bagian dari catatan proses berpikir saya tentang bidang yang sampai saat ini masih saya tekuni: budaya popular. Jelas kiranya, ada beberapa perkembangan pemikiran saya setelah tulisan ini dibuat.]
Jangan salah sangka: budaya populer bukan soal mudah. Tapi memang tak salah bahwa bagi kebanyakan orang, wa bil khusus bagi kebanyakan kaum cendikiawan, budaya populer adalah remeh belaka, semata remah peradaban yang mengganggu mata. Bagi banyak orang, budaya populer adalah non-isu. Bagi banyak orang, budaya populer sudah jelas wujudnya, letaknya, solusinya.
Itulah sikap populer terhadap budaya populer.
Padahal soal sesungguhnya jauh lebih runyam. Mari kita tilik sebuah kasus kecil. Anda bisa menyebutnya sebuah anekdot. Beberapa tahun lalu penulis membaca sebuah buku kumpulan fatwa karya seorang kyai yang kalau tak salah telah almarhum. Kyai haji tersebut membahas film The Message (karya Moustapha Akkad) – halal atau haram?
Dalam rangka “riset”, menelaah, menimbang, dan nantinya memutuskan, beliau pergi ke bioskop, menonton film itu. Bersama istri (!). Di tengah film beliau tak tahan, tak mampu menahan emosi, dan bangkit, berteriak: “Dusta! Sahabat tidaklah seperti itu…Hamzah bukan seperti itu…Bilal bukan seperti itu!” Atau ungkapan semacam itulah. Intinya, beliau kemudian memfatwakan bahwa umat Islam haram menonton film tersebut. Antara lain karena film itu telah “berbohong”: pemeranan para sahabat Rasul SAW oleh para aktor adalah “dusta”; rekonstruksi peristiwa historis dalam film itu adalah “dusta”, karena peristiwa “sesungguhnya” tak akan bisa, dan –menurut beliau– tak boleh, digambarkan.
Beberapa tahun kemudian, sekitar akhir tahun 1980-an hingga awal 1990-an, film itu –bersama karya Akkad lain, Lion of The Desert, yang dibintangi Anthony Queen, lebih disukai yang versi Arabnya juga– populer lagi. Kali itu versi berbahasa Arab, dengan judul Arab Ar Risalah. Dan publiknya tak sepenuhnya umum karena diputar dalam bentuk video dan biasanya diputar dalam kegiatan keagamaan Kerohanian Islam (ROHIS) SMA-SMA (kadang juga di kampus) Jakarta. Karena tanpa teks, biasanya pemutaran film didampingi seorang penerjemah yang sering menerjemahkan secara bebas.
Soal menerjemah bebas itu berkait dengan tujuan pemutaran film tersebut. Ar Risalah yang beberapa tahun sebelumnya diharamkan oleh kyai almarhum di atas, diputar dengan tujuan membangkitkan semangat (ghirah) Islam yang tinggi. Biasanya penerjemah menekankan bagian-bagian tentang jihad dalam film tersebut –lagipula bagian tentang jihad itu memang pas adegan-adegan penyiksaan dan perang (Badr, Uhud) yang asyik dan seru dilihat. Lalu dialog, serta adegan film, dikaitkan dengan ayat-ayat Al Qur’an yang relevan (para penerjemah itu biasanya punya kapasitas sebagai “ustadz” muda).
Sudah tak ada lagi problem pemeranan dan rekostruksi peristiwa sebagai “dusta”. Penonton malah digiring, dibetot-betot keharuan mereka, dengan, misalnya, menunjuk layar dan berkomentar “Lihat, betapa biadabnya Bilal disiksa” atau “Lihat, betapa gagahnya Hamzah, betapa tragis nasibnya ketika syahid, betapa kejamnya kaum kafir Quraisy…!” Setelah para penonton diharu-biru, kisah dramatis permulaan risalah Islam itu diberi relevansi kekinian dengan mengenalkan wacana “Jahiliyah modern” Kami mengamati pemutaran film tersebut cukup efektif membangkitkan semangat ke-Islam-an para penonton kaum muda itu.
Menarik. Sebuah teks yang sama bisa dibaca secara berlawanan. Sang kyai menganggap The Message/Ar Risalah melanggar dan membahayakan syari’at. Anak-anak muda SMA dan mahasiswa malah terbangkitkan semangat mereka untuk memperjuangkan syari’ah.
The Message/Ar Risalah adalah film yang digarap oleh Hollywood. Modal dan distribusinya di dukung oleh sistem Hollywood yang dikuasai orang-orang Yahudi. Moustapha Akkad adalah sineas Mesir yang telah memilih untuk menjadi warga Amerika. Menurut Syu’bah Asa dalam pengantar pemutaran Lion of The Desert suatu ketika di FISIP UI, Akkad dan keluarganya telah ter-Amerika-kan. Kedua film itu dibuat Akkad karena prihatin melihat anak-anaknya sama sekali tak punya lagi akar budaya Arab. Lion of The Desert bercerita tentang mujahid modern Umar Mukhtar. Mujahid agung itu diperani Anthony Queen dengan intens, sampai membuat basah mata beberapa penonton di FISIP UI di suatu ketika itu. Beberapa tahun kemudian Anthony Queen berperan dalam Ghost Can’t Do It yang mengeksploitasi tema seks dan keseksian tubuh Bo Derek yang moy.
Singkatnya, The Message/Ar Risalah adalah produk budaya populer. Apakah lantas tangis haru dan ghirah para penonton tadi jadi kehilangan makna? Dan apakah arti keterancaman sang kyai alamarhum itu?
Anekdot itu mengilustrasikan sebuah jaring makna yang pelik dalam produksi dan konsumsi budaya populer.
Secara sederhana kita bisa membayangkan apa yang ada di balik kepala Akkad, Anthony Queen, produser dan distributor Hollywood, sang kyai haji dan para siswa SMA atau mahasiswa tadi. Buat Akkad, ia hanyalah sedang mengekspresikan kesaksiannya akan sebuah nostalgia. Mungkin jauh dari impian Akkad bahwa karyanya bisa dipakai untuk membangkitkan semangat jihad sekelompok pemuda – yang kadang membangkitkan juga semangat anti-Barat/anti-Amerika yang kini jadi tanah air Akkad.
Buat Anthony Queen, mungkin “Just a job to do” yang boleh jadi menantang tapi tak lebih dari “bussines as usual”. Seperti mungkin juga yang dipikirkan para produser dan distributor Hollywood. Paling tidak, masak sih tak ada pikiran bahwa dua karya Akkad itu bisa membuka peluang pemasaran baru di negeri-negeri Islam (bahwa kemudian film The Message/Ar Risalah diharamkan di beberapa negara, itu lain soal; lagipula – mungkin justru karena pengharaman itu – toh kedua film itu cukup laku). Jadi, dari sudut produsen budaya, niat-niat idealistik baur dengan kepentingan-kepentingan ekonomis – dan itu wajar dalam produksi film yang memang kolektif.
Dan niat-niat idealistik produsen budaya, intensi sang produser, tak selalu relevan atau paralel dengan pemaknaan para penonton. Sang kyai memaknai produk tersebut sebagai pelanggaran, bahkan serangan, terhadap syari’ah. Sang siswa yang matanya basah dan dadanya gemuruh melihat “Bilal” disiksa dan “Hamzah” dicincang, memaknai lain lagi. Ada multi-makna yang bekerja dalam sebuah peristiwa.
Dan hal serupa terjadi setiap hari.
Makan di McDonald bisa berarti gengsi, tanda kemajuan atau memang karena fillet-O-fish pas di lidah. Memakai Nike bisa karena memang nyaman, atau karena gaya, dan orang lain bisa melihatnya sebagai simbol kekayaan atau kesombongan. Multi-makna terjadi pada saat kita memakai jeans, menonton Titanic, mendengar Madonna, membaca novel John Grisham terbaru, mengagumi gol indah Ronaldo, terbahak oleh Srimulat, bahkan saat kita terpukau oleh KH. Zaenudin MZ. Budaya populer ada dimana-mana, mengambil bentuk hampir apa saja, menjadi bagian keseharian kita. Di ujung abad 20, budaya populer semakin menjadi masalah kompleks dan khas.
Misalnya jika kita menghadapkannya pada politik Islam.
Sebagian atas jasa budaya populer, menjadi muslim adalah “kesalahan politik” sejak lahir. Kita yang lahir di negeri yang mayoritas berpenduduk muslim tentu tak akan merasakan itu. Tapi Anda yang pernah ke negeri lain, khususnya negara-negara Eropa dan Amerika; atau Anda yang punya akses terhadap informasi yang kuat dan tiap saat mengkonsumsi media massa luar, sambil kebetulan punya kesadaran identitas yang lumayan – Anda mungkin pernah mengalami semacam rasa tak berdaya karena sandaran identitas primordial Anda dihujat dan digugat. Semacam rasa tak berdaya yang mungkin dialami seorang Indian saat melihat film-film koboi lama yang mengheroikkan pemburuan Indian; atau saat seorang kulit hitam melihat gambaran pelayan negro dalam, misalnya, Gone With The Wind.
Islam di media massa Barat adalah si bungkuk buruk rupa dari Notre Dame. Tidak, lebih buruk lagi. Karena bahkan Quasimodo digambarkan berhati malaikat, seorang korban tragis dari syakwasangka masyarakat yang mengaitkan rupa dengan jiwa. Islam di media massa, Islam dalam citraan populer, adalah gerombolan orang bodoh tak berjiwa, yang dengan mudah menjadi teroris atau penindas wanita. Islam dalam citraan populer adalah seperangkat aturan antik, berlebihan, tak beralasan, menghambat kemajuan, anti intelektual dan tak memiliki spiritualitas. Islam dalam citraan populer adalah kasta paling rendah agama manusia.
Islam dalam citraan populer –atau, katakanlah, citra Islam di media massa sebagai sebuah produk budaya populer– hadir secara hantam kromo, taken for granted, berpretensi sebagai kenyataan yang tak terlawan: hanya benar dan titik. Citraan itu lalu dipercaya oleh sebagian kita. Atau dibenarkan oleh perilaku sebagian kita.
Itu masalah pertama. Bagaimana sebuah politik Islam bisa melawan citra populer tersebut? Sebab, persoalan mungkin “sederhana”: “hanya” perang citra. Tapi di baliknya ada kerumitan struktural yang jadi masalah umat Islam kontemporer. Salah satunya akses terhadap media massa, bukan sekadar sebagai “pembaca” tapi terutama jika hendak menjadi “penulis”. Bagaimanakah melawan sebuah jaringan informasi mondial dengan dukungan kapitalisme global?
Praktisnya, bagaimana melawan CNN, Reuter atau Hollywood? Atau jika hendak “melawan dari dalam”, bergerilya, memanfaatkan jaringan informasi yang telah ada, problem lain menyergap: cukup tersediakah para ‘gerilyawan’ informasi yang handal? Cukup tersediakah SDM dalam tubuh umat Islam? Maka terbukalah gerbang persoalan besar lainnya: masalah pendidikan, dan seterusnya, dan seterusnya.
Itu baru satu sisi persoalan, yaitu yang menyangkut bagaimana sebuah politik Islam bisa bergerak dalam medan budaya populer. Sisi lain adalah bagaimana sebuah politik Islam bisa bicara pada publik yang keseharian mereka dibentuk oleh budaya populer. Sisi soal kedua menyangkut hal yang lebih abstrak, lebih kultural. Ia lebih menyangkut makna, bahasa, wacana.
Bayangkan, misalnya, seorang yang jadi bagian generasi Orde Baru. Katakanlah ia lahir di periode 1970-an. Ia dibesarkan oleh majalah BOBO, televisi dan lagu-lagu pop (Barat atau lokal). Pendidikan seks yang pertama mungkin ia dapatkan dari komik silat atau novel-novel Nick Carter. Lalu nilai-nilai dalam dirinya – penghargaan akan yang “bagus” dan “tak bagus”, “yang perlu” dan “yang tidak”, misalnya – terajut oleh mal-mal dan iklan-iklan. Metabolismenya terisi fast food dan snack, di samping jajanan pinggir jalan. Pendidikannya antara lain mengajarkan –sadar atau tidak, sengaja atau tidak– bahwa agama adalah urusan privat di rumah atau dalam hati (tak ada hubungan dengan biologi, ekonomi atau sejarah); sambil diajari, diarahkan, untuk selalu patuh pada Negara atau paling tidak tak boleh/berani melawan lah; dan, yang terpenting, diajari, dibentuk, untuk menghargai tinggi posisi-posisi sosial di sektor-sektor ekonomi modern dan untuk itu diarahkan untuk selalu memprioritaskan keterampilan yang mendukung posisi-posisi tersebut.
Maka apakah arti politik Islam baginya? Bagaimanakah membahasakan politik Islam padanya? Eksperimen-eksperimen politik Islam selama ini menunjukkan bahwa pilihan-pilihan yang tersedia seolah hanyalah: (1) mengeraskan tradisionalisme (atau bahkan fundamentalisme); atau (2) beradaptasi – dalam pengertian menerima, percaya bahwa “ekses negatif” kemodernan yang (dianggap) biasanya hadir dalam “budaya populer” bisa diredam, dibendung, dengan ketinggian nilai-moral-etika Islam; atau (3) menjadi anti-politik sekalian, terjun sepenuhnya, dengan atau tanpa ideologisasi, pada pusaran budaya populer sebagai bagian dari hidup dalam alam modern.
Contoh pertama mungkin adalah kyai haji almarhum dalam anekdot di atas, di samping beberapa kelompok anak muda yang cenderung mengharamkan musik, televisi atau film/bioskop. Contoh kedua adalah Toto Tasmara yang dalam suatu kesempatan menganjurkan seni Islami dengan memanfaatkan seni modern misalnya dalam bentuk lagu-lagu rap dengan lirik “Islami”. Contoh ketiga (mungkin paling banyak terjadi), misalnya, AB Three yang dalam satu kesempatan berkerudung-ber-“busana muslimah” yang rapat, menyanyikan dengan penuh semangat shalawat pada Nabi SAW, sementara sehari-hari biasa manggung dengan rok mini, dan melakukan semua itu tanpa beban-beban psikologis, politis, ideologis apapun.
Dalam konteks budaya populer, ketiganya sama bersikeras menganggap budaya populer adalah masalah yang mudah dicari solusinya.
Tapi kita belum bicara hal yang mendasar: apakah “budaya populer” dan apakah “politik Islam”?
Sebuah artikel KOMPAS tentang musik populer mengilustrasikan kerancuan yang nyaris umum tentang pengertian budaya populer. Menurut artikel tersebut, benang merah diskusi antara musisi Bandung dengan para wartawan seni budaya tanggal 26 April 1998 adalah bahwa, “Akibat gempuran budaya pop, kelompok musisi muda (Indonesia) cenderung kesulitan mencari identitas dirinya sebagai bangsa Indonesia.” Lalu disebutkan bahwa para musisi muda itu “…cenderung eksis secara instan dan sulit membedakan karya musik sebagai komoditas dan sebagai kerajinan.” Dalam diskusi tersebut, Doel Sumbang lah yang menyumbang poin tentang “identitas”. Lebih lanjut, Doel Sumbang menggugat para musisi muda sebagai memiliki kesan “sulit tampil” ke permukaan jika tak “membonceng” ketenaran lagu-lagu Barat, sambil menyarankan bahwa “keanekaragaman budaya Indonesia sangat potensial membentuk identitas….”
Tampak bahwa secara umum budaya pop(uler) dalam diskusi tak lagi jadi terdakwa, tapi sudah divonis bersalah sebagai: 1. Komoditas (lawan dari kerajinan) ; 2. Membonceng Barat; 3. Menghambat identitas sebagai bangsa Indonesia.
Pertanyaan bisa diajukan: lalu apa namanya, misalnya, karya-karya Doel Sumbang itu? Apa karena dalam beberapa album terakhir (yang laris manis itu) ia memasukkan bunyi-bunyi alat musik tradisional, syair daerah, lantas karyanya bukan komoditi dan bukan budaya pop? Tampak bahwa budaya pop(uler) dipahami sebagai, kira-kira, produk budaya yang massal dan (karena itu) banal atau rendahan – singkatnya, musuh peradaban.
Pandangan merendahkan terhadap budaya populer mungkin muncul karena identifikasi budaya populer dengan “budaya rendah”, lawan dari “budaya tinggi”. Ignas Kleden sempat mencatat penghadapan tersebut. Di Indonesia, ungkap Kleden, kata “pop” lazimnya dipakai dalam pengertian sesuatu yang tak terlalu serius. Maka jika seseorang bicara tentang budaya pop, biasanya ia mengacu pada produk dan perilaku budaya yang dianggap tak termasuk dalam budaya mapan. Budaya pop diciptakan tak mesti sesuai dengan kriteria formal “budaya tinggi” dan tak dianggap oleh para elit budaya di Indonesia.
Dalam uraian tersebut Kleden kemudian mengungkap beberapa karakter utama budaya pop . Ia mengidentifikasi karakter budaya pop dengan: (1) membedakannya dari budaya yang telah mapan; (2) mengenali hubungannya dengan struktur sosial.
Lewat pembandingan (atau pembedaan) dengan budaya mapan, budaya populer pertama-tama memberi tekanan lebih besar pada kapasitas komunikatif dari produk-produk atau penampilan-penampilannya ketimbang pada apresiasi kritis khalayaknya. Dengan kata lain, budaya pop lebih memilih mengikuti estetika resepsi ketimbang estetika kreasi. Keindahan dalam budaya pop tak berhubungan dengan kriteria formal para kritisi, tapi hanya berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan aktual khalayak.
Perbedaan lain dengan budaya tinggi adalah sikap terhadap ruang dan waktu. Budaya tinggi, ungkap Kleden, berpretensi untuk menjadi kekal. Ia ingin memenangkan waktu, walau jika itu berarti mengorbankan ruang. Artinya, budaya tinggi pasti memilih memenangkan khalayak kecil untuk waktu yang lama ketimbang memilih memenangkan khalayak banyak pada satu waktu. Budaya pop jelas sebaliknya. Maka budaya tinggi berpretensi hadir untuk masa depan, dan budaya pop cukup berbahagia dengan masa kini. Yang pertama ingin abadi, yang kedua ingin global.
Dalam hubungan dengan struktur sosial, budaya pop dapat disifati sebagai budaya industrial dan budaya urban. Sebagai gejala masyarakat industrial, budaya pop punya dua sifat utama: di satu sisi ia cenderung jadi budaya massa; di sisi lain ia cenderung jadi budaya instan.
Sebagai budaya massa –yang merupakan bagian dari produksi massal, dan membutuhkan konsumsi massal– budaya pop dipromosikan dan dikembangkan dengan dasar penciptaan keinginan-keinginan. Maka, lanjut Kleden, budaya tinggi mencari khalayak sedang budaya pop mencari konsumen. Budaya tinggi memberi kepuasan budaya; budaya pop menjanjikan hiburan budaya.
Sebagai budaya instan, menurut Kleden, budaya pop cenderung mampu memenangkan perhatian khalayak ramai dalam waktu singkat untuk kemudian dilupakan selamanya. Kleden menyebut sebab kecenderungan itu adalah, pertama, budaya pop tak membutuhkan proses belajar lama untuk diterima; kedua, budaya pop tunduk pada kode perilaku pada masyarakat industrial, yaitu: semua hal berjalan cepat (tempo kehidupan harus menyesuaikan diri dengan kecepatan gerak dalam industri) – termasuk kreasi dan persepsi dari produk-produk budaya.
Dalam konteks tersebut Kleden menegaskan karakter urban budaya pop. Sebagai produk urban, budaya pop tak bisa tidak menjadi bagian ekonomi pasar dan submisif terhadap syarat-syarat mekanisme pasar. Dalam proses tersebut, seni, informasi dan pengetahuan tak lagi semata produk budaya tapi juga komoditi.
Uraian Kleden tersebut mulai menyentuh masalah-masalah dasar budaya populer dengan titik berangkat kasus Indonesia. Ia memulai uraiannya dengan membongkar akar sosiologis prasangka umum terhadap gejala budaya populer di Indonesia. Tapi Kleden sendiri belum sepenuhnya bebas dari prasangka terhadap budaya populer. Ketika Kleden membongkar akar sosiologis konsep budaya pop di Indonesia, ia dengan tepat menunjuk bahwa masalah bermula dari berlakunya paradigma tunggal estetika dalam dunia teori seni Indonesia, yaitu paradigma yang berakar dari humanisme universal. Mengingat, menurut Kleden, konsep budaya pop di Indonesia adalah perluasan dari konsep seni pop, maka paradigma estetika yang tunggal itu jadi penting dalam menilai budaya populer. Harga sebuah produk budaya populer bergantung pada estetika kaum humanis-universal.
Kleden tampak kritis terhadap paradigma estetika itu. Tapi dalam esei pendek tersebut belum cukup jelas apakah Kleden terutama mengkritik bangun konseptual paradigma estetika tunggal tersebut ataukah fakta bahwa ia menjadi paradigma tunggal.
Uraian Kleden amat logis. Terlalu logis, malah. Ia memuaskan secara alur logika, dengan mengorbankan kompleksitas masalah budaya populer: Kleden melakukan generalisasi, simplifiksi dan, sengaja atau tidak, melakukan reduksi. Dengan menempatkan budaya pop(uler) sebagai budaya industrial dan urban; atau budaya yang mementingkan kapasitas komunikasi dan penaklukan (khalayak) global ketimbang apresiasi kritis dan masa depan/keabadian, Kleden dengan enteng memandang kegiatan budaya pop(uler) sebagai kegiatan konsumsi –sebentuk kegiatan yang dipaksakan oleh sebuah sistem ideologi kapitalis, dan bukan sebentuk kegiatan pemaknaan yang aktif. Jangan-jangan budaya pop(uler) oleh Kleden masih dibayangkan sebagai benda, sebuah produk jadi atau by product dan tanpa kedalaman.
Jebakan umum dalam kajian teoritis tentang budaya populer memang adalah: satu, budaya populer tak dianggap sebagai “budaya”. Ia dianggap tak setara dengan, misalnya, “budaya bangsa”, “budaya Islam”, “budaya Jawa” dan sebagainya. Budaya populer (dianggap) adalah dangdut, Titanic, McDonald, bukan wacana, dan pasti tak punya kedalaman. Budaya populer adalah ekses modernisme/kapitalisme, bukan sistem pemaknaan atau sistem nilai yang khas.
Jebakan kedua adalah kelanjutan logis dari yang pertama: budaya populer tak dianggap sebuah kenyataan yang patut diperhitungkan dalam dunia teori. Dunia teori lebih tertarik pada teori-teori besar, pada doktrin atau ajaran, atau sistem (misalnya “kapitalisme”, “Marxisme”, “Islam” dan varian-varian mereka). Para teoritisi sering abai terhadap kenyataan sehari-hari. Makanya gejala budaya populer tak dipandang sebagai memiliki karakter pemaknaan yang aktif: ia tak punya ajaran, doktrin tertulis atau sistem berpikir yang tampak dan angker. Ia hanya hadir, merajut kesadaran keseharian kita.
Itu tampak pada Kleden saat ia menegaskan karakteristik-karakteristik budaya pop(uler). Misalnya saat ia menyebut budaya pop(uler) sebagai bagian dari budaya massa adalah komoditi. Dalam konteks tersebut Kleden menyoroti iklan sebagai alat ampuh penciptaan keinginan-keinginan, yang artifisial dan tak berhubungan dengan kebutuhan aktual para konsumen. Benarkah sehebat itu kekuatan pasar dan iklan? Benarkah komodifikasi berjalan linear, pasti, deterministik dan monolitik begitu saja?
Bahwa ada sebuah sistem kapitalisme yang meraksasa dan hegemonik memang bisa diterima. Tapi mengandaikan ada sekelompok besar manusia yang pasif, pasrah digiring ke satu arah tanpa perlawanan sama sekali adalah suatu hal yang masih perlu dipertanyakan. Dalam praktik, keberhasilan iklan merubah perilaku konsumen adalah anggapan yang terlalu dibesar-besarkan: Anda bisa tanya lah pada orang iklan sendiri. Tapi sebagai ilustrasi, John Fiske, dalam buku Understanding Popular Culture (1989), mencontohkan sebuah data: keluarga Australia rata-rata terekspos 1.100 iklan per hari lewat berbagai media (koran dan majalah (539), TV (374), radio (99) dan film (22)). Mereka juga terekspos bilbor, plang, iklan-iklan di taksi dan bis, jendela toko dan lain-lain. Nyatanya, menurut riset itu, yang termuat dalam Daily News, 15 Oktober 1987, orang-orang hanya ingat 3-4 iklan saja per hari.
Fiske membongkar anggapan umum tentang budaya populer sebagai semata produk banal kapitalisme. Ia menyebut produk-produk budaya populer (seperti jeans, program TV, iklan, dan sebagainya) sebagai teks. Budaya populer, bagi Fiske, adalah aktivitas pembacaan teks itu dan bukan produk-produk tersebut. Jadi budaya populer itu bukanlah dangdutnya, bukan “budaya pop” seperti yang dimengerti Doel Sumbang di atas, tapi adalah pemaknaan dari seorang penikmat dangdut, pemakai jeans dan semacamnya. Fiske menggeser nilai penting budaya populer pada aktifitas sang Pembaca (teks) budaya populer.
Penggeseran itu jadi mungkin karena Fiske percaya bahwa teks budaya populer tak memiliki makna tunggal (misalnya makna yang secara paksa dihadirkan oleh sistem kapitalisme), melainkan polisemi. Sekaligus, Fiske percaya bahwa kenyataan sehari-hari bukanlah nonsen. Maka pembacaan teks adalah sesuatu yang aktif dan merupakan kegiatan produksi juga. Pembaca adalah produsen makna. Budaya populer dengan demikian juga membuka ruang demokratis yang besar.
Mungkin akan lebih jelas jika kami kutip saja dahulu pengertian budaya/kebudayaan menurut Fiske: …culture – the active process of generating and circulating meanings and pleasures within a social system. Menurut pengertian itu, kebudayaan hanya bisa dikembangkan dari dalam, ia tak mungkin dipaksakan dari luar atau dari atas. Manusia tak mungkin berperilaku atau hidup sebagai massa – sebuah kesatuan yang dibayangkan sebagai sekumpulan pribadi yang terasing, satu dimensi, dengan kesadaran palsu serta berhubungan dengan sistem yang memperbudaknya dalam bentuk keterpaksaan seorang korban manipulasi.
Apa yang dilakukan seorang manusia dalam kesehariannya adalah melakukan pemaknaan aktif, dan dengan itu melakukan perlawanan terus-menerus, seringkali dalam bentuk gerilya, terhadap sistem yang mendominasinya. Itulah yang terjadi dalam budaya populer. Budaya populer adalah budaya dalam pengertian tersebut. Dalam ungkapan Fiske, dalam masyarakat konsumer, semua komoditi memiliki nilai-nilai fungsional sekaligus nilai-nilai kultural. Maka sebuah produk budaya populer dalam masyarakat industrial bisa diperlakukan dua macam: sebagai komoditi, maka penggunanya adalah konsumen – nilainya adalah jual-beli/ekonomi; dan sebagai sumber budaya (teks), maka penggunanya adalah, yah, pengguna (user).
Bahkan konsumsi pun kemudian jadi sebuah laku kebudayaan, jadi perlawanan, ketika sang konsumen adalah juga produsen makna. In consumer society of late capitalism, everyone is a consumer. Consumption is the only way of obtaining the resources of life…. Maka satu-satunya cara melawan adalah konsumsi dilakukan secara kreatif: konsumsi adalah produksi (makna); konsumen berkelit dengan adaptasi, dengan seni menggunakan yang ada, yang dipaksakan, agar sesuai dengan makna yang diciptakan sendiri.
Itulah yang terjadi, menurut Fiske, dalam kehidupan sehari-hari. Manusia bukan robot, bukan obyek dungu tanpa daya. Ia punya taktik untuk melawan dominasi (sering lebih intuitif ketimbang teoritik, tak sadar ketimbang sadar). Dan Fiske tepat ketika mengutip Umberto Eco: semakin besar suatu sistem, semakin mudah ia ditipu. Fiske juga mengutip studi de Certeau (1984). Dalam studinya, misalnya, de Certeau mengungkap bahwa sistem dominan –“si kuat”– mengkonstruksi “tempat” untuk mereka dapat melaksanakan kekuasaan mereka: kota-kota, mal-mal, sekolah-sekolah, kantor-kantor. “Si lemah” membuat “ruang” bagi mereka sendiri dalam tempat-tempat tersebut; mereka membuat tempat-tempat tersebut milik mereka untuk sementara saat mereka melewatinya, menduduki selama mereka bisa atau mereka perlu.
Perhatikan mal-mal, tempat sistem kapitalisme menyajikan diri dengan gemilang. Ada sekelompok ABG bergerombol, ngeceng. Ada dua orang sekretaris yang menggunakan waktu makan siang mereka untuk keluar-masuk toko pakaian dan sepatu, mencobai, dan tak memastikan diri akan jadi konsumen – malah bisa jadi mengadaptasi model baju yang mereka coba untuk jahitan sendiri dengan bahan lebih murah. Apa daya si empunya toko? Ada juga sekian banyak pedestrian yang murni window shopping. Ada anak yang menuntaskan seri Kungfu Boy di toko buku.

Foto diambil dari jateng.tribunnews.com, berita: “Yanti Ajarkan Pengunjung Mal Menghias Toples dan Parsel”
Di sekolah, murid hadir bukan untuk belajar tapi lebih karena ingin bergaul. Di kantor, karyawati menggunakan mesin fotokopi kantor untuk meng-copy artikel tentang susuk. Setiap orang dalam sistem berusaha untuk membuat ruang bagi dirinya, sekecil apapun. Setiap orang juga bisa memaknai sendiri produk-produk budaya populer yang terhidang di hadapannya. Iklan bisa jadi sekedar bahan lelucon. Jeans dirobek untuk memberi rasa keunikan pribadi, rasa kebebasan. Seorang dosen menyimak Titanic sebagai metafor pertentangan kelas dan karamnya Negara. Atau, kalaupun seorang ABG memanfaatkan Titanic untuk mengumpulkan bahan gombalan, ia, dalam pengertian Fiske, pun sedang melakukan aktifitas budaya.
Kata kunci yang mencirikan taktik dalam kehidupan sehari-hari adalah “adaptasi”, “manipulasi”, “tipu daya”. Fiske mengutip de Certeau: “People have to make do with what they have”, dan melanjutkan: …everyday life is the art of making do. Sementara budaya populer adalah seni “ada dalam antara” (“the art of being in between”) : menggunakan produk mereka untuk tujuan kita adalah seni meng-ada di antara produksi dan konsumsi; berbicara adalah seni meng-ada di antara sistem bahasa mereka dan pengalaman material kita; memasak adalah seni meng-ada di antara supermarket mereka dan makanan khas kita.
Masalahnya, sebagai gerilya kultural, kemenangan-kemenangan para pelakunya selalu kecil-kecil saja dan sementara, tak dapat dicatat dan sulit dipelajari. Tapi perlawanan itu ada dan nyata. Kehadirannya mirip dengan “perlawanan kaum tani” (seperti yang tercatat dalam penelitian klasik James C. Scott) – sebuah perlawanan bisu, diam-diam, perlawanan kaum tak berdaya, misalnya seperti yang tampak dalam anekdot petani yang diam-diam kentut saat menyembah sang raja. Jika “perlawanan kaum tani” terjadi di desa, perlawanan para konsumen terjadi dalam konteks urban. Dan, menurut Fiske, itu potensial untuk menjadi kekuatan progresif yang pada gilirannya – jika ada momen historis yang tepat – mampu menyumbang pada perubahan sosial.
Tapi perubahan sosial macam apa? Masa depan macam apakah yang diimplikasikan oleh uraian Fiske? Mengurai proyeksi perubahan sosial yang diharapkan Fiske akan terlalu panjang untuk tulisan ini. Cukuplah dikatakan, ungkapan Fiske bahwa kajiannya mendasarkan diri pada masyarakat industrial maju/tahap lanjut (yaitu “Barat”) menunjukkan sebuah konteks teoritis yang tak bisa kita lupakan begitu saja jika kita hendak memandang fenomena budaya populer di dunia ketiga (Indonesia, misalnya).
Di Barat, di samping telah memasuki tahap lanjut, masyarakat industrial juga lahir dalam sebuah proses sejarah yang relatif linear dibandingkan di Indonesia. Buktinya, di negeri ini berbagai peradaban hadir campur aduk dan tumpang tindih. Misalnya jika kita menggunakan kategorisasi peradaban Toffler, peradaban agraris, peradaban industrial dan peradaban informasi – nah, ketiganya hadir berbarengan sama kuatnya (atau, lebih tepat, sama tidak kuatnya).
Maka pengertian “budaya populer” pun punya aspek-aspek khusus di dunia ketiga. Misalnya pengertian seperti yang diungkap Izetbegovic. Ia pertama membedakan budaya populer dengan budaya massa: bagi Izetbegovic, tradisi membaca Al Qur’an dalam peradaban Islam adalah budaya populer – ia dilakukan oleh banyak orang, oleh khalayak yang beragam di lintas waktu dan tempat berbeda yang diikat oleh teks yang sama.
Bagi Izetbegovic rupanya sebuah produk budaya menjadi “populer” karena ia jadi milik “populis” – budaya populer adalah budaya rakyat/masyarakat (culture of the people). Sebetulnya Fiske juga berangkat dari titik yang sama. Hanya, di samping menekankan pada aktivitas pemaknaan atau pembacaan, Fiske juga menekankan budaya populer sebagai bagian – sebagai respon perlawanan pada – peradaban industrial. Tradisi membaca Al Qur’an seperti contoh Izetbegovic tadi bagi Fiske bukanlah budaya populer tapi budaya rakyat jelata (folk culture). Walau keduanya – sebagaimana orang-orang dalam masyarakat industrial dan rakyat jelata – memiliki beberapa karakteristik yang sama, tapi beda: Folk Culture adalah produk tata sosial tradisional yang stabil, yang membuat perbedaan-perbedaan sosial tak konfliktual sehingga masyarakatnya dicirikan oleh konsensus sosial ketimbang konflik sosial – sesuatu yang berlawanan dengan masyarakat industrial.
Tapi menurut hemat kami contoh Izetbegovic –walau punya kelemahan teoritis– tetap relevan untuk kasus dunia ketiga. Di Indonesia, misalnya, kehadiran taman-taman Al Qur’an adalah gejala kota. Begitu juga shalawat Nabi di TV-TV swasta dari Bank Mega (yang menampilkan Neno Warisman) atau dari Indosat yang keduanya menggunakan pendekatan video klip. Atau anak-anak muda “kaum pengajian” dalam contoh Ar Risalah / The Message di atas. Semuanya punya ciri budaya populer, tapi tak kehilangan jejak tradisi – masih mencirikan warisan “tata sosial tradisional yang stabil” (walau tentu patut ditelaah seberapa stabil, mengingat ia hadir dalam masyarakat konfliktual).
Jejak tradisi paling kuat dalam contoh-contoh di atas menurut kami adalah kehadiran yang sakral sebagai sumber-sumber gejala keagamaan tersebut. Kaum skeptis mungkin akan keberatan terhadap istilah yang sakral: gejala keagamaan di sela budaya populer hanyalah ‘baju’ atau kulit – budaya populer, betapapun, adalah sekuler. Itulah sebabnya Fiske dapat secara penuh menerima setiap pemaknaan pribadi sebagai perlawanan terhadap sistem, sebagai budaya. Tak ada problem “benar” atau “salah” dalam uraian Fiske, yang penting adalah ada. Persoalan perlawanan terhadap sistem yang mendominasi bukanlah persoalan “kebenaran” melawan “kebathilan” (konsekuensinya, bukan juga persoalan melawan dengan “jalan yang benar” atau bukan), tapi semata persoalan politik dalam pengertian Foucaultian – relasi kekuasaan yang diskursif dan berkonteks spesifik.
Memang perlu diskusi lebih lanjut tentang kehadiran dan posisi yang sakral dalam budaya populer. Yang jelas, dengan menjadikan yang sakral sebagai variabel maka berarti menghadirkan pula masalah nilai-nilai dalam budaya populer – sesuatu yang agaknya dihindari Fiske. Salah satu konsekuensinya, penghadapan budaya populer dengan yang sakral akan mencakup problemasi “kebenaran” (bahwa “ada” saja tak cukup, tapi juga bagaimana “kebenaran” hadir dan bekerja?), problemasi “kenyataan” (bagaimana menjelaskan yang sakral sebagai kenyataan; atau kenyataan apakah yang membuat yang sakral itu mungkin?) dan pada gilirannya akan mengharuskan problemasi radikal terhadap modernisme.
Celakanya, politik Islam seringkali tak menyadari masalah tersebut. Menghadapi budaya populer, politik Islam seringkali tak memiliki perangkat pemahaman yang tepat, sehingga sering memunculkan sikap yang tak jitu: apapun jenis eksperimen politik Islam yang disodorkan di Indonesia, rata-rata masih berpijak pada kekeliruan umum pemahaman budaya populer, yaitu tak menganggapnya sebagai budaya dan kenyataan – budaya populer hanyalah ekses yang mudah ditaklukkan. Dalam kebanyakan eksperimen politik Islam, budaya populer bukanlah isu.
Persoalan dasar politik Islam masih terletak pada persoalan pemahaman terhadap modernisme (dan modernitas, juga modernisasi). Salah satu ciri utama masalah itu adalah bahwa politik Islam umumnya masih berbasis wacana negara-bangsa. Seiring dengan itu politik Islam masih lebih sering menggantungkan diri pada teori-teori besar.
Padahal jujur saja, manakah yang lebih kuat merajut kesadaran seorang anak Orde Baru: doktrin Pancasila atau majalah BOBO? Mana lebih kuat, undang-undang politik atau MTV? Basis wacana negara-bangsa dalam politik Islam antara lain menghalangi pemahaman kekuasaan dalam pengertian Foucault. Akibatnya kita umumnya lalai mengurusi pertarungan politik dalam kenyataan hidup sehari-hari. Kita lebih suka mencaci “keawaman” ketimbang berusaha memahaminya. Padahal di wilayah “keawaman” itulah letak sesungguhnya politik modernisme; dalam kesadaran keseharian itu pula Islam digempur.
Maka apakah politik Islam dalam konteks masalah budaya populer? Pengertian yang utuh, menurut kami, baru mungkin jika kita membebaskan diri dari wacana negara-bangsa. Atau setidaknya jika kita memproblemasinya.
Untuk sementara, saya mencukupkan diri pada ajakan tersebut.