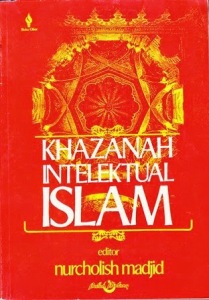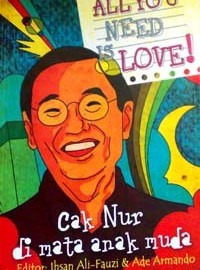ATHEISME: DARI TREND JADI BRAND

Foto: National Catholic Reporter (ncronline.com)
[Disclaimer]: Tulisan ini pernah saya muat di situs medsos almarhum multiply.com pada 2007. Diunggah lagi di sini untuk jadi arsip. Lagipula, tampaknya tema ini masih relevan. Telah 13 tahun berlalu, dan banyak hal belum beranjak jauh, rupanya. Semoga arsip pikiran saya ini bisa bermanfaat.
Kamis malam, 20 September 2007, sebuah rumah dengan pengaruh arsitektur Indies yang resik tampak ramai. Acara buka puasa. Tapi ada yang mungkin ganjil bagi sebagian orang di sini. Acara buka puasa itu juga dimeriahkan sebuah diskusi membedah tiga buku yang sedang laris di Amerika: God Delusions (Richard Dawkins), God Is Not Great (Christopher Hitchens), dan Letters to Christian Nation (Sam Harris –yang masih hangat dibincang publik Amerika karena bukunya yang lebih laris lagi, The End of Faith). Benar, diskusi Ramadhan di rumah itu menguar tema atheisme –tapi tak dengan nada menghujat.
Rumah itu adalah markas Freedom Institute. Pembicara malam itu: Rizal Mallarangeng, yang juga pimpinan Freedom Institute; Goenawan Mohamad, penyair dan salah satu esais paling berpengaruh di Indonesia selama dan sesudah Orde Baru; dan Luthfi Assyaukanie, aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL). Dalam sessi tanya jawab, seorang lelaki tinggi, pucat, dan bertampang Arab, dengan bersemangat urun komentar.
Ia, Hamid Basyaib, awak Freedom Institute dan aktivis JIL juga, membahas buku Sam Harris. Ia mengangkat satu contoh, isu stem cell research yang jadi kontroversi di Amerika. Setelah ia sedikit menerangkan uraian Sam Harris tentang riset itu, Hamid bilang, “Sam Harris cuma mau bilang, itu kaum agamawan ini, mereka jangan sok tahu …jangan asal bicara untuk hal-hal yang mereka tak tahu.” Hamid menekankan hal serupa untuk Indonesia.
Inilah yang mungkin ganjil bagi banyak orang di sini: diskusi tiga buku yang secara agresif menyerang (semua) agama dan mempromosikan atheisme dalam nada positif terhadap kehadiran buku itu, persis setelah buka puasa.
Hanya Goenawan Mohamad yang sangat kritis terhadap atheisme secara umum, dengan pendekatan kultural-filosofisnya. Rizal, walau tak sepenuhnya sepakat dengan isi ketiga buku itu, memuji kehadiran buku-buku sejenis yang bisa memberi “penyegaran” dan membantu kita kritis dalam keberagamaan kita. Rizal dengan jitu menekankan fakta bahwa ketiga buku itu laris, berarti memang penting (untuk dibicarakan). Luthfi sama sekali tak menampakkan kesadaran kritis terhadap buku-buku ini, ia hanya memuji-muji (terutama) kritik-kritik Dawkins terhadap teologi. Ada antusiasme di situ, terhadap tawaran sains ala Dawkins untuk menggusur agama; sebagaimana ada antusiasme pula dalam pengungkapan masalah stem cell research itu oleh Hamid.
Namun, antusiasme itu perlu kita soroti dengan lebih tenang dan hati-hati. Bagaimana pun, selalu ada konteks dalam setiap pemahaman. Ketika sebuah pemahaman dipaksakan untuk mengabaikan konteks yang nyata ada –konflik yang terjadi mungkin malah kontraproduktif. Mengangkat kasus steam cell research untuk menyimpulkan kaum agamawan harus dibatasi di Indonesia, misalnya, sama saja memaksakan konteks Amerika untuk persoalan Indonesia. Mungkin bagi Hamid atau Luthfi, konteks Amerika itu sungguh nyata.
Dalam uraiannya malam itu, Rizal dan juga Luthfi bercerita tentang betapa mudahnya menemukan buku-buku yang mereka bahas itu di gerai-gerai buku bandara berbagai kota dunia yang mereka temui. Tanpa sadar, mereka menampakkan sebuah konteks kelas sosial-ekonomi yang jauh berbeda dengan kebanyakan orang Indonesia yang barangkali berada di posisi berseberangan dalam hal peran kaum agamawan dalam masyarakat Indonesia. Hamid dan Luthfi bicara tentang stem cell research, sedang kebanyakan orang Indonesia masih dibingungkan soal lumpur Lapindo, bencana alam, merajalelanya narkoba, dan segala pelik soal dunia ketiga dalam keseharian mereka.

Foto: The Economist
Teori Evolusi sebagai perang kultural
Steam cell research adalah salah satu isu besar dalam sesuatu yang dinamakan sebagai “perang kultural” di Amerika dan Eropa. Majalah The Economist edisi 3-9 November 2007 yang menurunkan sebuah laporan khusus mengenai “The new wars of religion” menyebutkan juga isu aborsi, pernikahan kaum gay, dan euthanasia sebagai isu-isu perang kultural kontemporer.
The Economist mencatat bahwa isu-isu ini perlahan menjadi isu global, karena mulai muncul di berbagai belahan bumi saat ini. Namun majalah ini juga mencatat bahwa isu-isu ini diekspor dari Amerika, sebagaimana isu lain yang lebih kita akrabi di sini: sekularisme atau sekularisasi lembaga-lembaga politik dan sosial. Berdasarkan catatan The Economist, perang kultural ini memang sering problematis. Misalnya, para hakim dan politisi berpikiran liberal dari Colombia hingga Afrika Selatan mencoba melegalkan pernikahan gay. Walau langkah ini mengagumkan dalam pandangan The Economist, namun seringkali tak mencerminkan pandangan kaum kebanyakan di negara mereka sendiri.
Isu steam cell research menguat di publik awam Amerika selama beberapa tahun ini. Pemerintahan Bush, atas dasar pertimbangan keagamaan, berupaya melarang riset ini. Pelarangan ini menimbulkan amarah komunitas sains maupun sebagian masyarakat Amerika karena riset ini memberi secercah harapan pada penyembuhan kanker. Ketika Michael J. Fox, yang menderita penyakit Alzheimer, dilecehkan secara publik oleh seorang pejabat pemerintah karena mendukung steam cell research, ia mendapat simpati luas –demikian juga isu pelarangan riset ini mencapai tingkat emosional tinggi di Amerika.
Dalam kasus ini di Amerika, tampak bahwa segi kultural berjalin kuat dengan segi sains dan ekonomi. Memang, inilah tiga buah medan “perang” yang disebut The Economist dalam laporan khusus itu. Stem cell research menjadi perang kultural karena terjadi perebutan keras di wilayah publik mengenai nilai-nilai yang mendasari kedua belah pihak yang berlawanan itu: apakah agama bisa menjadi landasan keputusan politik, apalagi jika keputusan itu menyangkut isu sains-medis? Isu ini juga jadi perang ekonomi, karena riset ini menyangkut alokasi dana berjuta-juta dollar untuk penelitian dan pengembangannya. Bahkan, ada juga segi bisnisnya: industri kesehatan sudah membidik untung besar jika riset ini berhasil.
Perang kultural, sains, dan ekonomi yang juga keras di Amerika juga menyangkut berbagai segi teori evolusi. Sejak Edward O. Wilson mengumumkan kesimpulannya tentang sosio-biologi pada 1960-an, setelah penelitiannya terhadap semut selama belasan tahun, kontroversi teori evolusi menyeruak kembali ke dalam kesadaran publik Amerika. Tesis sosio-biologi menyatakan bahwa unsur biologi menentukan tata perilaku sosial segala makhluk, termasuk manusia.
Sosio-biologi sebetulnya punya nama buruk semenjak Hitler dan anak buahnya mencoba bereksperimen dalam naungan keyakinan superioritas bangsa Aryan. Dalam pandangan Hitler, unsur biologi menentukan kelas sosial. Bangsa Aryan lebih superior dari bangsa mana pun, apalagi dari bangsa Yahudi, dan karenanya punya hak untuk memimpin bangsa lain, kalau perlu dengan kekerasan. Ini merupakan titik ekstrem perdebatan teori nature dan teori nurture. Di dalam perdebatan ini, pertanyaan utama yang harus dijawab adalah: apakah perilaku manusia akibat bentukan alam (nature), ataukah akibat bentukan pendidikan (nurture)?
Penelitian terkenal antropolog Margaret Mead atas pertumbuhan para pemuda Samoa menjadi teks klasik selama puluhan tahun mengenai “kebenaran” teori nurture. Teori ini kemudian dimanfaatkan, antara lain, oleh gerakan kaum Feminis maupun kaum antirasial. Kaum kulit hitam yang tertindas, juga kaum Yahudi yang selalu diburu dan dibunuh, seolah punya senjata besar untuk menampik mitos kerendahan ras mereka: sebab-sebab alamiah tak lagi dipercaya sebagai dasar bagi diskriminasi yang mereka alami.
Sementara gerakan feminisme mendapat senjata jitu dengan teori nurture untuk menepis anggapan tradisional tentang hakikat perbedaan lelaki dan perempuan, yang menyebabkan diskriminasi terhadap peran-peran sosial-ekonomi-kultural perempuan dalam masyarakat. Dalam bahasa populer, “kodrat” bahwa perempuan harus jadi istri penurut, jadi ibu, dan tak punya peran publik setara dengan lelaki, hanyalah mitos. Jika perempuan mengembangkan sifat-sifat yang sesuai dengan mitos tersebut, itu terjadi karena proses pendidikan/nurture.

Foto: Edward O. Wilson, dari integrasi.science
Dan datanglah Wilson, dengan kesimpulan-kesimpulan ilmiahnya yang “dingin”, menyatakan bahwa teori nature adalah lebih sesuai dengan kenyataan. Evolusi kehidupan manusia, termasuk segala aspek-aspek sosial-budaya mereka, adalah tak lain bagian dari evolusi biologis manusia. Teori sosio-biologi pun kembali mendapatkan momentum. Dalam pemahaman sosio-biologi gaya baru ini, genetika dan neuroscience menjadi dasar yang lebih kuat untuk memahami perilaku manusia. Teori evolusi pun mengalami penyegaran kembali.
Tak mudah, pada mulanya. Wilson sendiri diperlakukan dengan tak adil dalam perdebatan-perdebatan ilmiah di kampus-kampus Amerika pada awal 1970-an yang masih sangat dipengaruhi gerakan counter culture dan semangat flower generation. Kaum feminis dan aktivis gerakan sipil atau antirasialisme terutama merasa sendi-sendi perjuangan mereka terganggu. Wilson dituduh sebagai pembawa paham fasisme baru, pewaris Hitler, dan sebagainya. Sang ilmuwan yang puluhan tahun bekerja dalam kesunyian, tiba-tiba menghadapi hujatan publik yang deras dan keras.
Namun, Wilson adalah juga seorang ilmuwan yang keukeuh, memegang teguh prinsip-prinsip ilmiah dengan segala konsekuensinya. Ia meneruskan penelitiannya, dan kesimpulan-kesimpulannya. Kekukuhannya, memancing kekaguman, di samping membantu perkembangan lebih jauh hasil-hasil temuannya. Wilson kemudian punya pengikut. Tumbuh sebuah generasi baru ahli biologi yang melanjutkan berbagai segi teori evolusi berdasarkan jalan yang telah dibentangkan oleh Wilson. Generasi baru ini terutama mengukuhkan diri pada 1980-an, seiring dimulainya bibit-bibit penelitian besar di bidang genetika (mengarah pada pemetaan genome dan kloning) dan neuroscience.
Generasi baru ini punya kepercayaan diri lebih dalam menerapkan teori evolusi pada semua segi hidup manusia, termasuk keberagamaan dan iman kepada Tuhan. Bagi mereka, berbagai misteri manusia yang masih belum bisa ditembus oleh sains kini bisa dipahami dalam terang teori evolusi mutakhir. Tak semua ilmuwan itu punya ketekunan dan keketatan sikap ilmiah seperti Wilson. Generasi baru kaum evolusionis itu antara lain: Richard Dawkins dengan teori meme-nya (yang antara lain dikembangkan oleh Richard Brodie, dalam bukunya yang telah diterbitkan KPG, Virus Akal Budi), Steven Pinker dengan penjelasan biologis mengenai asal-usul manusia, dan, belakangan, Sam Harris yang berkutat di bidang neuro-sciences, dan Daniel C. Dennett, yang berspekulasi tentang asal-usul biologis keberagamaan manusia. (Buku Dennet, Breaking The Spell: Religion as a Natural Phenomena, juga diulas oleh Luthfi dalam makalahnya.)
Posisi Wilson soal Tuhan sebetulnya sederhana dan jelas, tapi rupanya sukar diterima kebanyakan orang. Baginya, keberadaan Tuhan tak memiliki dalil ilmiah yang cukup. Namun kaum evolusionis bersemangat sesudah Wilson, menyoal Tuhan lebih jauh. Pertama, berkembang paham bahwa kepercayaan pada Tuhan adalah juga hasil perkembangan biologis manusia. Kedua, “kesalahan” iman pada Tuhan ini harus dihentikan dan atheisme mesti dipromosikan –secara agresif. Dawkins telah sejak lama menjadi advokat atheisme yang sangat bersemangat di Amerika.
Sebelum menyoal lebih jauh advokasi atheisme ala Dawkins dan kawan-kawan ini, kita lihat sejenak perkembangan kontroversi teori evolusi gelombang baru ini di Amerika. Kaum evolusionis yang bersemangat itu mendapat lawan yang mencakup sebagian kalangan akademis juga, yakni kaum kreasionis –mereka yang percaya bahwa alam semesta diciptakan Tuhan. Kaum kreasionis ini sering sama agresifnya seperti kaum evolusionis. Mereka mengajukan upaya-upaya sosial dan hukum untuk melembagakan kepercayaan mereka di ruang publik Amerika, khususnya di sekolah-sekolah. Mereka menuntut agar buku pelajaran biologi diubah, agar mencakup juga teori kreasionis sebagai counter teori evolusi yang seolah telah dianggap taken for granted dalam menjelaskan tentang asal mula kejadian alam semesta.
Di universitas-universitas, kaum kreasionis yang terdiri dari para akademisi dan peneliti mempromosikan teori desain intelijen (intelligent design) sebagai penjelasan “alternatif” terhadap terciptanya alam semesta. Asumsi dasar teori ini adalah: kerumitan penciptaan alam sendiri menjadi bukti bahwa ada sebuah desain dalam alam, dan kemungkinan ada “Kecerdasan Agung” di balik desain alam itu. Para pendukung teori ini merancang berbagai program perkuliahan, penulisan buku-buku, dan penelitian-penelitian di banyak universitas Amerika.
Ini membuat geram kaum evolusionis. Salah satu segi yang bikin geram: jatah dana proyek penelitian mereka harus terbagi dengan dana penelitian intelligent design tersebut. Lagi-lagi di sini kita melihat aspek ekonomi dari perang kultural dan pertarungan sains tersebut. Kaum evolusionis membalas dengan keras. Mereka melancarkan kampanye negatif terhadap kreasionisme, menekankan ketaklayakan mereka bercokol di ruang-ruang sekolah dan universitas. Buku-buku dituliskan, berbagai debat publik dan talkshow digelar. Pertarungan paham ini tumbuh menjadi industri tersendiri.
Paling minimal, begitu alur argumen yang berkembang di kalangan evolusionis militan, undang-undang telah menyatakan bahwa agama harus dipisahkan dari pengaturan masalah-masalah duniawi. Secara maksimal, masyarakat mesti menyadari kesesatan kreasionisme. Tak pelak, logis pula jika perang kultural, sains, dan ekonomi ini lantas mengampanyekan atheisme secara lebih tegas.
Dalam alur perdebatan ini, kaum evolusionis mengembangkan argumen bahwa bukan hanya iman dan agama memiliki sebab-sebab biologis dalam evolusi manusia; tapi agama dan iman telah menimbulkan mudharat besar bagi umat manusia. Atheisme, dalam alur argumen ini, bukan hanya jadi satu-satunya penjelasan paling masuk akal tentang alam dan manusia, tapi juga menjadi satu-satunya jalan penyelamatan.
Kehadiran (dan kelarisan) buku-buku macam God Delusion dari Dawkins, The End of Faith dari Sam Harris, dapat dipahami dalam konteks ini. Dawkins, misalnya, bukan hanya memaparkan argumen-argumen mengenai betapa Tuhan adalah tidak mungkin. Lebih jauh, Dawkins menyarankan bahwa pendidikan agama pada anak-anak adalah sejenis abuse (pelecehan) pada anak-anak. Dalam hampir 400 halaman bukunya itu, Dawkins tak mampu melihat sezarah pun manfaat atau maslahat agama bagi umat manusia. Seperti dicatat oleh Terry Eagleton, seorang ahli studi kebudayaan, dalam ulasannya atas God Delusion: “…ini adalah pandangan yang mustahil secara a priori, sekaligus keliru secara empiris.”
Eagleton mengingatkan, “ada jutaan orang yang mengabdikan hidup mereka tanpa kepentingan apa-apa untuk melayani orang lain atas nama Kristus atau Buddha atau Allah, yang dihapuskan dari sejarah” oleh prasangka Dawkins itu. Seperti catatan Rizal Mallarangeng juga, dalam bedah buku Freedom Institute tersebut, ia tak bisa mengabaikan neneknya yang taat beribadah dan nyatanya tulus serta baik hati. Eagleton melihat betapa bagi Dawkins, tak ada satu pun kepercayaan agama, kapan pun dan di mana pun, yang layak untuk mendapat penghormatan apa pun. Dawkins bersikeras menganggap bahkan pandangan agama yang moderat pun harus dibantah dengan keras karena hanya akan membawa pada fanatisme. Bagi Eagleton, ini adalah sebuah pendapat seorang yang sangat terbenam dalam dogmatisme.
Hal ini patut disayangkan. Seperti kata Eagleton, Dawkins benar untuk menghujat fanatisme dan fundamentalisme dalam segala bentuknya. Tapi Dawkins malah melawan fanatisme dengan dogmatisme atheisme. Di Amerika sendiri, berkembang sebuah gerakan yang menamakan diri Positive Atheism. Mereka mendefinisikan atheisme secara lunak, dan lebih ingin menjadikan atheisme sebagai sebuah gerakan positif bagi masyarakat. Dalam gerakan ini, garis keras yang ditegaskan Dawkins dan kawan-kawan sama sekali tak membantu, malah merepotkan.
Teori Evolusi: salah paham dan salah guna
Suatu ketika, dalam sebuah forum ilmiah di sebuah kampus Amerika, Edward O. Wilson mendapat pelecehan saat berdebat dengan Stephen Jay Gould, ahli teori evolusi yang berseberangan pandangan dengan Wilson dalam mendefinisikan sifat kemanusiaan kita. Pelecehan itu dilakukan oleh para mahasiswa beraliran kiri, counter culture, dan kaum hippie. Wilson dilempari telur dan dicacimaki. Wilson kalem saja.
Yang tak kalem justru Tom Wolfe, jurnalis dan novelis flamboyan itu. Dalam sebuah tulisannya tentang perkembangan teori informasi dan teori evolusi, dalam Digibabble, Fairy Dust, and Human Anthill yang dimuat dalam edisi khusus Forbes ASAP, Big Issue 4, October 1999, Wolfe mencela Gould sebagai inisiator pelecehan itu. Ini tuduh serius, dan Wolfe memang sama sekali menganggap remeh Gould karena kejadian itu. Ini keberpihakan yang tak layak.
Untuk adilnya, Wolfe juga meremehkan Dawkins yang ia anggap sebagai pengagum Wilson yang gegabah. Tapi Wolfe telah mereduksi Gould sebagai ilmuwan papan bawah, tanpa menyajikan bukti memadai kecuali insiden terhadap Wilson yang sebetulnya bukan salah Gould itu. Stephen Jay Gould adalah ilmuwan dengan ketekunan ilmiah yang sepadan dengan Wilson. Ia menjadi ahli teori evolusi berdasarkan sebuah obsesi yang sama pada Wilson dan Darwin: obsesi mencari kebenaran.
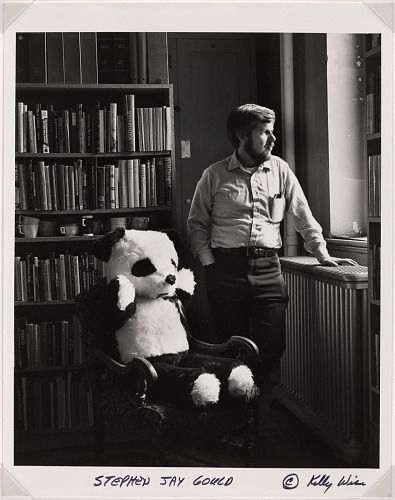
Foto: Stephen Jay Gould (1983), by Kelly Wise. Sumber: npg.si.edu
Seperti Darwin, juga Wilson, Gould telaten menelaah detail. Ketelatenan itu jelas tampak dalam esai-esainya yang terkumpul dalam 10 buku. Sejak Januari 1974 hingga Januari 2001, ia menulis esai bulanan untuk majalah Natural History nyaris tentang apa saja dan selalu dengan perspektif seorang evolusionis sejati. Bagi Gould, evolusionis sejati adalah seorang naturalis sebagaimana Darwin. Seorang naturalis adalah seorang penelaah alam, pencari sekaligus pencatat keindahan dan kebenaran dalam detail-detail yang disediakan alam.
Perjalanan Darwin di kapal Beagles, juga penelaahannya di pulau Galapagos, menunjukkan kecermatan seorang naturalis tulen. Hasilnya, sebuah permenungan panjang tentang hakikat bekerjanya hayat alam berjudul The Origin of Species. Kata “evolusi” baru muncul dalam kalimat terakhir buku ini, dan menandai sebuah zaman baru dalam memahami kejadian kehidupan di alam semesta ini. Teori evolusi ini kemudian dipertegas Darwin dalam The Descent of Man. Seperti bisa diduga, teori ini mengguncang akhir abad ke-19 yang adalah juga waktu berjayanya moralitas Victorian yang sangat konservatif dan agamis.
Gould menulis 300 esai tentang berbagai aspek ilmu hayat yang sering melintas batas ke ilmu kemanusiaan dan budaya, tetap dengan gaya Darwin menelaah keunikan-keunikan kecil setiap spesies di pulau Galapagos. Esai-esai yang terkumpul dalam buku kumpulan terakhirnya, I Have Landed (2003), membahas tulisan tangan kakeknya di buku tata bahasa Inggrisnya pada 11 September 1901; juga, tulisan tangan Netty Huxley kepada cucunya, Julian Huxley, pada sebuah buku; atau menyelami cara pikir Nabokov, baik sebagai sastrawan maupun sebagai taksonomis spesialis kupu-kupu.
Keluasan minat Gould, dan apresiasinya terhadap ilmu-ilmu budaya, menyebabkan ia lebih hati-hati dalam memahami agama. Tak seperti Dawkins atau Sam Harris (atau Hitchens, yang bukan ilmuwan tapi seorang jurnalis) yang gebyah uyah menganggap agama pasti membawa mudharat. Hakikatnya, Gould sama atheisnya dengan Dawkins dan Harris. Tapi ia bisa melihat maslahat agama bagi manusia. Ia mencoba merumuskan relasi ideal agama dan sains dalam istilah NOMA (Non-Overlapping Magisteria). Sains bekerja di magisteria kebenaran empiris; sedang agama bekerja di magisteria kebenaran metaforis dan moral. Dua-duanya bisa bekerja optimal jika tak saling turutcampur.
Rumusan ini tentu masih bisa diperdebatkan. Tapi setidaknya, ini menunjukkan kesadaran dialogis Gould dalam memahami kehidupan manusia.
Gould juga telaten menelaah teori evolusi sendiri. Sejak pertama dilontarkan oleh Darwin, teori ini banyak disalahpahami dan dihujat. Seringkali, hujatan itu lahir dari kesalahpahaman itu. Misalnya, teori ini dihujat sebagai “Darwinisme” akibat pemahaman keliru ungkapan Darwin, “survival of the fittest”. Dalam pandangan umum, kalimat ini diartikan sebagai “yang kuat, yang menang”. Dari sini, ditarik kesimpulan bahwa “Darwinisme” mengajarkan hukum rimba, dan jadi dasar fasisme Hitler. Seperti diulas Jaya Suprana dalam seri buku Kelirumologi, arti sebenarnya kalimat ini adalah, “yang paling cocok, yang paling mampu bertahan hidup”. Artinya, kunci evolusi dan bertahan hidup adalah kemampuan makhluk untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan lingkungan hidupnya.
Gould menelaah salah paham terhadap teori evolusi, dan mengajukan usulan-usulannya sendiri. Selain dalam kumpulan esainya, Gould mencurahkan laporan penelitiannya terhadap evolusi dan teori evolusi dalam buku setebal 1500 halaman, The Structure of Evolutionary Theory. Dalam I Have Landed, ia mengidentifikasi salahpaham umum terhadap evolusi. Dua kesalahpahaman umum tentang teori evolusi Darwin adalah: (1) evolusi dianggap transformasional, padahal yang benar adalah variasional (halaman 247); (2) evolusi di anggap punya arah (makin lama makin baik) dan dapat diramal, padahal tidak (halaman 245).
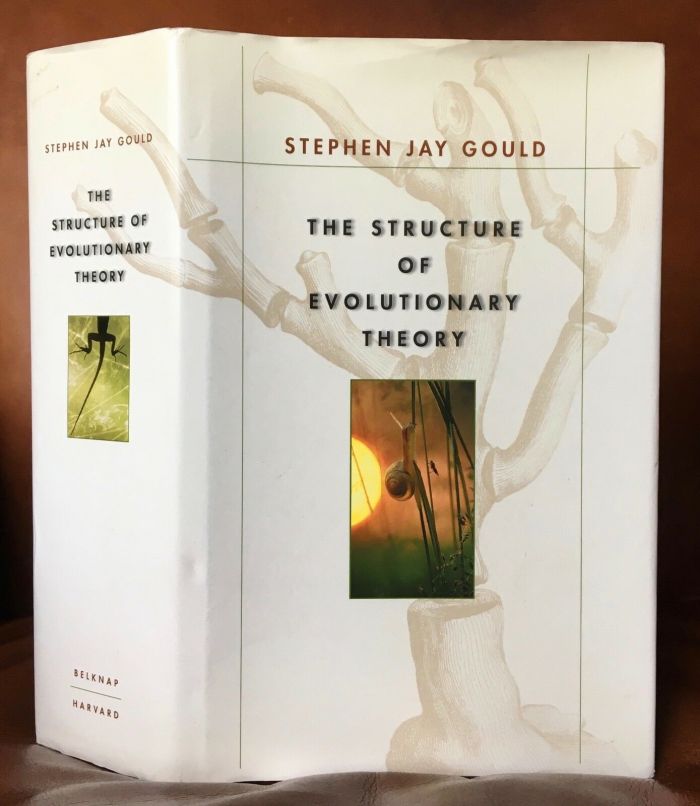
Foto: dari vialibri.net
Anggapan bahwa evolusi makhluk hidup adalah transformasional membawa pada, misalnya, anggapan bahwa monyet melompat jadi manusia atau dinosaurus jadi burung. Tidak begitu, kata Gould. Evolusi adalah variasional: misalkan gajah-gajah di Siberia pada era hangat ada bermacam-macam, ketika era es tiba maka hanya gajah berbulu lebih banyaklah yang mampu bertahan dan berketurunan (halaman 247).
Kesalahpahaman jenis kedua, menganggap bahwa evolusi memiliki arah (makin lama makin baik) dan dapat diramal, tampak menjangkiti kaum evolusionis militan macam Dawkins dan Harris. Evolusionisme, dan atheisme sebagai syarat mutlaknya, mereka anggap sebagai sebuah kemajuan dan arah yang harus dituju umat manusia. Ketika Dawkins mencoba membahas politik global, ia mengungkapkan keyakinannya akan sebuah zeitgeist (semangat zaman) berupa kemajuan yang tak dapat dibendung. Bagi Dawkins, kemajuan itu hanya terganggu oleh “langkah undur” yang kadang terjadi dan kecil saja. “Seluruh gelombang kemajuan ini terus bergerak,” kata Dawkins. “Trend kemajuan ini sungguh nyata, dan akan terus berlanjut.”
Dengan gaya evangelist begini, Dawkins membutakan diri pada berbagai masalah dunia yang telah, sedang, dan akan terjadi: berbagai bencana ekologis seperti kebakaran hutan dan lumpur Lapindo, kelaparan, perang etnis, ancaman perang nuklir dan perang kimia. Jika Anda jeli, berbagai bencana itu memiliki relasi erat dengan kemajuan sains dan teknologi manusia. Jumlah orang yang terbunuh oleh teknologi perang maupun teknologi yang membawa bencana ekologis (seperti DDT, atau nuklir seperti di Chernobyll) di abad ke-20 lebih banyak daripada jumlah orang terbunuh oleh perang agama sepanjang sejarah manusia.
Atheisme sendiri tak bisa “cuci tangan” mengaku tak punya relasi dengan rezim-rezim atheistik yang menyingkirkan agama dengan paksa, termasuk dengan pembunuhan, seperti Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot. Sam Harris menampik kenyataan ini dalam sebuah artikelnya, 10 Myths –and Truths—About Atheism. “Masalah fasisme dan komunisme,” kata Harris, “bukanlah karena mereka terlalu kritis terhadap agama; masalahnya adalah, mereka terlalu mirip agama.” Benar.
Tapi itu tak menutup fakta bahwa atheisme yang dilembagakan dalam sistem politik pernah memburu dan membunuh para penganut agama. Rezim agama dan rezim atheistik pernah punya dosa yang sama. Atheisme belum terbukti mampu mencegah kekerasan ketika dilembagakan menjadi sistem politik. Dengan kata lain, membunuh atas nama agama sama buruknya dengan membunuh atas nama atheisme.
Perang karikatur
Yang terjadi kemudian, memang, adalah perang karikatur antara kaum atheis dan kaum agamis. Masing-masing pihak menciptakan karikatur lawan mereka, dan bersikap atas dasar karikatur-karikatur itu.
Karikatur adalah penyederhanaan, reduksi, dan pelebih-lebihan. Dalam seni karikatur yang baik, teknik penyerderhanaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan saripati kebenaran objek yang digambarkan. Dalam seni karikatur yang buruk, teknik itu justru menjadi alat untuk merendahkan, menguasai, melecehkan, dan pada akhirnya, meniadakan kebenaran objek yang digambarkan. Gampangnya, kartun-kartun karya Sempé, Saul Steinberg, Michael Leunig, atau Sibarani tentu beda dengan kartun-kartun propagandis dari para pendukung revolusi kebudayaan Cina atau karya-karya Harmoko pada 1960-an.
Sam Harris, dalam artikel tentang 10 mitos tentang atheis mendaftar mitos-mitos negatif tentang kaum atheis, dan membantahnya. Namun dalam bantahan-bantahan itu, Harris malah mencipta karikatur-karikatur negatif baru tentang kaum beragama. Poin pertama, tentang mitos “kaum atheis percaya bahwa hidup ini tak punya makna”, dijawab Harris begini: “Sebaliknya, kaum beragama sering cemas bahwa hidup ini tak punya makna dan mengkhayalkan bahwa ketakbermaknaan itu hanya bisa diselamatkan oleh janji kebahagiaan abadi yang melampaui kuburan.” Lho? Bukannya dengan sederhana bilang bahwa “oh, sebaliknya, kaum atheis memandang hidup ini bermakna”, Harris lebih suka ‘meninju’ kaum beragama dulu.
Ini menunjukkan bahwa basis definisi keberadaan kaum atheis bagi Harris adalah “lawan agama”. Dengan kata lain, cara Harris ini justru membuat atheis didefinisikan oleh lawannya. Dalam istilah Buddhis, “kiri sebetulnya terikat oleh kanan”. Gaya Harris ini mewarnai seluruh poin Harris dalam menepis mitos-mitos tentang kaum atheis. Misalnya, jawabannya atas mitos “kaum atheis bersikap dogmatis”: “Kaum Yahudi, Kristiani, dan Muslim mengklaim bahwa kitab suci mereka amat memenuhi kebutuhan manusia sehingga kitab itu hanya mungkin ditulis oleh Tuhan yang Maha Esa. Seorang atheis sekadar seorang yang menimbang klaim itu, membaca kitab suci, dan menyimpulkan bahwa klaim itu bodoh.”
Langsung dua karikatur: gambaran Harris sama sekali meniadakan sosok macam Nurcholis Madjid, Muhammad Iqbal, Isaac Newton, atau CS Lewis. Karikatur yang lebih halus: anggapan bahwa kaum atheis pastilah telah memelajari ketiga kitab suci itu sebelum menyalahkan “klaim bodoh” itu. Memang, bagi Harris, atheisme identik dengan “akal sehat”. Ketika ada atheis yang dogmatik dan membantai orang, Harris menganggap itu bukan karena atheisme tapi karena pikiran mereka telah “terlalu mirip agama”. Bersamaan itu, Harris membuat karikatur bahwa orang beragama sama dengan “tak punya akal sehat”.
Menjawab mitos “kaum atheis adalah arogan”, Harris menjawab “berpura-pura tahu akan sesuatu yang tak diketahui adalah sebuah kelemahan besar di mata sains. Namun, inilah yang jadi urat nadi agama-agama berbasis iman.” Lagi-lagi sebuah karikatur yang, ironisnya, arogan. Dengan kaca mata kuda, Harris hanya melihat kecenderungan sebagian orang beragama yang tanpa bukti ilmiah mengaku lebih tahu hakikat alam daripada kaum ilmuwan (seperti Harun Yahya dan para pengikutnya dalam pseudo-sains laris tentang anti-Darwinisme), lalu menyimpulkan hakikat agama seluruhnya.
Menarik juga dalam membandingkan hal ini dengan sikap Dawkins terhadap teologi dalam God Delusion. Eagleton dengan jitu menulis: “Bayangkan, ada seseorang yang bilang bahwa ia tahu segalanya tentang biologi, padahal satu-satunya yang ia tahu adalah berdasarkan Book of British Birds. Nah, Anda akan dapat membayangkan apa rasanya membaca Richard Dawkins mengomentari teologi.” (Terry Eagleton, London Review of Books, 2006) Menurut Eagleton, Dawkins terhitung paling miskin bekal pemahamannya tentang teologi yang ia cela, karena ia (dan kawan-kawan sesama “atheis profesional”) meyakini tak ada satu pun yang mesti dipahami dari teologi, atau minimal meyakini tak ada satu pun yang cukup berharga untuk dipahami dari teologi. Apakah ini, kalau bukan arogansi?
Ketika membahas mitos “kaum atheis mengabaikan fakta bahwa agama dapat sangat bermanfaat bagi masyarakat”, Harris menjawab: “Bagaimana pun, efek baik agama tentu dapat dibantah. Dalam kebanyakan kasus, tampaknya agama memberi alasan buruk untuk berperilaku baik, padahal alasan yang baik itu ada. Tanyalah pada dirimu sendiri, mana yang lebih bermoral, menolong orang miskin karena prihatin atas penderitaan mereka, atau melakukannya karena kau berpikir bahwa pencipta alam semesta ingin kau melakukannya, akan memberimu pahalah jika kau melakukannya dan akan mengazabmu bila kau tak melakukannya?”
Di sini, Harris sang ilmuwan terjebak menjadi seorang moralis. Lebih menarik sikap Gould setelah memapar salahpaham kedua tentang evolusi. “Sains,” tulis Gould, “tak akan pernah memutuskan moralitas moral-moral.” (I Have Landed, halaman 221). Di titik ini, evolusi bukan hanya telah disalahpahami, tapi juga telah disalahgunakan.
Atheisme: dari salon, hingga revolusi
Mungkin “moralisme atheis” dari Harris dan Dawkins didorong oleh semacam kecemasan dan rasa terdesak. Atheisme sendiri adalah paham yang rawan secara sosial: para penganutnya lebih sering mendapat stigma dan sangsi sosial yang kadang begitu kerasnya, sehingga ada kebutuhan untuk melawan balik sama kerasnya. Lihat saja pengalaman kita sendiri di Indonesia. Atheisme diidentikkan dengan komunisme, dan komunisme diidentikkan dengan pembantaian. Ini adalah salah satu hasil “didikan” Orde Baru yang sangat berhasil terhadap masyarakatnya.
Atheisme tak identik dengan komunisme, sebagaimana komunisme tak identik dengan pembantaian. Saya kenal secara pribadi para mantan PKI yang rajin shalat dan taat ke gereja bahkan saat jadi anggota PKI. Saya juga kenal atheis yang tulus dan baik terhadap sesama. Namun saya juga kenal banyak sekali kaum beragama yang tak masuk dalam karikatur Dawkins dan Harris.
Atheis berasal dari kata Yunani kuno, atheoi, pertama kali muncul dalam sebuah papirus dari awal abad ke-3. Kata atheos dalam Yunani kuno adalah kata sifat yang berarti “tiada bertuhan” atau “godless”. Filosof dan penyair Yunani, Diagoras asal Melos, pada abad ke-5 SM dianggap sebagai “atheis” pertama, karena jadi orang pertama yang tercatat sejarah sebagai pencela doktrin-doktrin agama secara terbuka. Ia tak menuliskan risalah atheisme, tapi banyak kisahnya yang terkenal. Salah satunya, ia dengan sengaja mengungkapkan ritus rahasia agama Elusinian, dan menjadikannya “sesuatu yang biasa belaka”. Artinya, ia sengaja melakukan itu untuk memancing orang sezamannya agar merenungi ulang agama mereka. Ia kemudian dituduh “meresahkan masyarakat”, dan diburu. Negara menjanjikan setalen perak jika ia dibunuh, dan dua talen perak jika ia ditangkap hidup-hidup. Agaknya Diagoras lolos, dan lenyap dari Yunani.
Pada masa Romawi, atheos atau atheis adalah celaan pada lawan debat yang ditujukan pada baik kaum pagan maupun kaum Kristen, dalam persengketaan mereka saat itu. Karen Armstron menulis bahwa pada abad ke-16 dan ke-17, kata “atheis” hanya digunakan secara eksklusif dalam polemik tertutup. Kata ini, menurut Armstrong, dianggap sebagai hinaan –tak ada orang yang bermimpi mau melekatkan dengan sadar kata ini pada diri sendiri.
Baru pada abad ke-18, di Eropa, “atheisme” pertama kali digunakan untuk ajaran atau kepercayaan yang menyatakan diri sebagai penolakan terhadap agama –lazimnya, terhadap agama-agama Semit seperti Kristen dan Yahudi. Kebangkitan renaissance atau Pencerahan sejak abad ke-16 menyebabkan kebangkitan akal budi, rasionalitas, melawan kuasa berlebih agama. Ilmu dan seni menggeliat melawan kemapanan agama dan lembaga-lembaganya, yang mencengkeram masyarakat Eropa sejak abad pertengahan dan mengukuhkan struktur sosial yang feodal saat itu. Ilmuwan dan seniman pun tumbuh, seiring pertumbuhan kelas baru –kelas menengah borjuis, di Eropa. Dalam masyarakat, tumbuh sekelompok orang yang mengedepankan pemikiran bebas dan skeptisisme. Leonardo da Vinci melakukan banyak eksperimen ilmiah sebagai alat menjelaskan kebenaran tentang alam, dan menentang banyak klaim agama.
Di Prancis, pada abad ke-18 itu, terjadi revolusi yang bermula pada pergolakan pemikiran yang sangat panas. Sistem sosial yang ada, termasuk kemapanan lembaga agama (Katolik) yang menyangga sistem kerajaan Prancis dan Eropa pada umumnya, digugat. Para pemikir bebas menuliskan pikiran mereka dan mengumumkannya di salon-salon tempat mereka berkumpul. Walau celaan terhadap agama sudah nge-trend di Prancis dan Inggris pada abad ke-17, kebanyakan mulanya enggan menyatakan diri sebagai atheis. Bahkan, atheisme masih dicela juga oleh para pencela agama itu. Pada awal abad ke-18, Jean Meslier, seorang mantan pendeta, membuang kepercayaannya pada Tuhan dan menjadi atheis pertama yang secara terbuka menyatakan diri sebagai atheis.

Gallileo Before The Holly Office, lukisan abad ke-18 oleh Joseph-Nicolas Robert-Fleury
Kita bisa bayangkan suasana penuh semangat saat itu. Tekanan inkuisisi terhadap Galileo Galillei telah jadi legenda, simbol pertentangan agama dan sains yang sukar didamaikan. Voltaire di Prancis menuliskan esai-esainya yang meledek ketakrasionalan agama dan agamawan. David Hume menuliskan pikiran-pikirannya yang sangat sistematis merumuskan pemikiran Pencerahan, menampik dasar metafisis dalam teologi alam dan mengembangkan sebuah epistemologi skeptis berbasis empirisme. Artinya, ia mendorong orang-orang untuk mempertanyakan segala sesuatu, dengan asumsi bahwa yang tak bisa dibuktikan secara empirisme adalah keliru.
Apakah Paus punya hak mengampuni dosa? Apakah dosa? Apakah raja punya hak berkuasa mutlak? Dari mana hak itu? Bagaimana ia senyatanya menggunakan kekuasaan mutlak itu? Apakah kekuasaan mutlak itu membawa kebaikan pada masyarakat? Mengapa rakyat sangat menderita? Apakah itu takdir? Begitulah kira-kira topik hangat di salon-salon Prancis pra-Revolusi. Ketika ledakan revolusi menumbangkan monarki terjadi di Prancis, revolusi itu memicu gelombang yang sama di seluruh Eropa: gelombang kelahiran negara-bangsa, sekuler, demokratis. Kehidupan modern dalam naungan semangat Pencerahan secara perlahan dari akhir abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19 (khususnya dengan gelombang revolusi di Eropa pada 1848), dan dengan sangat keras, dimapankan dalam kelembagaan politik Eropa.
Revolusi Prancis membawa pula atheisme dari salon-salon ke sphere publik. Atheisme menjadi trend, menjadi life style di kalangan kelas menengah cendekiawan, dan menjadi lebih sistematis. Bahkan sempat atheisme dilembagakan secara paksa sesudah revolusi Prancis.
Untuk menggantikan pemujaan terhadap agama dan gereja, Jacques Hébert dan Pierre Gaspard Chaumette serta para pengikut mereka mencanangkan gerakan cult of reason. Gerakan ini mengambil modus perayaan yang menyertakan aksi-aksi perusakan gereja dan simbol-simbol ketuhanan mereka, dikembangkan pada masa penuh ketidakpastian 1792-94. Beberapa gereja di Paris diubah menjadi “kuil nalar” (temple of reason), dan seorang perempuan diangkat jadi lambang “dewi nalar”. Salah satu penentang gerakan ini adalah Maximilien Robespierre, yang sempat menebarkan teror hukuman mati sebagai penguasa Prancis pasca-Revolusi. Robespierre mendirikan gerakan cult of the supreme being. Namun setelah ia sendiri ditumbangkan, cult of reason menanjak dalam politik. Bahkan pada 24 November 1793, Misa Katolik dilarang di Prancis. Hal ini tak berjalan lama. Rezim Napoleon mengembalikan pengaruh Katolik ke dalam politik Prancis.
Eropa abad ke-19 menjadi lahan subur sistematisasi pemikiran atheisme dan atheistik. Filosof macam Ludwig Andreas von Feuerbach. Sejak buku pertamanya, yang ia terbitkan secara anonimus pada 1830, ia memasalahkan keabadian pribadi. Buku ini membuat dirinya terkucil dari lingkungan akademis. Ia terus menulis buku yang menggali ide atheistiknya, termasuk mengangkat kasus romantis terkenal –percintaan terlarang Abelard dan Heloise. Kita tahu, Abelard adalah seorang pastur cendikia yang menjalin cinta rahasia dengan Heloise. Begitu ketahuan, sebagian karena dibocorkan oleh para lawan polemik Abelard dari kalangan Kristen ortodoks, Abelard dipaksa (konon, dikebiri) untuk hidup selibat. Mudah kita lihat mengapa Feuerbach tertarik pada kisah Abelard dan Heloise ini. Dalam kisah ini tercakup sebuah kasus ketika Kristianitas menampilkan wajah terburuknya dalam melecehkan sesosok manusia penalar.
Tak lama, Feuerbach menerbitkan bukunya terpenting, diterjemah oleh sastrawan George Eliot, The Essence of Christianity. Buku ini menyerang sendi-sendi ajaran kontemporer Kristen di Eropa, dan menyodorkan gagasan atheisme yang cukup sistematis. Inti gagasan Feuerbach adalah manusia menjadi pusat pertanggungjawabannya. Sebetulnya, ia berangkat dari pemahaman bahwa agama (Kristen) memiliki hakikat antropologis. Karena dasar pemikiran ini, Feuerbach justru sering dikritik sebagai atheis yang kurang konsisten. Yang jelas, Feuerbach memengaruhi pemikiran Karl Marx dan Engels.
Pada masa itu pula muncul pemikir-pemikir yang meletakkan sendi-sendi penalaran manusia modern hingga kini: Nietszche, Freud, dan Darwin. Semua mengguncang sendi-sendi agama di Barat. Yang sering luput ditangkap adalah –sebagaimana Feuerbach—berbagai gagasan atheistik mereka sebetulnya kaya nuansa dalam memandang agama. Karl Marx, misalnya, terkenal dengan ucapan “agama adalah opium masyarakat”. Tapi, setelah kalimat itu, Marx sesungguhnya menulis: “agama adalah hati dari sebuah dunia tak berhati, jiwa dari berbagai kondisi yang tak berjiwa.” Seperti kata Eagleton, ini menampakkan sebuah penilaian yang hati-hati dan dialektis, tak seperti penilaian gegabah Dawkins terhadap agama.
Nietszche, yang terkenal dengan ungkapan “Tuhan telah mati” dalam Thus Spake Zarathustra, memodelkan manusia idealnya pada Zarathustra, yang dalam sejarah filsafat merupakan “nabi” monotheisme pertama. Nietszche memang dengan keras menetak “berhala-berhala agama”, tapi ia merindukan kualitas spiritual yang murni. Tak heran jika ia dianggap guru oleh seorang pemikir Islam yang sangat berpengaruh di abad ke-20, Mohamad Iqbal.
Darwin sendiri konon menunda risalahnya yang ia tahu akan mengguncang kepercayaan kaum Kristiani pada (kisah penciptaan) Injil, demi menghormati istrinya yang adalah seorang Kristiani taat dan saleh. Dalam risalah-risalahnya, Darwin tak mengajarkan atheisme sebagai sebuah gerakan moral –apalagi ajaran yang agresif dan cenderung intoleran. Menurut Gould, ajaran Darwin adalah: pandanglah alam apa adanya. Lalu, mengapa ada kebutuhan besar bagi Dawkins dan kawan-kawan untuk menjadi atheis yang agresif?
Atheisme sebagai bisnis
Memang, Dawkins dan Harris getol menyodorkan alasan-alasan moral. Dawkins kini menggalang organisasi yang misinya melawan penindasan bagi kaum atheis di seluruh dunia. Harris, dalam artikel tentang mitos-mitos kaum atheis itu, mengawali argumennya tentang diskriminasi yang dialami oleh kaum atheis dalam politik, dan lebih sial dalam karir politik di Amerika daripada kaum kulit hitam, homoseksual, dan Muslim. Dalam polling Newsweek terkini, hanya 37% warga Amerika yang mau memilih presiden seorang atheis. (Ini mengingatkan pada adegan pemilihan astronot dalam Contact, ketika tokoh yang diperani Jodie Foster kalah karena menganut atheisme.)
Padahal, menurut Harris, kaum atheis adalah kaum yang layak. “Berhubung kita tahu,” kata Harris, “bahwa kaum atheis seringkali merupakan kaum yang paling cerdas dan paling berpendidikan di masyarakat mana pun, penting bagi kita untuk menepis mitos-mitos yang menghambat kaum atheis berperan lebih besar dalam diskursus bangsa kita.” Lagi-lagi, karikatur. Sekaligus peluang bertanya-tanya: apakah motif politik berjalin dengan motif moral yang didengung-dengungkan oleh Harris dan Dawkins?
Lebih dari itu, kita lihat betapa larisnya mereka diundang dalam seminar dan talkshow di Amerika, gara-gara posisi atheistik mereka yang agresif. Eagleton memang jitu ketika mengistilahkan Dawkins sebagai “atheis profesional” –dengan modelnya adalah Bertrand Russel di awal abad ke-20. Dawkins dan Harris menjadi “profesional”, karena ke-atheis-an mereka seakan jadi profesi –mereka dibayar dan menjadi kaya karena itu. Dawkins dan Harris lebih mengabdikan hidup mereka untuk tulisan-tulisan ilmiah populer ketimbang melakukan penelitian ilmiah yang tekun seperti guru mereka, Wilson (yang kini sedang menekuni gerakan penyelamatan keanekaragaman hayati dunia).
Menarik sekali, bahwa “bisnis atheisme” laris seiring larisnya juga “bisnis agama”; atau paling tidak, kedua “bisnis” saling merespon. Menurut laporan khusus The Economist, saat ini bisnis mega-gereja tumbuh pesat. Lima dari sepuluh mega-gereja terbesar ada di Korea Selatan. Yang terbesar, Gereja Yudio Full Gospel, mengklaim beranggotakan 830.000 orang dan bertambah 3000 per bulannya.
Menurut The Economist, pesatnya “bisnis agama” di Korea Selatan itu memberi pelajaran tentang sifat-sifat agama yang sukses di era kini. Salah satunya, karakter “panas” agama-agama tersebut. “Dalam istilah global,” tulis The Economist, “kisah sukses paling menakjubkan di abad lalu adalah agama yang paling tidak intelektual (dan paling emotif).” Fanatisme dan fundamentalisme menjadi bensin yang membakar energi pertumbuhan (aliran) agama-agama paling efektif. Pemerintahan Bush, bisa dibilang, juga menampakkan kecenderungan pada isu-isu “panas” agama dan bisa sangat emosional dalam isu-isu itu.
Di satu sisi, wajar jika lantas reaksi anti-agama seperti atheisme ala Dawkins dan Harris, juga mengambil karakter “panas” yang sama. Tinggal kita bertanya-tanya, apakah pilihan isu “panas” itu sebuah tanggapan reaksioner murni, atau sebuah oportunisme bisnis yang menjadikan isu “panas” sebagai bagian dari brand yang dianggap (dan memang nyatanya) laris.
Ada banyak segi ekonomi-politik yang memang bisa jadi alasan naiknya minat terhadap atheisme. Kalangan peneliti di bidang genetika dan steam cell research, misalnya, jelas berkepentingan untuk menyerang keberagamaan pemerintahan Bush yang memang menghambat dana dan potensi bisnis penelitian-penelitian tersebut. Dan jangan remehkan bisnis buku di kedua kubu ini. Amerika yang sekuler menjadi lahan subur Tim LaHaye dengan seri Left Behind, tentang kiamat dan messiah, yang boleh dibilang hanya setingkat di bawah Harry Potter dalam suskesnya yang bernilai ratusan juta dollar. Belum lagi bisnis televangelist, khutbah di televisi. Tentu ini memancing rangkaian aksi-reaksi. Seperti kata The Economist, tanpa Falwell (seorang pengkhutbah sukses), royalti Hitchens dan Dawkins akan lebih kecil.
Di Indonesia, sedang naik “bisnis agama” dalam dua bentuk: “agama kemarahan”, dengan maraknya industri buku berisi hujatan terhadap Islam liberal, kaum jahiliyah modern, ajaran-ajaran sesat, sekulerisme-pluralisme, dan teori konspirasi Yahudi; yang kedua, “agama harapan”, yang terkait dengan maraknya “bisnis harapan” lain seperti industri buku-buku “how to” yang menjanjikan kekayaan melimpah. ESQ, misalnya, bukan hanya menjadi gagasan yang diterbitkan sebagai buku-buku terlaris, tapi kemudian menjadi gerakan pelatihan kepemimpinan yang bernilai tinggi.
Sejauh ini, reaksi balik dari kaum atheis atau atheistik (jadi, tak terang-terangan atheis) masih sangat terbatas, seperti dalam diskusi Freedom Institute di bulan puasa kemarin itu. Buku The End of Faith telah diterjemah, dan agaknya ada yang tertarik menerjemah God Delusion. Cukup banyak dan marak, memang, reaksi dari golongan atheis dalam negeri terhadap semaraknya semangat agama yang mengeras paska-Reformasi 1998. Namun, semua masih terbatas di ruang-ruang publik kecil, seperti salon-salon Prancis semasa pra-Revolusi Prancis abad ke-18. Sebagai brand, atheisme di Indonesia masihlah berpangsa pasar kecil. Atheisme di Indonesia belum jadi brand seperti CocaCola (yang sudah mencapai branding begini adalah aliran agama tertentu macam ESQ, tarekat Naqsabandiyah, atau MQ sebelum diguncang poligami AA Gym), tapi lebih mirip brand Benetton: kecil, tapi cenderung elitis.***
BERSEPEDA SEPERTI GUNTHER, Esai Setelah 20 Tahun Reformasi
Hikmat Darmawan
*Disampaikan dalam sebuah acara di Makassar International Writers Festival 2018.

Foto: “Berbagai Peristiwa dan Penanganannya, 1998-1999” |Author=Ministry of Defense of the Republic of Indonesia
1998
Kamis, 14 Mei 1998. Saya ingat kereta yang saya tumpangi dari Depok ke Cikini melewati beberapa titik api. Menjelang masuk ke stasiun Pasar Minggu, batu-batu dilemparkan warga ke kereta. Entah apa maksudnya. Para penumpang merundung. Sebagian menjerit panik. Lalu, udara terasa panas. Gerbong melintasi api. Sebagian penumpang berteriak, menunjuk jendela kereta sebelah kiri. Saya melihat keluar, tergetar: mal Ramayana Pasar Minggu terbakar, asap hitam tebal menggumpal di udara terik, hawa panas sampai ke dalam gerbong, dan pikiran saya tak mampu mencerna apa yang saya lihat.
Saat itu, saya berusia 28. Pasar Minggu adalah tempat main saya sejak kecil. Pada 1983, saat saya baru lulus SD, saya bersama ibu saya menonton Di Balik Kelambu, film pemenang FFI karya sutradara Teguh Karya, di bioskop Pasar Minggu Theatre. Pada 1998, kira-kira setahun mengalami haru biru dan jatuh bangun dampak Krisis Moneter 1997 yang meruak jadi krisis semesta di Indonesia, saya salah satu yang mengangankan kejatuhan rezim Soeharto.
Ada banyak jalinan makna dan pengalaman pribadi yang membentuk angan-angan oposisi itu. Pengalaman mengaji tarbiyah dan mencandra kezaliman struktural terhadap umat Islam di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia, bacaan-bacaan humaniora dan ilmu sosial yang saya dapati dari perpustakaan kampus atau tukang buku loak dari Pasar Senen, diskusi-diskusi hangat dengan kawan-kawan kos, pengalaman berganti-ganti pekerjaan, semua membentuk keyakinan bahwa bangsa dan Negara Indonesia saat itu sedang mengalami pembusukan.
Dampak Krismon 1997 memukul kebiasaan konsumtif saya, yang mewarnai pemikiran-pemikiran kebudayaan saya saat itu. Jelasnya, kebiasaan konsumtif membeli komik impor dari AS. Pada sekitar 1994, saya berjumpa toko komik impor khusus terbitan Amerika (DC Comics, Marvel Comics, Image Comics, Dark Horse Comics, Valiant, dll.) di Pondok Indah Plaza, mal Cinere, dan mal Kelapa Gading.
Kurs dollar AS pada 1994 itu ada dalam kisaran Rp. 2000-2500, dengan titik terendah pada 1991, Rp. 1.997. Harga komik impor dari AS saat itu sekitar Rp. 7000-an, rata-rata. Saya berkenalan dengan karya-karya Alan Moore, Neil Gaiman, Frank Miller, Grant Morrison, Dave Sim, dsb. pada periode itu. Di saat saya sedang menemukan suaka intelektual dalam komik-komik “dewasa” yang bicara banyak aspek sains, mitologi, dan masalah sosial di AS/Barat itu, dollar AS meroket.
Rupiah terjun bebas. Saya menyaksikan dengan takjub betapa harga Dollar AS melesat ke atas: 3000, 4000, 6000, 7000, 8000 (mata saya mulai nanar pada saat mencapai nilai ini), 12.000 (!), 13.000, dan 16.000 rupiah!
Harga komik impor dari AS tentu saja melesat. Sebuah judul komik bulanan yang sebetulnya tipis belaka, hanya 32 halaman, terbitan DC atau Marvel, naik harganya, jadi Rp. 12 ribu, lalu Rp. 24 ribu, lalu Rp. 30-40 ribuan. Bahkan seingat saya, pernah ada yang mencapai Rp. 70 ribu. Apatah lagi edisi Trade Paper Back (TPB, Bundel): dari puluhan ribu rupiah, jadi rata-rata Rp. 200-300 ribu.
Belum lagi konsumsi yang lain: belanja buku, nonton di bioskop (iya, saya waktu itu berdalih bahwa menonton adalah pekerjaan saya juga, karena saya mulai menuliskan ulasan-ulasan film dalam perspektif kultural), dan ongkos luntang-lantung blusukan ke pelosok-pelosok Jakarta (dan kadang, ke luar kota juga).
Sejak 1994, mulai terjadi kerusuhan-kerusuhan sosial di berbagai kota di Indonesia. Dari berbagai berita kerusuhan sosial itu, saya mulai mengendus baying-bayang perlawanan terhadap rezim yang menguat. Ketidakpuasan atas keadaan dan kepemimpinan Soeharto yang dirasa telah telah terlalu lama, ketegangan yang menggumpal di udara, tulisan-tulisan yang mengeras di buku-buku sastra, kebangkitan komik indie dengan semangat Punk di Jogja dan Jakarta.
Pada 1996, peristiwa kerusuhan politik yang signifikan terjadi di Cikini, Jakarta: penyerbuan ke kantor PDI yang telah berbulan-bulan diduduki oleh para pendukung Megawati yang secara formal didepak dari tampuk pimpinan partai oleh sebuah kasak-kusuk atas titah Soeharto lewat jalan “belakang”. Soeharto mengeras, dan menyatakan biang kerok kerusuhan 27 Juli 1996 itu adalah “setan gundul”.
Saya ingat, ketegangan telah semakin hamil tua menjelang 27 Juli itu. Pada 26 Juli, sudah santer kabar akan ada “sesuatu”. Para wartawan berkumpul di depan kantor PDI, jalan Diponegoro, dekat stasiun Cikini. Pada dini hari 27 Juli, penyerbuan dimulai. Kawan saya yang meliput dan ada di lokasi pada detik-detik penyerbuan itu, menceritakan betapa batu-batu menghujani gedung partai, dan segerombol orang datang dengan truk, menyerbu ke dalam. Suasana kocar-kacir. Beberapa wartawan digebuki gerombolan penyerbu.

Foto: Dokumentasi Tempo
Jakarta dalam keadaan mencekam esoknya, kerusuhan merembet ke luar, ke jalan-jalan Jakarta dari titik pusat gedung di jalan Diponegoro. Dan itulah titik balik bagi gerakan sipil: beberapa aktivis diculik, sebagian hilang hingga kini. Pemerintah mengumumkan kambing hitam mereka, para “setan gundul” itu: PRD (Partai Rakyat Demokratik), yang memang melakukan perlawanan dengan a.l. mengadvokasi para pendukung Megawati menduduki gedung kantor partai, di samping sejak beberapa tahun sebelumnya menggarap perlawanan-perlawanan di kalangan buruh.
Lalu, krisis moneter itu. Pukulan pertama ke Thailand pada Mei 1997, dan Indonesia pun mulai merasakan api krisis itu dengan segera. Orang-orang belanja panik, baik kebutuhan sehari-hari di berbagai pusat perbelanjaan, maupun dollar AS di bank-bank. Krisis telah menonjok intisari kestabilan rezim Orde Baru: kemakmuran ekonomi.
Semua pembantaian di awal rezim selama 1965-1966 yang kemungkinan mencapai lebih dari sejuta korban; penindasan suara dan hidup orang-orang yang dianggap mengganggu pembangunan; pembantaian Priok 1984, Tragedi Lampung, Petrus (Penembakan Misterius), penenggelaman Kedungombo, diskriminasi sosio-kultural terhadap kelompok keturunan Cina, dsb., semua dimaafkan atas nama kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi. Kesenjangan sosial-ekonomi dimaklumi, karena ada iming-iming “cucuran ke bawah” dan “tinggal landas pembangunan”.
Tapi, ketika harga-harga berbagai kebutuhan sehari-hari naik secara fantastik, kepercayaan terhadap sistem dan rezim pun meruap, mulanya perlahan, dalam bentuk berbagai kebingungan dan kegamanan, lalu semakin cepat dan spektakular. Harga susu bayi pada awal 1998 naik hingga 400%, dan hal ini segera dimanfaatkan oleh para aktivis inti gerakan perempuan pada saat itu yang tergabung di Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia untuk meluncurkan sebuah gerakan politik yang memainkan simbol: Suara Ibu Perduli (SIP) melancarkan demontrasi memprotes naiknya harga susu bayi di bundaran HI, pada 23 Februari 1998.
Demonstrasi pertama itu berlangsung singkat, hanya 30 menit. Aparat segera melakukan pembubaran, dan Karlina Leksono, Gadis Arivia, dan Wiwil (aktivis dari Salatiga), ditangkap, dibawa dalam truk, dan ditahan semalam. Tapi, saat itu, rezim telah kalah oleh “politik susu”: imajinasi politik warga kebanyakan langsung tersentak, dan merambat ke mana-mana –rezim telah dengan jahatnya menelantarkan “ibu” dan “anak” Indonesia, dan menangkapi kaum perempuan yang memperjuangkan tuntutan agar harga susu bayi turun.
Selama bulan-bulan yang genting itu, momentum gerakan SIP semakin kuat, politik simbol dan simbolisasi politik mereka yang berpusat pada “ibu”, “susu”, “bayi”, “anak”, dan “masa depan” dan “bangsa” menjadi imajinasi popular yang semakin membesar. Dukungan massif menggelondong dari semua arah, dan seiring dengan itu, gerakan mahasiswa pun menggelinding, menemukan momentum yang juga semakin membesar.

Foto aksi SIP di HI, 1998 (Dokumentasi Yayasan Jurnal Perempuan)
Saya tak hendak menuliskan sejarah gerakan mahasiswa pada 1998 itu. Saya selalu merasa sebagai “orang luar” dalam berbagai gerakan itu. Beberapa kawan saya memang tampak masih aktif “di dalam” gerakan, walau saat itu gerakan mahasiswa tak tunggal, banyak sisi, banyak ideologi, dan untuk beberapa bulan itu tampak tunggal karena bergerak ke satu arah, melawan satu musuh bersama: Soeharto. Saya memerhatikan dari luar[1], bagaimana keragaman dan ketegangan-ketegangan terjadi pada gerakan mahasiswa.
Mahasiswa di berbagai kota, misalnya para aktivis di ITB, selain Jakarta punya ketegangan sendiri terhadap para aktivis UI. Lha, aktivis UI sendiri tegang pada senat UI. Sesama gerakan mahasiswa di Jakarta juga saling tegang, antara aktivis mahasiswa universitas swasta dengan aktivis di UI. Belum lagi yang orientasinya Islam bertegang-tegang dengan para aktivis berorientasi “Kiri”, “Kristen”, atau “sekular”, dll. Semua, masih tampak satu langkah: bagaimana menjatuhkan Soeharto.
Sidang Umum MPR pada Maret 1998 betul-betul keterlaluan dengan memilih kembali Soeharto dan sehabis putusan tersebut sang rezim tampak justru semakin mengukuhkan kekuasaan dalam upaya mengatasi krisis. Misalnya, memilih anak Soeharto, Siti Hardianti Rukmana (Tutut) Soeharto sebagai salah satu menteri. Di hadapan krisis, rezim Soeharto justru meningkatkan kendali politiknya, hanya berhubungan dengan orang-orang yang dia percaya dalam lingkaran terdekat kekuasaannya. Mekanisme kekerasan lewat tangan militer dan polisi menjadi instrumen alamiah pengelolaan krisis dengan cara demikian.
Setelah penangkapan-penangkapan, penculikan aktivis, pada 12 Mei 1998, terjadi penembakan pada mahasiswa Trisakti. Empat orang mahasiswa tewas: Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, Hendriawan Sie. Peristiwa ini membuka pintu bagi gelombang kerusuhan di Jakarta, yang terburuk di Indonesia pada ujung abad ke-20. Dua hari kemudian, 14 Mei 1998, puncak kerusuhan itu –saat kereta yang saya tumpangi melintasi api di Pasar Minggu dan beberapa kali lemparan batu yang tak jelas benar sebabnya.
Saya bangun kesiangan di kos pada hari itu. Kawan-kawan di kamar lain sudah pergi, entah kuliah, mengajar, atau bekerja di kantor. Hari-hari yang menegangkan menyisakan sesuatu yang aneh, sukar digambarkan, menggantung di udara. Saya mencoba mengontak seorang mahasiswa perempuan yang waktu itu dekat dengan saya, via pager dan telepon koin. Tak ada kabar. Tiba-tiba saya cemas. Dan saya merasa tak bisa sendirian di kos hari itu, menenggelamkan diri dalam tumpukan buku, kaset, atau video dan VCD film koleksi saya. Saya memutuskan ke Cikini, tepatnya ke radio Delta di jalan Borobudur, dekat stasiun Cikini, tempat saya siaran secara rutin seminggu sekali pada saat itu.
Hari telah siang. Di stasiun UI, tanda-tanda hari yang degil telah terbaca. Orang-orang bergerombol di stasiun, di sana-sini terpetik percakapan ada kerusuhan dan mal-mal terbakar. Wajah-wajah cemas atau bingung, baur dalam pandangan bingung saya sendiri.
Kereta yang datang dari arah Pasar Minggu menuju Bogor menyajikan pemandangan aneh: banyak remaja, anak muda, di sela-sela ada orang dewasa juga, yang duduk (atau berdiri) di atas gerbong, membawa barang-barang seperti sepeda yang masih terbungkus plastik atau entah apa lagi. Mereka banyak yang berteriak, riang menganjurkan kami di stasiun untuk ikut menjarah di Pasar Minggu atau mana pun jalur kereta Bogor-Jakarta Kota.
Saya tetap naik kereta ke Cikini, walau merasa ragu untuk lanjut memasuki pusat huru-hara. Dan begitulah, saya melintasi titik api di Pasar Minggu, dan mungkin Tebet juga Manggarai (saya lupa). Turun di stasiun Cikini, hari sudah agak sore. Rasanya sureal, melintasi sebuah dunia yang baru saja rusuh. Mal-mal dijarah, dalam suasana yang telah melunak jadi semacam panggung hiburan rakyat.Beberapa penjarah datang dengan keluarga, ada sekelompok remaja perempuan dan ibu-ibu datang dan berusaha mengambili barang di mal dengan berdandan. Ada pasangan keluarga muda, dengan anak mereka, datang naik motor dan menonton aksi penjarahan yang tersisa. Saya berjalan terus ke arah jalan Borobudur, dan di dekat gedung radio Prambors, melintas anak-anak remaja membawa meja dan kursi dari McDonald. Satu meja bundar begitu besar digelindingkan anak-anak itu, dan saya bertanya dengan wajah yang pasti kelihatan heran benar: untuk apa itu? Mereka tertawa, dan menjawab, kurang lebih, ya diambil saja dulu, Kak.
Di radio Delta, saya tiba, mengobrol, mendapat update lebih lengkap akan situasi, menyerap lebih lengkap situasi Jakarta saat itu. Saya melihat kawan-kawan media sebagai salah satu garda depan gerakan sipil yang penting juga. Gerakan perempuan (dengan simbol kaum “ibu”), gerakan mahasiswa, dan media. Televisi semakin panas. Kabar korban kerusuhan semakin banyak melintas saat hari semakin malam. Horor di mal Plaza Yogya, Klender, Jakarta Timur yang dibakar sehari sebelumnya, pada 13 Mei 1998, semakin terungkap. Diperkirakan 400 orang terbakar dalam mal, saat orang-orang merangsek dan menjarah barang-barang dalam mal itu.
Di titik itu, saya tak bisa menyalahkan gerakan mahasiswa. Setahun sebelumnya, pun hingga sekitar Maret-April 1998, saya meyakini bahwa gerakan politik mahasiswa bukanlah peran strategis mahasiswa menghadapi krisis nasional saat itu. Saya memandang bahwa pilihan menjadi gerakan moral dan gerakan sosial tidak terlalu memadai bagi kapasitas mahasiswa saat itu. Mungkin saya telah mengalami disilusi terhadap anggapan bahwa gerakan mahasiswa lah yang telah menjatuhkan Soekarno dan Orde Lama.
Saya meyakini saat itu bahwa gerakan paling strategis bagi mahasiswa adalah gerakan intelektual: melakukan oposisi-oposisi dengan menggali dan menyebarluaskan pemikiran kritis terhadap rezim. Tentu saja, ada semacam simpati dan perasaan terwakili yang menggetarkan saat melihat gerakan mahasiswa di berbagai kota saat itu mengalami peningkatan momentum. Saya bertanya-tanya: apa saya telah keliru?
Dengan kata lain, saya sempat tergoda untuk menempatkan mahasiswa dengan segala gerakan mereka saat itu sebagai para “pahlawan”, dan bukan “hanya” salah satu pemain atau bahkan pion. Soal jadi pion, kebetulan waktu itu ada beberapa ulasan sejarah melintas terbaca tentang gerakan mahasiswa 1966 yang jadi semacam pion militer/Soeharto dkk., untuk memuluskan kudeta terhadap Soekarno. Hal ini, antara lain, dapat terbaca dalam tulisan-tulisan Soe Hok Gie di masa akhir hidupnya, yang kecewa pada rezim baru. Risiko jadi sekadar pion itulah yang selalu saya kuatirkan tentang gerakan mahasiswa saat itu, yang membuat saya beranggapan posisi terbaik mahasiswa adalah posisinya di dalam “kuil ilmu”.
Saya tergoda untuk menggeser pendapat saya terhadap gerakan mahasiswa itu. Bahwa mereka mungkin saja mereka punya peran strategis di luar gerakan intelektual, yakni sebagai gerakan politik. Setidaknya, saya tergetar oleh keberanian (dan keasyikan) mereka terjun ke jalanan, berhadapan dengan aparat, menuntut sesuatu yang sungguh tabu seumur-umur saya hidup saat itu: turunkan Soeharto!
Apalagi keadaan sungguh degil. Tangan-tangan kekuasaan semakin kasar dalam mempertahankan kekuasaan. Pada 14 Mei 1998, kedegilan itu telah semakin tak bisa diterima oleh orang kebanyakan. Kekerasan dan kekeraskepalaan rezim melampaui ambang batas normal, jika kata “normal” bisa diterapkan di sini. Dalam situasi tidak normal, saya membuka diri pada kerkah dan anomali-anomali menuju keadaan baru. Barangkali saja, gerakan mahasiswa akan jadi anomali sejarah juga –menjadi pahlawan di garis depan pertempuran politik menumbangkan rezim?
Satu hal, gerakan intelektual adalah kura-kura yang merangkak lamban di sisi gerakan massa di jalanan. Baik ketika masa Revolusi Kemerdekaan, mau pun masa Revolusi ’66. Pada hari-hari penuh api di lima bulan pertama 1998 itu, saya pun merasa bahwa yang dibutuhkan adalah sebuah gerakan yang lebih jasmaniah daripada gerakan intelektual. Sudah lewat waktu untuk berpikir, sebagaimana setiap revolusi di tahap jasmaniah (gerakan massa, perebutan kekuasaan, konflik di jalanan) telah melampaui tahap “pikir-pikir” dulu.
Revolusi di tahap ide barangkali sudah seharusnya mencapai puncak pada masa 5-10 tahun sebelum revolusi di tahap jasmaniah bergulir. Untuk kasus Indonesia pada 1998, masa perumusan ide-ide revolusi dan perubahan sistem adalah pertengahan 1980-an. Misalnya, ditandai dengan munculnya LSM dan oposisi sistematis terhadap rezim Soeharto, meruaknya teori-teori kritis dan teori Negara seperti, antara lain, dikenalkan oleh Arief Budiman dan berlanjut dengan kemunculan intelektual organik seperti Mansour Fakih, Stanley (ELSAM), dan Romo Sandyawan pada awal 1990-an. Juga berbagai “studi klub”.
Gus Dur juga harus disebut sebagai salah satu pemberi bentuk ide-ide baru kebangsaan di Indonesia yang penting, baik sebagai pemikir maupun sebagai pemimpin organisasi massa terbesar Indonesia, Nahdhatul Ulama. Kegigihannya menekankan aspek pluralisme keagamaan dan kebangsaan di ranah pemikiran maupun organisasi menjadi salah satu fondasi penting angan-angan revolusi kultural sesudah 1998. Ia, sejak semula, mengambil peran sebagai oposan bagi mainstream Islam politik yang mendekati dan didekati Soeharto pada 1990-an. Pemikirannya beranak pinak ke generasi pemikir muda NU seperti Masdar F. Mas’udi, Ulil-Abshar, Ahmad Basso, dan generasi intelektual NU yang kini berkiprah di ranah gerakan sipil dan sosial.
Pada 1998, khususnya pada bulan-bulan Maret-April-Mei, pembicaraan-pembicaraan intelektual terasa sebagai sebuah kemewahan. Gerakan oposisi bekerja dengan perkakas intelektual yang telah jadi, siap pakai, dan tak ada waktu untuk selalu menguji segi-segi epistemologis dan paradigmatik dari gerakan. Gerakan berjalan, berlari, bukan dengan kebenaran epistemologis tapi dengan keyakinan akan kebenaran-kebenaran praksis. Malah, untuk bisa berlari dalam gerakan di tahap genting tersebut, yang dibutuhkan adalah semacam iman tanpa banyak cingcong.
Setelah penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei, dan kerusuhan Jakarta pada 13-14 Mei, semua elite dan gerakan di tingkat akar rumput seperti bergerak cepat. Pada Senin, 18 Mei 1998, mahasiswa mulai aksi menduduki gedung MPR menuntut mundurnya Soeharto. Sumber-sumber daring saat ini sudah bisa memberikan cukup banyak informasi kronologis gerakan mahasiswa yang sangat dramatis menjelang mundurnya Soeharto itu. Saya ingin sekali masuk juga ke gedung MPR yang saat itu telah dijaga ketat oleh militer.
Saya cukup bingung saat itu. Mau mengaku mahasiswa, jaket kuning saya telah didermakan ibu saya karena toh memang telah kekecilan untuk saya yang rupanya sangat menggemuk setelah lepas kuliah. Mau mengaku wartawan, saya hanya seorang penulis lepas tanpa kartu wartawan apa pun. Seorang kawan, Krisnadi, yang saat itu adalah reporter majalah Gatra mengabari bahwa saya bisa ikut dia meliput ke dalam gedung MPR pada Selasa, 19 Mei 1998.
Pemandangan membanyaknya massa mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang nimbrung kemudian dari pagi hingga malam sungguh menyesakkan dada. Orasi-orasi semakin berani, begitu banyak tabu politik dan tabu kultural dilanggar. Butet menirukan gaya bicara Soeharto. Tentu saja, 3-5 tahun sebelumnya, bisa hilang dia di kolong laut jika berani melakukan itu di depan publik terbuka seperti sore itu.

Sumber foto: dari situs BEM Politeknik Lhokseumawe
Beberapa mahasiswa di panggung orasi memaki-maki Soeharto. Sifat asal saya sebagai seorang kutu buku penyendiri sebetulnya tak merasa genah atas berbagai orasi kasar di panggung itu. Tapi, perasaan merdeka bisa melanggar banyak larangan di udara terbuka di salah satu simbol Negara terpenting lebih terasa membuai dan menyenangkan daripada perasaan estetika saya. Saya malam itu pulang dengan perasaan puas. Harapan itu ada. Rakyat, akhirnya, punya kekuatan yang nyata. Prospek menumbangkan rezim dan mengubah sistem terasa nyata.
Dan ketika pada 21 Mei 1998 pagi semua televisi menyiarkan Soeharto membacakan pengunduran dirinya sebagai presiden, menyerahkannya kepada Habibie, saya dan teman-teman kos bersujud syukur. Saya dengan semacam ke-ge-er-an kosmik menganggap itu adalah sebuah hadiah ulang tahun buat saya yang datang sehari lebih cepat. Sebuah hadiah yang indah.
2018
Dua puluh tahun berlalu, dua generasi telah tumbuh dan menjadi kenyataan baru dalam kehidupan kebangsaan di negeri ini –generasi Y (“millennial”) dan Z hidup dalam sebuah situasi pasca-Nasionalisme yang konkret. Harapan pada dua puluh tahun lalu terasa naif, tapi juga terasa ngangeni.
Sebetulnya, di samping perasaan bahwa harapan-harapan pada 1998 terasa naif, ada juga perasaan ringsek ketika menjalani tahun-tahun sulit di awal Reformasi. Yang paling berat adalah menyaksikan kerusuhan dan konflik horizontal bercorak agama dan kesukuan di tahun-tahun awal yang sulit itu. Kerusuhan Ambon, Poso, juga beberapa kerusuhan di jalanan Jakarta dan beberapa kota di Indonesia, sungguh membuat prospek Reformasi akan gagal semakin terasa menggigit.
Analisis yang lazim di kalangan aktivis gerakan sipil atau kawan-kawan jurnalis adalah memang ada yang “bermain”. Hal ini menumbuhkan perasaan bahwa Reformasi 1998 masih rapuh berdiri di tahun-tahun awal itu. Perasaan yang menerbitkan semangat para aktivis itu untuk terus militan. Persoalan konflik horizontal dengan kekerasan yang kadang massif itu perlu ruang pembicaraan tersendiri. Tanpa mengabaikan persoalan ini, saya hendak fokus pada kiprah kaum intelektual yang terkait persoalan kebudayaan di Indonesia pasca-Reformasi 1998.
Perasaan naif dalam memandang harapan-harapan pada 1998 muncul dengan segera, ketika terjadi berbagai pengkhianatan kaum intelektual di ranah politik praktis dari tahun ke tahun. “Pengkhianatan kaum intelektual” adalah istilah lama dari Julien Benda, dalam bukunya La Trahison Des Clercs yang terbit pada 1927. Saya pinjam di sini dalam pengertian aslinya seperti yang dimaksud Benda –yakni, mendekatnya kaum intelektual yang seharusnya mengabdi pada pencarian kebenaran kepada kekuasaan demi mendapatkan keuntungan material. Saya pun mengambilnya dengan perluasan makna.
Pada tahun-tahun awal abad baru, abad ke-21, banyak sekali tokoh-tokoh intelektual pendorong reformasi (dari kalangan akademisi, aktivis mahasiswa, tokoh agama, dsb.) yang tampak mengecewakan sebagai pemain politik praktis. Tentu saja, banyak yang akan segera menyebut Amin Rais sebagai tokoh paling mengecewakan pasca-Reformasi 1998. Tapi saya hendak menceritakan sebuah percakapan pagi untuk menggambarkan perasaan kecewa yang akut itu.
Pada suatu pagi di awal April 2004, saya yang saat itu tinggal di rumah mertua[2] turun sarapan di meja makan dalam ruang keluarga. Televisi dan koran pagi itu mengabarkan berita penangkapan Mulyana W. Kusuma, komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum), dosen dan aktivis yang dihormati, karena kasus korupsi berupa penyuapan pada seorang anggota BPK terkait audit KPU. Abah Mertua (almarhum) di meja makan dengan masygul berkata, “kalau orang semacam Mulyana W. Kusuma saja tertangkap karena kasus korupsi macam begini, siapa lagi tokoh intelektual yang bisa kita percaya?”
Pertanyaan itu sangat membekas dalam diri saya. Dalam hati, saya selalu mencoba menjawab diam-diam dalam hati: masih ada. Saat itu, saya merasakan kegelisahan demi kegelisahan mengganggu harapan-harapan yang terbangun sejak 1998. Ketika terjadi eksperimen politik luar biasa, boleh dibilang revolusioner, terjadi dengan pengangkatan Gus Dur sebagai presiden RI, kita melihat banyak intelektual masuk ke dalam sistem dan melakukan upaya-upaya reformasi dari dalam.
Seakan tesa dari Julien Benda tak lagi relevan: para tokoh intelektual justru dianggap lebih bermanfaat saat bisa masuk ke dalam sistem, ke dalam struktur kekuasaan, ketimbang hanya memurnikan diri di kuil-kuil kampus dan hanya menulis buku demi buku. Di sisi lain, tesa Benda itu selalu menghantui, setiap kali tampak tokoh-tokoh politik melakukan manuver-manuver politik praktis yang tampak hanya menguntungkan diri atau kelompoknya saja.
Di sisi lain, saya masih memandang dengan cukup bergairah kiprah kelompok-kelompok yang saya anggap generasi baru intelektual Indonesia. Bukan hanya mereka tumbuh dari kelompok yang berkiprah sebagai “intelektual organik” dalam pengertian lama dari Antonio Gramsci, bekerja bersama kaum proletar dalam melawan sistem Kapitalisme. Mereka saya sebut sebagai sebuah jejaring ide yang relatif baru dalam merumuskan kembali ide dan praksis kebangsaan. Mereka bekerja di luar sistem, di luar struktur politik formal, karena mereka bekerja membangun jejaring ide kebangsaan dalam situasi “pasca-nasionalisme”.
Kaum pembangun jejaring ide kebangsaan baru ini bekerja secara kolektif, mengembangkan etos DIY dalam produk-produk kebudayaan mereka, menekuni (seringkali secara tertatih) kerja-kerja spesifik seperti pengarsipan seni rupa, film, atau musik. Atau kegiatan-kegiatan “mulia” seperti membersihkan sampah di pantai, menanam pohon di sebuah wilayah, menghidupkan hak para pejalan kaki. Mereka membangun watak komunitas yang kuat, dan sering kali berakar pada hobi-hobi konsumtif yang dikembangkan menjadi gerakan-gerakan pemaknaan yang militan. Misalnya, komunitas pesepeda, pelari, cosplayer, atau penggemar Karl May.
Pernah menyimak uraian-uraian almarhum Pak Pandu Ganesa, pendiri komunitas Paguyuban Penggemar Karl May (di samping tokoh/aktivis di komunitas Beatles Indonesia, Progrock Indonesia, dan juga komunitas komik Indonesia) tentang pengaruh Karl May di Indonesia? Jejak digitalnya masih bisa dilacak. Menyimak uraian-uraiannya, seakan berwisata menyusuri sebuah versi lain sejarah Indonesia. Gagasan-gagasan keindonesian yang terasa baru dan beragam, sebuah “imagined community” bagi generasi Y dan Z, tampil penuh warna dan buat saya menyegarkan.
Singkat kata, harapan-harapan saya akan perubahan sistem “dari dalam” semakin menipis bukan sekadar akibat kekecewaan pada kiprah para intelektual yang bergerak di dalam sistem, tapi karena “logika” kebangsaan selama dua dekade abad ke-21 ini telah berubah. Dalam situasi “pasca-Nasionalisme” yang dijalani kelompok-kelompok tersebut, Negara dan berbagai sistem (serta narasi) besar tidak diangankan akan tiada, malah diterima sebagai fakta keras biasa. Mereka lebih sibuk bersirkulasi di antara mereka sendiri, melampaui geografi Negara-bangsa. Baik secara fisik, maupun secara maya.
Di titik ini, saya merasa bahwa Reformasi 1998 –yang saya yakini hakikatnya adalah sebuah Revolusi Kebudayaan– sebenarnya punya hasil-hasil konkret. Politik memang tetaplah busuk. Korupsi masih terjadi secara “massif, sistematik, dan terstruktur”. Tapi, daya masyarakat sebetulnya semakin kuat, dalam arti posisi Pusat Sang Negara telah semakin sering direlatifkan oleh tindakan-tindakan politik warga. Setidaknya, melalui lakon dan tindakan-tindakan melalui komunitas-komunitas khas itu.
Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 barangkali adalah sebuah kasus kemenangan “logika” baru bernegara tersebut. Kita tak bisa meremehkan peran politik kerelewanan dalam kemenangan tersebut. Analisis yang lebih mendalam mungkin akan menemukan, misalnya, di balik politik kerelawanan itu ada juga mesin-mesin politik dan modal besar yang bekerja baik secara langsung atau tak langsung. Tapi, analisis yang mendalam juga tak semestinya meniadakan variabel komunitas-komunitas spesifik yang bergerak mendukung pemenangan Jokowi.

Foto: Beritasatu, Suara / SP/Joanito De Saojoao
Dengan kata lain, mesin-mesin politik dan modal itu harus bernegosiasi terus-menerus dengan spontanitas komunitas-komunitas spesifik yang bergerak tanpa struktur organisasi dan kepemimpinan yang jelas. Pada sebuah aksi politik yang spektakular di Gelora Senayan saat hari-hari terakhir kampanye Jokowi, kelompok relawan yang terdiri dari berbagai komunitas spesifik menolak dengan keras kehadiran partai PDI-P yang berusaha mengambil alih panggung. Secara spontan, para relawan tanpa nama di lapangan mencegah penetrasi para anggota partai ke dalam hajatan tersebut.
Tapi, politik kerelawanan ini juga punya sisi gelap. FPI dan gerakan-gerakan keagamaan yang melakukan konsolidasi setelah kekalahan calon mereka, Prabowo, akhirnya juga mampu bergerak dan mengalahkan Ahok dalam Pilkada Jakarta 2017. Puncak Aksi Massa 212 adalah sisi terbalik dari cermin atas kemenangan Jokowi pada 2014. Lebih dari sekadar menghasilkan kekalahan Ahok, Aksi tersebut bahkan mampu menekan lembaga hukum Negara untuk memenjarakan Ahok untuk sebuah tuduhan yang dalam sejarah akan tampak semakin absurd.
Sisi gelap politik kerelawanan ini setidaknya ada dua:
Pertama, para relawan yang bergerak dan mampu mendorong sebuah kemenangan politik nasional pada 2014 tanpa panduan sebuah ideologi yang koheren itu harus berhadapan dengan konsekuensi kemenangan tanpa kesiapan gagasan kebangsaan yang memadai. Dalam kasus Ahok, begitu banyak para relawan dari kalangan kelas menengah menampakkan kepongahan kelas dalam isu-isu penggusuran dan pembangunan infrastruktur di Jakarta. Pada Pilkada 2017, mereka harus terbentur pada kenyataan bahwa “spectre of class struggle” (hantu pertentangan/perjuangan kelas) adalah sesuatu yang ternyata nyata.
Kedua, metode kerelawanan adalah metode yang bisa dikawinkan dengan pendekatan kekerasan dalam segala bentuk (verbal, intelektual, hingga fisik) apabila dipandu oleh sebuah ideologi yang mampu menawarkan ilusi koherensi dalam retorika dan pemanggungan ide-ide mereka –khususnya, jika ideologi itu diakarkan pada paham keagamaan yang disederhanakan.
Apa yang saya sebut sebagai “ilusi koherensi dalam retorika dan pemanggungan ide-ide mereka” adalah praktik-praktik orasi di panggung-panggung jalanan yang dilakukan kelompok-kelompok Islam anti-Jokowi dan anti-Ahok. Jika kita menyimak orasi Rizieq Shihab, misalnya, harus diakui bahwa ia menawarkan sebuah narasi tentang Indonesia yang seakan logis, koheren, dan “benar”. Ia mendongengkan sebuah “kenyataan” yang “tersembunyi” tentang Indonesia dan sejarahnya: sebuah Indonesia yang dipenuhi oleh rencana jahat kaum non-Islam (yang bisa merujuk pada orang-orang Islam yang tak sepaham mereka) untuk menghancurkan Islam, menjual Negara ini kepada kekuatan asing dan aseng, dan selalu dibasahi dan akan terus dibasahi oleh darah umat Islam jika umat Islam tidak melawan.
Retorika demikian lebih berdampak di tingkat emosi dasar (membangkitkan marah, dan kesedihan mendalam) apabila didengarkan tanpa kamera dan monitor: di depan panggung langsung, bersama euphoria kebersamaan yang diikat oleh simbol-simbol identitas seperti baju putih dan takbir setiap sebentar. Dampak berupa kerelaan untuk melakukan apa saja untuk (a) membela Allah, (b) membela agama Allah, (c) membela para pembela agama Allah.
Sedikit lebih jauh mengenai metode kerelawanan seperti yang dipraktikkan dalam gerakan FPI: metodenya dipinjam, tapi ide dan semangat dasarnya tidak.
Misalnya, sikap terhadap Negara. Berbagai kolektif pekerja budaya dan sosial yang mengusung semangat kerelawanan dalam aksi sosial mereka cenderung apatis dan menolak (atau, lebih tepat, mengabaikan) campur tangan Negara dalam kerja-kerja mereka karena mengakarkan diri pada gagasan tentang pudarnya peran Negara. Mereka seringkali cenderung tidak percaya pada sistem besar secara konsisten.
Sementara kelompok seperti FPI, menolak Negara atau manifestasi yang ada dari Negara, bukan karena mereka tidak percaya pada Negara sepenuhnya. Mereka hanya tidak percaya pada Negara yang ada, tapi sepenuhnya percaya pada Negara yang seharusnya ada, yakni sebuah Negara Islam. Bahkan jika mereka mengkhutbahkan gagasan Khilafah, imajinasi mereka tak lebih dari sebuah versi global Negara-bangsa, sebuah Super State. Malah, pada banyak varian dari gagasan Khilafah, imajinasi mereka adalah sebuah Kerajaan global. Poros gagasan dan imajinasi politik mereka masihlah gagasan Negara-Bangsa abad ke-19 dan abad ke-20, atau kerajaan-kerajaan tradisional sebelum itu.
Terhadap jenis metode kerelawanan itu, kepentingan Modal dan Kuasa lama (kelompok yang mendapatkan akumulasi kekayaan dan kekuasaan dalam model sistem ekonomi dan politik abad ke-20, atau setidaknya model Orba), agaknya bisa bermitra. Seperti dulu Soeharto bisa bersekutu dengan kelompok-kelompok Islam politik pada 1990-an setelah melibas kelompok-kelompok Islam politik selama 1970-an dan 1980-an. Kini, Gerindra dan Prabowo pun bisa bersekutu dengan PKS, FPI, maupun kelompok alumni 212 yang mencakup para aktivis Hisbut-Tahrir Indonesia juga yang jelas mempromosikan ide Khilafah.
Bayangkan, bagaimana bisa retorika nasionalisme patriotis dari Prabowo didukung oleh kelompok yang dengan gamblang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah yang mengatasi Indonesia? Sebab, yang satu membayangkan kemenangan bagi sebuah Negara yang kuat, yang satu lagi mengangankan kehadiran sebuah Negara super.
Dalam sengkarut gagasan kebangsaan tersebut, hadir sebuah bentuk lain dari “Pengkhianatan Kaum Intelektual”. Saya musti meluaskan dulu pemaknaan terhadap istilah Julien Benda itu. Hemat saya, “pengkhianatan” tersebut tak lagi dapat dipahami dalam kerangka hubungan intelektual dan Negara secara sederhana dan langsung. Yang hendak saya hitung adalah juga masalah penempatan posisi intelektual sebagai pusat dan poros kebenaran, sekaligus berada mengatasi masyarakat.
Saya akan menggambarkan pandangan ini lewat sebuah percakapan pada 2009. Saat itu, saya membantu Radhar Panca Dahana menjadi ketua pelaksana Mufakat Budaya yang pertama. Ini memang inisiatif Radhar, yang waktu itu didukung oleh Sys NS dan Jockie Suryoprayogo. Radhar memilih steering committee untuk kongres tersebut adalah Rocky Gerung dan Yudi Latif. Sebetulnya, ada juga dalam perumusan masalah yang akan dikongreskan, Donny Gahral dan Yasraf Amir Piliang. Tapi, tim inti pemikirnya adalah Rocky, Yudi, dan Radhar.
Dalam sebuah pertemuan di Cilandak Town Square, saya mencatat diskusi ketiga tokoh ini, yang seringkali ngalor ngidul dan penuh dengan “skala besar”. Banyak hal yang mereka masalahkan dalam kebudayaan dan kebangsaan Indonesia yang mereka lihat. Mereka mengidentifikasi berbagai kegagalan kultural, sosial, filosofis, dan sistem. Saya lupa apa saja diagnosa mereka. Tapi, saya ingat pada satu titik, saya meminta penegasan sikap Mufakat Budaya: “Oke, jadi Mufakat Budaya ini bersikap bahwa Reformasi 1998 telah gagal?”
Dengan segera Rocky mengibas tangannya, dan berkata, kurang lebih, “Nggak usah lah disebut lagi itu Reformasi… tidak pernah ada yang namanya Reformasi… itu hanya istilah yang dibikin-bikin kaum Pemodal untuk melestarikan Kapitalisme mereka….”
Terus terang, reaksi awal saya adalah semacam emosi: enak betul, dia bilang Reformasi tidak ada… ada berapa orang telah kehilangan nyawa, masih banyak orang hilang tak jelas kabarnya, juga betapa banyak produk kebijakan seperti kebebasan pers dan otonomi daerah yang telah dinikmati?
Saya berpikir, saat itu, bahwa ketiga tokoh cendekia di meja itu adalah orang-orang yang tak berperan banyak dalam Reformasi 1998 dan tak kebagian peran dalam panggung politik pasca-Reformasi.
Mungkin saja ada argumen di balik penampikan Rocky itu. Tapi, yang menetap pada saya adalah gestur meremehkan. Konteks percakapan itu sendiri menuntun saya pada kesimpulan tersebut. Di meja itu, kebudayaan dipercakapkan dalam langgam bahasa elitis. Seolah kebudayaan hanya bisa dirumuskan, diartikulasikan, dan dientaskan oleh para dewa-dewa kebudayaan dan kesenian. Bahkan ketika rakyat, atau budaya orang kebanyakan, dibicarakan, semangat dasarnya adalah sebagai objek yang tak paham aspek kebudayaan dari perilaku mereka sehari-hari.
Hal ini saya ingat kembali, ketika beberapa kali melihat Rocky tampil ke permukaan terkait dengan Pilkada 2017 dan kini saat secara agresif di berbagai media manggung sebagai filsuf (“profesor”) anti-Jokowi dan anti-Jokower. Dua isu kontroversial ia lontarkan: bahwa hoax adalah bentuk oposisi yang patut dibela, dan bahwa Kitab Suci adalah fiksi.
Saya pribadi menganggap perdebatan soal makna “fiksi” dan “fiktif” menurut Rocky Gerung sudah terhitung debat kusir. Yang saya sesalkan dalam masalah “kitab suci adalah fiksi” adalah ungkapan yang mengaburkan makna leksikal (makna dalam kamus) tentang “fiksi” itu, dengan segala perkakas retorika filsafatnya, dilontarkan Rocky dalam kerangka membela ucapan Prabowo secara agresif. Termasuk, bagaimana ia memulai argumennya dengan penempatan para pendukung Jokowi sebagai “dungu”.
Ungkapan semacam “dungu” ini cukup konsisten dilontarkan Rocky Gerung terhadap orang-orang yang menyanggah pendapatnya, seperti saat melontar soal hoax sebagai mekanisme kritik terhadap rezim. Yang saya soal di sini tentu saja bukan masalah kepatutan bicara, tapi lebih ke soal cara berpikir: kata “dungu” yang diperlawankan dengan susunan retorika filosofisnya adalah sebuah mekanisme menghentikan percakapan dan segala dialektika yang mungkin timbul dari percakapan tersebut dengan cara menempatkan lawan pendapat sebagai inferior atau tidak layak diperlakukan setara.
Di samping kiprah Rocky Gerung, yang sering membuat saya terkenang perasaan tak nyaman di meja diskusi persiapan Mufakat Budaya itu adalah kiprah Mufakat Budaya yang terus dilanjutkan Radhar hingga ke istana, menemui Jokowi. Tampak sekali bahwa tokoh-tokoh yang dilibatkan dalam percakapan-percakapan dengan Jokowi dalam naungan Mufakat Budaya itu adalah perwakilan dari gagasan-gagasan kebudayaan para elite era 1970-an sampai 1990-an.
Beberapa kali saya mendengar langsung atau membaca ungkapan Radhar mengenai pentingnya sebuah “helicopter view”, yang berarti pandangan dari ketinggian untuk memandang bangsa ini secara keseluruhan. Tapi, melanjutkan ungkapan tersebut, pertanyaannya adalah: helikopter siapa gerangan yang dianggap layak dan absah menyampaikan pandangan-pandangan dari ketinggian tersebut?
Jika hendak menimpali dengan metafora juga, saya lebih suka memilih metafora ini: Gunther Holtorf, seorang pelancong profesional dari Jerman, bersepeda keliling Jakarta dan menyusun peta yang seringkali dianggap paling akurat. Gunther pertama kali menyusun peta Jakarta pada 1977, dan secara berkala datang kembali ke Jakarta untuk melengkapi atau memperbaharui petanya. Pada edisi cetakan ke-12, petanya telah mencakup area Jabodetabek dan memakan 385 halaman.
Saya percaya, pemetaan kebudayaan dan gagasan-gagasan kebangsaan saat ini justru akan lebih memadai jika dilakukan di tingkatan jalanan. Bersepeda, menyusuri perlahan jalan demi jalan, kecil atau besar, gang-gang atau jalan raya, memerhatikan bangunan-bangunan dan penanda lokasi, lebih memungkinan sebuah pengetahuan, pemahaman, dan nantinya gagasan yang lebih lengkap atas sebuah kota, dibandingkan sebuah pemandangan dari ketinggian helikopter. Kalaulah sesekali diperlukan pemandangan dari ketinggian, lebih baik pakai teknologi GPS yang mengawinkan penyorotan satelit atas bumi dan informasi lokasi langsung lewat gawai di tangan kita.
Maka, dalam konteks demikianlah, saya menganggap bahwa pendekatan-pendekatan elitis dan “dari ketinggian” terhadap kebudayaan dan masyarakatnya adalah sejenis pengkhianatan kaum intelektual. Pengkhianatan jenis ini bisa dilakukan oleh kaum cendekiawan yang berada di dalam mau pun di luar sistem. Hal ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap semangat zaman.
Jika ada hal yang saya bisa peras dari pengalaman menatap dari dekat (walau, tetap sebagai “orang luar”) gerak-gerik Reformasi 1998 dan serba-serbi yang terjadi hingga kini, ialah beberapa kata kunci yang menggambarkan modalitas budaya kita setelah Revolusi Kebudayaan pada 1998:
Partisipatif, bukan elitisme.
Kesetaraan, bukan ketinggian.
Siasat, bukan cetak biru.
Ketiga kata kunci itu menyiratkan bentuk-bentuk politik kewargaan yang lebih terdistribusikan secara luas, pembentukan pengetahuan bersama yang mengakarkan diri pada keterlibatan dengan hal-hal konkret di dalam masyarakat, sebuah upaya serta kerja-kerja sosial dan kebudayaan yang tak termampatkan hanya dalam sekelompok kecil Begawan.
Hal ini bisa punya implikasi luas. Misalkan, salah satu amanat UU Pemajuan Budaya yang disahkan oleh DPR pada 2017, Negara menjadikan Kebudayaan sebagai dasar bagi pembangunan. Langkah perwujudan amanat ini adalah pembentukan sebuah Strategi Budaya Nasional. Langkah ini dimulai dari perumusan masalah-masalah kebudayaan dan gagasan-gagasan untuk jadi solusi pada tingkat lokal-desa yang akan terus mengerucut ke atas.
Langkah tersebut akan diarahkan menuju penyusunan sebuah rumusan Strategi Budaya Nasional yang diolah serta diampu oleh sebuah Dewan Kebudayaan Nasional yang merupakan perwakilan para pengampu kepentingan di bidang kesenian dan kebudayaan dari seluruh daerah di Indonesia. Setidaknya, langkah-langkah ini menampakkan sebuah semangat partisipatif dan asumsi kesetaraan para pengampu kepentingan seni-budaya di Indonesia.
Akan lain soal ketika, misalnya, perumusan Strategi Kebudayaan Nasional itu dilakukan oleh para Begawan dengan semangat mencipta sebuah cetak biru kebudayaan yang bersifat top down atau mengucur dari atas ke bawah. Secemerlang apa pun para Begawan itu, risiko pengabaian kenyataan masalah-masalah di tingkat akar rumput menjadi terlalu besar. Dengan kata lain, pendekatan cetak biru para Begawan akan selalu berisiko terlalu berjarak dari situasi konkret masyarakat.
Risiko ini terasa semakin genting di masa kini, karena antara lain perkembangan pesat teknologi internet yang berjalin dengan situasi kebebasan media. Jalinan ini mengakibatkan adanya sirkulasi informasi dan pengetahuan yang lebih kompleks dan pesat daripada di masa pra-1998. Sirkulasi pengetahuan yang lebih leluasa ini mengakibatkan setiap “arahan” sepihak dari “atas” dalam hal kesadaran dan pemaknaan hidup sehari-hari akan selalu bisa dengan cepat terbatalkan oleh dinamika dan negosiasi-negosiasi pemaknaan di lapangan.
Sederhananya: kaum Begawan boleh bikin cetak biru, kaum jelata di bawah bisa dengan mudah menampik sambil bilang ape lo?!?
Kaum elitis itu mungkin sekadar produk zaman mereka. Jika wadah kewargaan adalah waktu, saya lebih memilih menjadi warga masa kini daripada warga masa lampau. ***
[1] Saya beruntung, karena walau berada di “luar”, saya masih bisa berhubungan secara alamiah (lewat “nongkrong” atau ngobrol spontan) dengan para aktivis senior yang masih kiprah di kampus. Malah, beberapa kali masih diundang jadi pembicara dalam diskusi-diskusi di kampus saat itu.
[2] Agar jelas, tepatnya adalah “mantan mertua”, karena saya berpisah pada 2007.
BUKAN SOAL AGAMA, TAPI ATAS NAMA

“Our Freedom Can’t Wait!” Muhammad Speaks. Source: CBS (From http://www.baas.ac.uk)
Saya sebetulnya tidak setuju, dengan retorika yang kini jadi seakan kebenaran umum pada sebagian orang: “Jangan bawa-bawa agama ke dalam politik!”
Saya tidak setuju pernyataan itu dalam banyak segi. Pertama, kalimat “jangan” di situ sungguh patronizing, dan memaksakan nilai tertentu pada lawan bicara. Nilai sekularisme, nilai yang menyatakan bahwa agama dan politik adalah dua wilayah yang beda, terpisah, dan tak boleh bercampur.
Dalam nada pemaksaan tersebut, ada semacam pemutlakan: bahwa pemisahan agama dan politik (kenegaraan) adalah satu-satunya kebenaran, sumber kebaikan, dan sebaliknya, pencampuran politik dengan agama adalah sebuah keburukan dan pembawa mudharat nyata. Apa benar?
Sebelum sampai pada kesimpulan benar atau tidak preposisi itu, saya kok lebih suka mulai dengan menyorot dari segi praktik. Sederhana saja: mau dilarang-larang, di-“jangan-jangan”, nyatanya banyak orang membawa begitu saja agama ke ranah politik praktis di Indonesia. Lha, bukankah tak ada halangan bagi kelompok macam FPI, atau partai-partai macam PKS, PPP, PKB, untuk membawa-bawa agama dalam kiprah politik mereka? Percuma berpegang pada “jangan” jika memang tak ada yang dilarang dalam soal ini.
Beda soal dengan, misalnya, India. Atau Turki. Di kedua Negara itu, Sekularisme diakui secara resmi dan gamblang sebagai dasar bernegara. Ada regulasi (pengaturan) Negara untuk menjamin agar mereka tetap Sekular. Tapi, ternyata, bahkan dengan regulasi yang gamblang pun, kedua negara tersebut tak mampu membendung politik berbasis agama.
Di India, ada masanya partai kaum fundamentalis Hindu, BJP, mendominasi pemerintahan India, dan membikin banyak ketegangan dengan banyak kelompok politik di India. Turki, kita tahu, sudah dianggap mengalami Islamisasi di bawah rezim Erdogan. Lucunya, baik menurut kaum konservatif Islam di dunia (termasuk, banyak juga, di Indonesia) maupun oleh kaum Hawkish yang cenderung anti-Islam di Amerika, misalnya, sama saja rupanya: rezim Erdogan adalah rezim “Islami”. Kelompok fanboi (sebetulnya, banyak juga fangirl-nya) Erdogan memaklumi saja jika rezim Erdogan tidak/belum benar-benar menggugat secara radikal dasar negara sekular Turki.
“Politik adalah siasat,” begitu retorika lazim para ustadz untuk soal seperti Erdogan. Dan itu, kawan, adalah sebuah doktrin agama juga, dalam Islam, yang popular dalam ajaran dakwah ala Ikhwanul Muslimin. (Buat yang buru-buru mengaitkan gerakan Ikhwanul Muslimin, hey, itu bukan pendapat saya: Ikhwanul Muslimin punya sejarah panjang, dan bermula dari kehendak membebaskan dunia Islam dari kolonialisme –saya menghormati banyak pemikiran dalam gerakan tersebut, walau saya juga menampik banyak hal dari gerakan itu).
Lagipula, jangan salah, toh dari sebelum Indonesia ini resmi lahir, taruhlah seperti dipraktikkan oleh Tjokroaminoto di masa Hindia Belanda, agama telah digunakan sebagai instrumen penting kepolitikan. Tjokro menciptakan sebuah wahana penting gerakan politik kebangsaan, yakni Syarikat Islam (SI). Memangnya “Islam” di situ, apa? Nama orang? Ya, nama agama lah. Bukan hanya nama, prinsip-prinsip keagamaan pun dibawa serta dalam gerakan yang sangat penting bagi gerakan nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20 itu.
Lho, malahan, SI juga jadi rahim kelahiran Komunisme di Indonesia yang berujung pada lahirnya PKI yang sampai kini masih jadi momok bagi banyak kelompok Islam itu. Dan selama PKI berkiprah, banyak lah unsur agama dibawa-bawa, entah secara positif maupun negatif.
Teruskan saja sejarahnya, walau lintasannya sekilas-sekilas: pada masa Orba, agama juga sering dibawa-bawa, baik oleh rezim penguasa, maupun berbagai kelompok oposisi. Dalam kampanye era Orba pun demikian: paling meriah jika Pemilu, PPP dan Golkar akan “perang ayat”, menggunakan ayat-ayat Qur’an untuk menjatuhkan lawan dan menggiring suara pemilih. Menyebalkan? Nista? Atau hiburan? Katarsis? Mungkin semua itu.
Apa artinya, jika saat ini isu SARA menjerat Sang Petahana Pilkada DKI 2017, lantas kita berteriak-teriak “Jangan bawa-bawa Agama dalam politik!” Praktis, ucapan itu seakan abai pada kenyataan, keberartiannya gugur sejak diucapkan.
Mending, kita berpikir secara praktis juga: bagaimana agama bisa berperan secara positif dalam politik praktis?
Sebab, segala jurus fitnah (lewat hoax dan pelintiran), ujaran kebencian, ledakan-ledakan emosi akibat isu agama (atau, dianggap isu agama) hanyalah satu dari sekian banyak cara beragama. Dan sekian cara beragama itu akan bergantung pada gagasan pelaku masing-masing cara beragama itu tentang apa itu “beragama”.
Ketersinggungan kaum pengguna retorika Islam “keras” terhadap Ahok itu kan bukan hal baru, sudah sejak semula Ahok jadi gubernur DKI, atau bahkan sebelum itu (waktu masih jadi calon wagub bersama calon gubernur Jokowi), sebagian umat Islam seakan meradang betul ada “orang kafir” bakal memimpin umat Islam.
Pangkalnya adalah gagasan bahwa status keagamaan resmi seseorang bersifat menentukan secara mutlak kelayakan seseorang memimpin sekelompok umat manusia –kelompok umat manusia yang, coba tilik lebih dalam, dipandang juga hanya sebagai sekumpulan pemeluk resmi satu agama. Begitulah cara beragama orang-orang yang menolak Ahok (atau Jokowi, atau siapa pun) sebagai pemimpin politik atau birokrasi dengan alasan status agama sang calon.
Apa tak ada cara lain beragama? Tentu saja ada, bahkan banyak. Intinya, bisa saja seseorang pemeluk taat Islam justru meyakini agamanya menitah dirinya untuk, misalnya, “menyerahkan sesuatu pada ahlinya”. Atau, seperti Ibnu Taimiyah, yang berpendapat bahwa intisari agama adalah keadilan –maka beragama yang baik, ideal, dan “benar” adalah menegakkan keadilan di atas menegakkan status resmi agama si pemimpin dan umat.
Taimiyah berpendapat, “Lebih baik suatu negara dipimpin oleh seorang kafir tapi adil, ketimbang oleh seorang muslim yang tidak adil/zhalim.” Tentu saja, akan ada yang bisa membelokkan adagium ini ke dalam kasus Ahok, “Nah, Sang Petahana, menilik kasus-kasus penggusuran rakyat kecil di Jakarta, sudah bukan muslim, zhalim pula!” Bukan itu poinnya, Akhi, Ukhti!
Poin saya, adalah: ada cara beragama yang lebih baik daripada cara beragama yang gampang marah, terpaku hanya pada status agama resmi seorang calon gubernur dan para calon pemilih, dan gemar menebar fitnah serta sembarangan memakai podium agama seperti mimbar Jumat untuk menghujat dan menghujat dan menghujat seseorang.
Jangan bawa-bawa agama? Tidak. Demi Tuhan, bawalah agama ke arena politik! Seperti Martin Luther King dan Malcolm X membawa agama ke arena politik untuk mengilhamkan keadaan yang lebih baik bagi semua umat manusia. Seperti Nabi Muhammad SAW menggugat kesenjangan dan penindasan kelas yang dikukuhkan oleh penguasaan Agama dan sumber-sumberdaya Agama di tangan para elite saja.
Bawalah agama ke dalam politik seperti Gus Dur, Cak Nur, Gus Mus, Tjokro, Soegija, Njoman S. Pendit, Hamka, Munir, Bambang Widjoyanto dan banyak tokoh dengan kadar keagamaan berbagai-bagai yang penuh yakin menyusun Indonesia batu demi batu. Seperti Quraish Shihab berdoa di sebuah panggung politik demi menenteramkan para relawan di sebuah Pilpres, di tengah hujan fitnah dari orang-orang seperti Jonru.
Seperti KH. Zainuddin MZ berdakwah tentang kebajikan di tengah pentas Kantata Takwa. Seperti Emha dulu menggemuruhkan Lautan Jilbab di berbagai kota di Jawa, di saat jilbab dilarang rezim Soeharto dan jadi simbol perlawanan atas ketakadilan struktural masa itu. Agama bisa jadi ilham kemanusiaan. Agama, ya, Islam pun, yang banyak disangka buruk sebagai perusak dunia modern kita, bisa jadi ilham kemanusiaan dan kebangsaan kita.
Mungkin, Cak Nur (Nurcholis Madjid) memang jitu. Ia menyarankan sekularisasi Islam. Yang orang sering luput, Cak Nur pada saat yang sama, menolak sekularisme. Gagasan “sekularisasi” dari Cak Nur adalah mengolah dunia dalam logika dunia, dan tidak dengan mudah menyerahkan segalanya pada yang gaib. Antum a’lamu biumuuri dunyakum, kata Nabi SAW, Kalian lebih paham urusan-urusan duniawi kalian.
Lalu di manakah letak dan peran agama, dalam gagasan Cak Nur? Ia ada dalam ranah etis –agama menjadi sumber penilaian benar-salah dan baik-buruk bagi seseorang (atau sekelompok orang) dalam menjalani kehidupan dunia yang diarahkan menjadi keadaan lebih baik bagi manusia. Agama tidaklah memberi arahan bibit mana yang lebih unggul untuk panen jagung terbaik, tapi Agama lebih berperan, misalnya, pada membentuk kepercayaan bahwa seorang ilmuwan dan petani harus bekerja sebaik-baiknya untuk mendapatkan panen jagung terbaik demi kemaslahatan orang banyak.
Jadi, cara beragama yang lebih positif terhadap kemanusiaan itulah yang perlu masuk dan merangsek ke ruang percakapan politik dan publik saat ini. Jadikan berkompetisi saja, antara “agama” yang serba-marah-marah dengan agama yang serba berkah dan penuh rahmah dan marwah. Bawalah agama, yakni “agama” yang menjunjung tinggi keadilan, keadaban, kesejukan, ke dunia politik kita yang kotor ini. Bawalah agama yang etis.
Bukan “agama” yang penuh caci maki, gampang mengancam bunuh, serba membenci kanan kiri, dan memakai fitnah demi kemenangan. Buat saya, cara beragama penuh kebencian itu adalah penyalahgunaan agama: agama dijadikan alasan saja untuk membenci dan memenuhi hasrat perang yang pokoknya menghanguskan, menyingkirkan, menistakan orang dan kelompok yang beda. Buat saya, itulah penistaan Islam yang sesungguhnya.
Masjid dan Keretakan Bangsa
#arsip Ini tulisan saya, kalau tak salah, pada 1997. Saya tak yakin juga ini pernah dimuat di mana. Membaca tulisan ini, saya jadi mesem-mesem sendiri: saya “anak musholla” banget ya 🙂
Pasar murah sembako di masjid? Transaksi jual beli di rumah Allah? Secara iseng, orang bisa bilang bahwa itu versi harfiah dari ungkapan Akbar S. Ahmed dalam Posmodernisme dan Islam : masjid bersaing dengan mal!
Tentu saja maksud Ahmed bukan itu. Ia kurang lebih menyoroti betapa mal menjadi kuil manusia modern dalam memusatkan hidupnya. Dalam masyarakat muslim, masjid memiliki sejarah panjang sebagai pusat sosial, dan kini tergerus oleh mal-mal.
Mal adalah kuil pemaknaan manusia modern terhadap hidup mereka yang didefinisikan oleh ekonomi. Bukan kebetulan jika kita, Indonesia Orde Baru (dengan mengambil Jakarta sebagai pusatnya), menampakkan gairah belanja luar biasa yang ditandai maraknya mal-mal.
Menurut MEDIA INDONESIA (16/1/1997), total tanah untuk area mal-mal di Jabotabek yang telah maupun akan dibangun adalah 4.132.480 m2. Sebelum krisis, sedang antri pembangunan mal di Ancol, Bintaro dan BSD, masing-masing seluas 200.000 m2 atau lebih. Semua itu lahir dalam suatu Orde yang menjadikan ekonomi sebagai panglima dalam melakukan nation building menjelang milenium ketiga.
Dan justru ekonomi lah yang mengkhianati Indonesia Orde Baru!
Reformasi = pertanyaan
Krisis telah (selalu) membawa hikmah luar biasa. Siapa sangka, krisis yang semula ‘sekedar’ jatuhnya rupiah di bulan Agustus akan membuka jalan bagi desakan amat kuat untuk reformasi ekonomi-politik (juga sosial, dan akhirnya – atau mulanya? – budaya) yang telah lama diidamkan, dan disuarakan, oleh sebagian orang berakal sehat di negeri ini sejak lumayan lama.
Reformasi bermula dari pertanyaan, dari ketidakpuasan pada apa yang ada – pada status quo. Jika suatu pertanyaan dibiarkan tumbuh secara wajar, reformasi akan tumbuh, insya Allah, secara wajar pula. Jika pertanyaan muncul karena paksaan keadaan, reformasi bisa jadi juga akan tumbuh secara ogah-ogahan, merasa terpaksa, dan bisa jadi menuntut biaya (amat mahal, malah).
Di samping itu, pertanyaan yang lahir dari keadaan yang mendesak bisa jadi akan berujud pertanyaan-pertanyaan panik. Maka pertanyaan-pertanyaan salah kaprah bisa tumbuh subur, menyesatkan, mengarahkan pada reformasi yang seolah-olah saja. Tercakup dalam “pertanyaan salah kaprah” adalah pertanyaan yang benar, tapi diutamakan lebih dari porsi seharusnya.
Secara kasar, pertanyaan dasar dalam krisis kita bisa disederhanakan jadi soal “siapa” dan “kapan”, atau “apa” dan “bagaimana”. Dalam panik karena pukulan krisis moneter yang tak habis-habis, banyak yang bertanya “siapa” (padahal lebih penting bertanya “apa”) dan “kapan” (padahal lebih penting bertanya “bagaimana”).
Pada awal krisis, misalnya, populer pertanyaan “siapa yang jadi biang keladi krisis”? Mencari kambing hitam sempat jadi keasyikan nasional: sebagian menunjuk para spekulator, dengan mengikuti suara galak Mahathir yang menghujat Soros. Sebagian lain menunjuk para konglomerat. Hingga kini pun, kambing hitam masih laku.
Dalam talk show Liputan Khusus SCTV, 25/2/97 lalu, Ekky Syahrudin sang wakil rakyat masih yakin membatu bahwa krisis moneter akibat ulah spekulator. Ia percaya CBS, karena agaknya yakin ungkapan “jurus yang akan mematikan para spekulan”.
Beberapa waktu sebelumnya, ramai soal Sofjan Wanandi dan CSIS. Dalam acara peluncuran program KAUM di Masjid Sunda Kelapa, 27/1/97 lalu, Syarwan Hamid menyebut “tikus-tikus” yang menyebabkan krisis sedemikian parah begini. Di beberapa tempat, masyarakat memutuskan bahwa “Cina”-lah masalahnya. Pers juga ikut disalahkan karena dianggap memperparah situasi dengan “menyebarkan berita-berita yang tak benar dan membingungkan”. Mungkin sebentar lagi, para ahli yang meragukan CBS atau orang-orang yang skeptis pada calon wapres pun akan ditunjuk sebagai penyebab rupiah tak stabil.
Kita terus berkutat pada pertanyaan “siapa”. Apalagi saat krisis ekonomi bergeser menjadi tuntutan reformasi politik demi efektifnya reformasi ekonomi. Ramailah orang menyoal siapa pemimpin bangsa untuk masa depan, siapa wapres (yang dianggap jabatan strategis untuk reformasi politik ke depan). Jelas, dalam politik praktis, “siapa” adalah soal amat penting. Tapi di tengah euphoria pertanyaan “siapa”, ada bahaya masalah reformasi ekonomi dan politik tergemboskan maknanya. Semua orang bicara “reformasi”, semua merasa mengerti, tapi tanpa sadar meluputkan soal “apa” di balik reformasi.
Padahal, mementingkan “apa” dalam agenda reformasi akan memberi kerangka kerja yang lebih tahan lama dan fleksibel. Siapapun wapres atau presiden kita, agenda reformasi yang jelas mestinya tetap berjalan dan dijalankan. Siapapun yang berkuasa, sistem ekonomi kita mestilah diupayakan selalu produktif dan bersih dari korupsi, kolusi dan manipulasi; siapapun pemimpin bangsa, sistem politik harus diupayakan selalu partisipatif dan transparan. (Memang ada saat “siapa” jadi pertanyaan penting, khususnya dalam politik; tapi saya ragu apa Indonesia sudah sampai ke titik itu?)
Sejalan dengan itu, pertanyaan “kapan” tak sepenting “bagaimana”. Ya, penting memang soal kepastian kapan rupiah stabil. Tapi soal kurs cuma kulit dari masalah ekonomi, apalagi jika masalah ekonomi itu sudah bermatra politik-sosial, bahkan budaya, seperti di Indonesia kini. Tak ada formula ajaib untuk seluruh masalah itu. Setiap pilihan punya konsekuensi yang mesti ditanggung bersama oleh bangsa Indonesia (dan itu biasanya berarti lebih banyak ditanggung oleh rakyat kebanyakan).
Tapi desakan “kapan” mungkin akan menendang jauh-jauh soal “bagaimana”. Keinginan mendapat hasil segera bisa membuat kita dengan panik “menjual jiwa kepada iblis”: pakai apa sajalah, yang penting rupiah stabil besok!
Retak, rekat
Kepanikan tersebut amat terasa pada saat ikatan kebersamaan runtuh, saat semua orang merasa tak bisa mengandalkan orang lain dan harus menyelamatkan diri sendiri. Kiamat belum tiba, tapi psikologi “ibu melupakan anak yang disusuinya” sudah terhidang di depan kita.
Saat rush belanja beberapa waktu lalu, sesuatu yang dahsyat terjadi: “orang lain” (mencakup orang-orang Irian yang mati kelaparan, orang-orang kampung yang sama butuhnya pada susu dan sembako tapi tak punya duit, para penganggur korban krisis moneter) jadi demikian abstrak bagi para pelaku rush, hingga derajat tiada. Saat orang tarik urat berebut minyak goreng, tak ada “Indonesia”, yang ada hanya perut sendiri.
Bangsa ini memang telah retak sejak lama. Senjang demi senjang telah membelah bangsa ini: senjang antara yang kaya dan yang miskin, senjang antara yang berkuasa dan yang tidak, antara elite dan rakyat alit; belum senjang antara idealitas kenegaraan dan praktek birokrasi di lapangan, senjang antara cita-cita/harapan dengan kenyataan, antara yang simbolik dengan yang keseharian.
Contoh mutakhir dari senjang antara yang simbolik dengan yang realistik adalah gerakan cinta rupiah dan cinta tanah air. Masyarakat, kita tahu, kini menderita ketakpercayaan yang akut pada Pemerintah (nyaris setiap ada kebijakan pemerintah soal krisis moneter, respon pasar adalah rupiah jatuh atau capital flight ). Tapi apa respon kita? Tipikal: bikin stiker, bikin acara jor-joran, bikin slogan – simbol, simbol dan simbol! Sementara mal-mal tetap ramai, dan valentine night di kafe-kafe tetap penuh.
Masyarakat, bangsa, yang retak perlu direkatkan kembali. Masyarakat jangan dibiarkan jadi keping-keping yang terserak tak berdaya. Disintegrasi jadi soal yang krusial untuk kita saat ini: kita tak ingin nasib Lebanon, Yugoslavia, Aljazair (dan, kalau mau jujur, negeri kita di jaman PKI) menimpa kita; kita tak ingin antar tetangga jadi musuh dan masyarakat terjerumus dalam kegelapan teror. Itu tak bisa diupayakan sekedar lewat simbol dan upacara. Dan itu juga tak bisa melalui keasyikan Pemerintah mengupayakan sendiri semuanya, mengasyiki penjagaan kemapanan perannya sebagai pusat, termasuk dalam menyelesaikan soal krisis kini.
Berhentilah mengidentikkan stabilitas pemerintahan sama dengan stabilitas masyarakat. Berilah ruang seluas mungkin pada masyarakat untuk mengupayakan sendiri kebersamaan mereka – ajak masyarakat berdialog soal apa saja yang mungkin menimpa mereka, dan bagaimana mengatasinya; jangan tetap membudayakan “bermain dalam gelap”, yang bertumpu pada keharusan pasifnya masyarakat.
Community centre
Di situlah perlunya community centre (pusat kemasyarakatan) yang aktif dan efektif. Dalam situasi normal pun selalu perlu ada lembaga-lembaga yang bisa jadi perantara individu dengan Negara. Ruang bagi masyarakat untuk mengupayakan kebersamaan perlu dilembagakan. Dan untuk Indonesia, masjid-masjid bisa berperan demikian.
Sebetulnya, bukan cuma masjid, tapi pusat-pusat ibadah. Masjid menjadi strategis karena memang umat Islam adalah mayoritas. Lebih strategis lagi jika, seperti ajakan Amin Rais dan Adi Sasono dalam peluncuran KAUM (Komite Aksi Untuk Masyarakat korban krisis moneter), masjid tak membatasi aksi sosialnya hanya pada umat Islam saja, tapi juga pada umat agama lain. Betapapun, rakyat adalah rakyat, korban adalah korban dan pertolongan mesti selalu diberikan.
Secara teoritis, masjid, atau pusat ibadah, akan menjadi lembaga yang efektif untuk memberi kubah pemaknaan bagi individu-individu, anggota masyarakat, yang kehilangan orientasi dalam realitas yang retak seperti kini. Saat semua yang stabil, taken for granted, tak bisa diandalkan lagi, seseorang perlu membangun lagi pemaknaan baru, atau menyegarkan kembali pemaknaan yang telah ia miliki. Dan melalui pemaknaan bersama, kata “Indonesia” akan kembali berarti, kongkrit dan hadir dalam keseharian. Masjid/pusat ibadah bisa mengakomodir proses itu.
Secara praktis, tentu saja banyak masalah. Orang, misalnya bisa menyorot risiko primordialisme yang bisa berkembang jadi tribalisme yang populer di jaman globalisasi ini. Dalam hal masjid, di lapangan masih muncul kendala warisan lama: “masjid NU” atau “masjid Muhammadiyah” masih jadi kategori kerja para aktifis masjid. Belum lagi soal-soal SDM, soal-soal kemampuan organisasional dan manajerial yang di kebanyakan masjid bagai makhluk dari planet lain: asing dan cenderung dimusuhi (atau setidaknya tak dianggap penting).
Ya, banyak masalah. Tapi itu tak mengurangi nilai strategis masjid/pusat ibadah dalam situasi krisis kini. Bermula dari penyaluran sembako, masjid-masjid bisa mengembangkan diri jadi pusat kegiatan masyarakat yang aktif dan efektif: jadi penyalur dana masyarakat, pusat pertemuan, kegiatan makan bersama, bahkan tempat memupuk ketrampilan dalam rangka mempersiapkan diri menyongsong wajah ekonomi yang berubah akibat bantua IMF dan globalisasi.
Dalam bahasa seorang rekan: daripada para pengangguran (yang notebene banyak yang intelektual) itu turun ke jalan, kan lebih baik kumpul-kumpul di masjid…. ***
Pelajaran Kebangsaan Baru
#arsip Ada masanya, saya mengkliping (dengan secara fisik menggunting koran dan menyimpannya) tulisan-tulisan saya yang dimuat di media massa. Sekarang, entah di mana kliping-kliping itu. Awal saya menulis di media massa, kebanyakan membahas soal-soal kebudayaan dengan fokus masalah Negara-Bangsa, dan politik Islam, atau mengulas buku-buku sastra dan kebudayaan secara umum. Ini salah satunya, tulisan tahun 1997, saya lupa dimuat di mana. Waktu itu, terasa ada yang sedang mematang, seperti akan terjadi sesuatu yang besar, di Indonesia. Kekuasaan sudah busuk, semua terasa sedang was-was menunggu entah apa. Sekarang, kita tahu apa yang terjadi kemudian.
Eep Saefullah, dalam acara buka puasa Lembaga Studi Ilmu Sosial 18 Januari 1997, mengungkapkan beberapa pendekatan dalam menyikapi kasus-kasus kerusuhan baru-baru itu. Eep memisalkan kasus-kasus tersebut sebagai “bom waktu” – dan ada dua sikap terhadap “bom waktu” itu: yang pertama – yang lebih populer dalam sikap-sikap resmi Pemerintah dan ekspos media massa – adalah mencari siapa “penyulut bom” tersebut; yang kedua, mencari penyebab adanya “bom” itu dan siapa (atau apa) pembuatnya.
Menurut Eep, sikap kedua lebih penting dilakukan. “Sang penyulut” hanyalah meledakkan “bom” yang telah tersedia belaka. Sementara pertanyaan utamanya adalah: mengapa Indonesia menjadi lahan yang begitu subur bagi “bom-bom waktu” tersebut?
Jika sikap kedua diambil, masih menurut Eep, maka ada dua penjelasan yang mungkin dikemukakan: penjelasan teologis dan penjelasan ekonomi-politik. Penjelasan teologis beranggapan bahwa terdapat unsur-unsur yang potensial radikal dalam doktrin dan sistem keimanan agama yang tersangkut kerusuhan. Eep mencontohkan penelitian oleh Kompas tentang “agama protes” di Pesisir Timur Jawa untuk penjelasan pertama. Sedang penjelasan kedua – yang menjadi pilihan Eep – beranggapan bahwa soalnya terletak pada masalah struktural.
Keberbedaan, identitas
Yang masih luput dibicarakan adalah penjelasan problem identitas. Barangkali tak ada hubungan langsung antara amuk massa di Situbondo, Tasik dan Kalimantan dengan problem identitas. Tapi sentimen (krisis) identitas – dibahasakan atau tidak – sesungguhnya lebih mudah kita temui dalam keseharian kita. Bahkan seringkali penjelasan identitas menjadi penjelasan common sense dalam “analisa warung kopi” tentang berbagai gejala ketegangan sosial di sekitar kita (misalnya pengaitan kerusuhan dengan isu Kristenisasi; atau kebencian terhadap etnis Cina). Karena itulah – karena ia ‘sekedar’ sebuah “analisa warung kopi”, mungkin, problem identitas menjadi penjelasan yang kalah pamor dibanding penjelasan lain. (Agaknya yang paling aman adalah tidak menggunakan/memaksakan suatu pendekatan tunggal)
Tapi problem identitas lah benang merah yang membuat kerusuhan di Situbondo, Tasik dan Kalimantan relatif unik dibanding kerusuhan 27 Juli: jika pada kerusuhan 27 Juli alasan yang dikemukakan oleh para pelaku kerusuhan adalah politik, pada tiga kerusuhan di daerah tersebut terangkat alasan yang berbeda. Di Situbondo dan Tasik: pelecehan agama (di Tasik, tidak langsung menyangkut pelecehan agama – tapi penganiayaan aparat polisi/Negara terhadap “aparat” agama). Di Kalimantan: konflik etnis, antara Dayak dan Madura. Kerusuhan di Timor Timur beberapa waktu lalu juga mengangkat soal (pelecehan) agama.
“Agama” dan “etnis”, adalah kata yang merujuk pada keberbedaan yang primordial. Kenyataan bahwa perbedaan tersebut bisa meletupkan kekerasan massal menunjukkan bahwa sekedar retorika anti-primordialisme saja tidak cukup. “Primordialisme” telah menjadi kata yang bersifat rapalan, sedemikian rupa, sehingga bobot persoalannya menjadi diremehkan dan dientengkan. Seolah, seseorang (atau suatu masyarakat) dengan pilihan terhadap modernitas akan dengan mudah meninggalkan kenyataan-kenyataan primordialnya.
Kenyataan primordial adalah sesuatu yang menghujam dalam pada diri seseorang. Kenyataan primordial adalah sebuah rujukan akan keberbedaan yang mendasar. Ketika nasionalisme – sebagai representasi proyek modernisme – datang, ia ingin menggusur keberbedaan itu, menggusur segala yang dinisbatkan sebagai “alam dan warisan tradisional”, dan menggantikannya dengan sebuah “alam” baru, entitas baru. Nasionalisme menginginkan keberbedaan primordial jadi tak relevan – loyalitas seseorang terhadap bangsa dan negara lah yang penting.
Apakah “bangsa”? Sebuah imagined community, “komunitas yang dibayangkan” (Anderson, 1983). Apakah “Negara”? Organisasi yang menaungi dan mengkoordinasi imagined community tersebut.
Cara nasionalisme menangani keberbedaan primordial mengalami evolusi. Pada mulanya keberbedaan ditangani dengan menyodokkan sikap yang secara naif memandang nasionalitas sebagai sebuah entitas yang bulat, sebuah gestalt, yang utuh dan tanpa kompromi mensubordinasi kenyataan-kenyataan primordial. Itulah nasionalisme-nya Mohammad Yamin dan Soepomo (dengan model negara integral-nya). Nasionalisme macam itu masih populer – tentu dengan berbagai adaptasi dan modifikasi agar tetap up to date (paling tidak secara retoris).
Penanganan keberbedaan yang kedua menghadirkan nasionalisme yang lebih halus dan apresiatif terhadap keberbedaan primordial. Pendekatan itu relatif belum melembaga di Indonesia, walau mulai populer setelah sekian lama hanya dikenal di kalangan budayawan dan ilmuwan sosial saja. Pendekatan itu sering diistilahkan sebagai multikulturalisme.
Sayangnya, multikulturalisme belum bisa keluar dari perangkap gestalt. Ia dibangun berdasarkan asumsi adanya sebuah budaya pusat. Seperti kata James Donald dan Ali Rattansi: dalam praktek, multikulturalisme gagal mengenali hirarki kekuasaan dan legitimasi sehubungan dengan keberbedaan yang masih terus berlanjut; multikulturalisme mendefinisikan budaya lain (yang bukan pusat atau bukan ”budaya nasional”) dengan oposisi A : bukan-A, ketimbang pembedaan A : B, A : C, atau A : n …(Donald & Rattansi, 1992). “Bukan-A” adalah berarti – dalam praktek – adalah subordinat, perlu “disesuaikan”, “dididik” dan “dibina”.
Pandangan gestalt memerangkap karena ia luput menangkap kenyataan partikular. Individu, dengan segala kenyataan primordial dan non-primordial yang melekat dalam dirinya, adalah kenyataan partikular. Nasionalisme membawa orang-orang Madura ke Kalimantan. Di sana, atas nama Nasionalisme gestalt, orang Dayak dan orang Madura dituntut untuk meniadakan sentimen kesukuan. Tapi ketika terhampar masalah kongkret berupa jurang sosial-ekonomi, seorang Dayak awam – hampir secara instingtif – menengok kepada sesuatu yang ia rasa bagian dari dirinya sejak lahir: ke-“Dayak”-annya. (Barangsiapa beranggapan sentimen etnis, dan agama, sebagai “warisan lampau”, cobalah lihat bahwa massa yang terbakar di Situbondo, Tasik dan Kalimantan adalah kebanyakan kaum muda…)
Sentimen macam itulah yang dengan mudah dibakar, terutama ketika dikombinasikan dengan problem sosial-ekonomi-politik yang nyata, plus hadirnya “penyulut” yang pandai. Keberbedaan (primordial) akan lebih rawan jika ia ditekan-tekan, disembunyikan, atau secara naif dianggap minimal – bahkan dianggap tak ada – peran dan fungsinya dalam masyarakat. Itulah problem identitas yang menggayut di udara, dan sewaktu-waktu bisa meledak, baik di tingkat individu maupun di tingkat sosial.
Menerima keberbedaan
Bukannya saya menyarankan primordialisme. Tapi manusia (individu, komunitas) selalu membutuhkan identifikasi dalam modes of being-nya. Kenyataan primordial adalah subyek identifikasi yang asasi, dan merupakan modal untuk membangun identitas. Identifikasi adalah sebuah titik berangkat bagi seseorang atau suatu masyarakat/komunitas dalam perjalanan untuk menemukan “Siapa dirinya?”
Dalam identifikasi tersebut, keberbedaan (difference) menjadi bagian yang penting. Pembedaan adalah cara yang paling mula untuk menegaskan garis dan warna identitas. Barulah setelah kontras garis dan warna itu ditemukan, harmonisasi antara berbagai difference, berbagai garis dan warna itu, bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bagaimanakah harmonisasi warna ada jika yang tersedia hanyalah satu warna belaka? Nasionalisme gestalt menuntut kita untuk meloncati aneka garis dan warna, lantas hidup dalam seragam.
Cara kita menangani difference akan menunjukkan kesiapan kita untuk hidup sebagai sebuah bangsa. Sudah saatnya kita mengevaluasi kembali hidup berkebangsaan kita. Jika “bangsa” diikat oleh kesatuan-kesatuan khusus (misalnya, kesatuan geo-politis dan bahasa), sejauh mana kesatuan/penyatuan itu dapat bekerja; dan bagaimana kesatuan/penyatuan itu dilakukan? Apakah dengan menekan difference sekeras mungkin? Atau justru dengan mengapresiasinya? Lalu jika “bangsa” diikat oleh tujuan bersama, apakah “tujuan bersama” itu? Masih relevankah pengertian kita akan hal itu? Dan, lagi-lagi, bagaimana tujuan tersebut kita capai?
Pendidikan dasar kita adalah karikatur tentang betapa kaburnya materi kebangsaan kita bagi kebanyakan orang, dan betapa kekaburan itu menggagalkan hadirnya manusia-manusia dengan jati diri yang kuat. Kekaburan itu hanya menghasilkan sosok-sosok yang identitas mereka sebatas nomor KTP, sosok-sosok massa yang begitu rentan terhadap berbagai perubahan.
Lembaga pendidikan resmi kita mengajari anak-anak bangsa dengan seragam. Di sekolah umum mereka dilucuti dari kenyataan-kenyataan primordial mereka. Mereka diseragamkan: pakaian, cara berpikir, bahkan target-target (jangka pendek) pendidikan mereka – mereka ditempatkan dalam situasi di mana kepandaian matematika, misalnya, akan membuat seseorang dianggap lebih baik (mekanisme “juara kelas”), sedangkan kepandaian bermain suling tak berarti apa-apa. Kenyataannya adalah: tidak semua orang bisa menjadi “juara kelas”. Tapi karena itu satu-satunya nilai utama, maka berarti, secara realistis, lembaga pendidikan kita telah menghasilkan sekumpulan besar (mayoritas) anak-anak yang bukan juara kelas, anak-anak yang kalah.
Dalam situasi serba seragam, serba terpusat itu maka nasionalisme berhenti sebatas hafalan dan basa-basi. Ia tak lagi menyentuh masalah-masalah kongkrit manusia pelakunya. Dan ketika wacana-wacana lokal menggeliat ingin bangkit, nasionalisme menjadi serba canggung.
Saya kira sudah saatnya nasionalisme kita menerima difference apa adanya. Perlu ada pergeseran tekanan dari “Tunggal” menjadi “Bhineka”. Biar kita bersepakat untuk sama dalam hal-hal yang mendasar saja (misalnya, dalam hal geo-politis di pelataran internasional; atau kesamaan lingua franca bahasa Indonesia). Aneka warna kultur, ekspresi, dibiarkan beragam. Masalah nasionalisme kontemporer bukanlah bagaimana menghilangkan difference, tapi bagaimana mengatasi inequalities (ketaksetaraan/ketakmerataan) dan injustice.
Tentu saja, untuk masalah itu ada banyak sekali yang mesti kita lakukan.
Renungan
Masalah kerusuhan massa bukan cuma terletak pada sisi “kerusuhan” saja, tapi juga pada sisi “massa”-nya. Dan saya percaya bahwa “massa” seharusnya diperhadapkan dengan “identitas”: sosok individu – dengan jati diri yang kuat – adalah benteng kuat untuk menghadapi “massa”.
Di sisi lain: “Identitas tak pernah merupakan sebuah pusat yang tetap,” kata Avtar Brah (dalam Donald & Rattansi, 1992). Ia selalu berproses. Demikian juga dengan nasionalisme, jika ia ingin menjadi bagian dari identitas manusia-manusia pelakunya.
Nasionalisme Seolah-olah
#arsip Pertama kali saya menulis untuk rubrik Opini media massa, dan dimuat, adalah pada 1993-1994. Saat itu, saya banyak menulis esai dan opini masalah kebudayaan, dengan fokus pada wacana kritis tentang Negara-Bangsa, Identitas, dan juga Islam dari sudut pandang kebudayaan. Yang ini, tulisan 1995, dimuat di rubrik Opini Republika. Tanggal, lupa. Jadi sedih mikir Republika saat ini. Juga: wah, ini tulisan waktu saya usia 25, ya. Sekitar 20 tahun lalu. Banyak yang telah berkembang, tentu.
Tahun ini (1995), Indonesia semarak dengan peringatan 50 tahun kemerdekaannya. Menurut saya, lebih tepat jika dikatakan bahwa 50 tahun itu adalah usia “Indonesia” memiliki jasad wadag (yaitu, negara-bangsa Republik Indonesia). Sedangkan “Indonesia” sebagai sebuah konsep, telah lahir ketika terjadi konsensus kesatuan nasional pada Sumpah Pemuda 1928. Sementara pada tanggal 20 Mei 1908, yang biasa kita rujuk sebagai hari Kebangkitan Nasional, “Indonesia” belumlah lahir. Yang ada pada masa itu adalah kesadaran sekelompok (kecil) orang, di bumi Nusantara, bahwa kaum pribumi terjajah perlu memiliki sebuah identitas yang berbeda dari sosok identitas yang telah diterakan oleh kaum kolonial. Tapi justru di situlah semua ini bermula: pada kebutuhan akan identitas (kolektif maupun individual), yang merentang menjadi kebutuhan akan bangsa dan negara.
Maka nasionalisme memanglah masalah identitas sejak semula. Dan saat ini, masalah identitas terasa semakin sulit.
Identitas kebangsaan seringkali kita lekatkan pada dua hal: pada keberadaan negara-bangsa; dan pada budaya bangsa. Dalam kenyataan, pelekatan itu sesungguhnya ilusif, lebih merupakan pretensi yang diterapkan secara tendensius. Kedua konsep kunci tersebut tidaklah innocent, pemaknaan dan penggunaannya perlu dipersoalkan kembali.
Negara-bangsa
Ungkapan “saya orang Indonesia” umumnya, pertama-tama, berarti “saya warga negara Republik Indonesia”. Artinya, sebuah pelekatan identitas/identifikasi seseorang dengan sebuah negara-bangsa (nation state).
Tapi konsep negara-bangsa sedang menghadapi gugatan dari dua jurusan: dari jurusan konseptual dan jurusan kenyataan global kontemporer. Negara-bangsa adalah sebuah konsep pola organisasi politik modern. Negara-bangsa adalah sesuatu yang historis — ia hadir untuk menstrukturkan eksistensi orde internasional, yang dasar-dasarnya diletakkan sejak abad XVI di Eropa (Dorodjatun Kuntjoro-jakti, 1991). Orde internasional itu sendiri bermula dari sebuah asumsi teori ekonomi klasik mengenai kebutuhan akan adanya pembagian tugas ekonomi di dunia, agar terjadi pertukaran ekonomi antar negara (Arief Budiman, 1995).
Perkembangan ilmu-ilmu sosial kini berusaha semakin memahami nature negara-bangsa. Dalam usaha pemahaman tersebut, semakin tampak bahwa “bangsa” adalah sebuah simbol, ide, yang difungsikan untuk sebuah kebutuhan pragmatis: memberikan batasan, lokasi, bagi sebuah organisasi politik bernama negara. “Negara” sendiri, dalam kenyataan, tumbuh menjadi sebuah kekuatan yang otonom, umumnya bercirikan birokrasi dan penguasaan kekuatan pemaksa (militer).
Negara amat berkepentingan untuk melestarikan eksistensinya. Satu hal lagi, negara juga amat berkepentingan dengan penguatan kapital. Secara historis, ini logis. Bukankah asumsi awal kehadiran negara adalah kebutuhan akan adanya orde internasional untuk memudahkan pengembangan ekonomi? Dalam praktek, khususnya di dunia ketiga, tampak pula bahwa negara sering menjadi partner kekuatan-kekuatan kapital internasional (seperti, berbagai korporasi multinasional dan negara-negara maju yang mendesakkan kepentingan-kepentingan industrialnya ke negara-negara kurang maju/berkembang dan terbelakang).
Maka negara tampil membedakan diri dengan masyarakat sipil (civil society). Kepentingan negara berhadapan dengan kepentingan masyarakat sipil. Jika kita paralelkan masyarakat sipil dengan sosok bangsa (personifikasi bangsa sebagai masyarakat), negara tampak berposisi dominan mengatasi bangsa.
Di sisi lain, ada perubahan mendasar yang sedang bergerak di dunia. Pola ekonomi internasional sedang berubah menjadi pola ekonomi global. Demikian juga pola-pola politik-sosial-budaya turut bergerak secara serius. Akibatnya, tumbuh saling ketergantungan di dunia. Ada yang menyebut fenomena ini dengan gejala desa buana (global village). Dunia seolah mengerut karena jarak-jarak terlampaui. Kenichi Omahe, kita tahu, malah menyebutkan bahwa tapal-tapal batas negara telah terlampaui.
Di titik inilah konsep negara-bangsa mengalami tantangan hebat. Globalisasi banyak membawa hal ‘aneh’: di satu sisi, penguatan sentimen dan fanatisme etnis, kebangkitan wacana lokal, post colonial (geliat penolakan/perlawanan terhadap wacana dominan) dan plural; di sisi lain, penguatan perasaan global dalam keseharian kita (misalnya lewat suguhan MTV, CNN, atau persoalan ekologi dan hak asasi manusia) telah menggamangkan wacana kebangsaan — tepatnya, telah menggamangkan identifikasi nasionalitas kita pada negara-bangsa..
Ironis. Kesadaran, kebutuhan, akan nasionalitas dalam upaya mengkonstruksikan sebuah identitas, menjadi mula perjalanan kelahiran sebuah negara-bangsa. Tapi dalam perkembangannya kemudian, pelekatan identitas pada negara-bangsa menjadi problematis dan ilusif.
Budaya bangsa
Masalah identitas budaya bangsa adalah persoalan yang lebih populer dari persoalan negara-bangsa. Untuk Indonesia, persoalan ini agaknya masih dihantui debat klasik polemik kebudayaan. Perbincangan tentang kebudayaan nasional (khususnya di kalangan birokrat dan para intelektual mapan) masih banyak berputar pada debat Ki Hadjar-Takdir: ke manakah kita arahkan orientasi kebudayaan nasional kita — ke Barat, atau ke Timur; modern, atau tradisional? Umumnya orang percaya bahwa jawaban terbaik adalah gabungan unsur terbaik keduanya; bahwa Barat-Timur bukanlah soal benar; bahwa modernisasi bukanlah westernisasi.
Tapi yang sering dilupakan orang adalah bahwa “kebudayaan nasional” dipandang secara taken for granted sebagai sebuah entitas yang utuh dan total. Dalam kenyataan, adakah entitas semacam itu? Bisakah kita menunjuk dengan pasti dan tegas, apakah “kebudayaan nasional Indonesia”? Tentu saja kita juga akrab dengan jargon Bhinneka Tunggal Ika. Kita sepakat, ini juga secara taken for granted, bahwa keragaman adalah kekayaan kita. Toh dalam konteks “budaya nasional”, kita cuma ingin mengambil “puncak-puncak kebudayaan daerah”. Puncak-puncak. Ada asosiasi “pusat” dalam konsep ini — mungkin karena pengaruh wacana negara yang hegemonik.
Homi Bhabha, seorang pemuka wacana pascakolonial, melontarkan pembedaan menarik antara cultural diversity (keragaman budaya) dan cultural difference (keberbedaan budaya). Keragaman budaya adalah konsep yang dibangun dari asumsi tradisi liberal, khususnya relativisme filosofis dan asumsi-asumsi antropologis, bahwa kebudayaan adalah beragam dan keragaman adalah baik serta mesti dipentingkan.
Dalam praktik, menurut Bhabha, konsep keragaman budaya mengandung dua masalah: pertama, ia diterapkan sambil membangun sebuah aturan main yang ditetapkan oleh masyarakat ‘tuan rumah’ atau budaya dominan; aturan main yang kurang lebih berbunyi, ‘budaya-budaya lain ini memang baik, tapi mesti bisa ditempatkan dalam jaring budaya kita.’ Artinya, (konsep) keragaman budaya diciptakan, sementara keberbedaan budaya dikurung. Masalah kedua, pada banyak masyarakat yang menganjurkan multikulturalisme, rasisme masih hadir dalam berbagai bentuk. Hal ini karena, menurut Bhabha, konsep keragaman budaya menopengi norma-norma, nilai-nilai dan berbagai kepentingan etnosentris.
Bhabha tentu saja melontarkan pandangannya dalam konteks Inggris, tempat ia tinggal kini. Di Inggris, masyarakat dan budaya Anglikan — ‘Inggris putih’ — adalah tuan rumah, dominan dan menekan. Kaum migran (seperti Bhabha, Salman Rushdie dan Hamid Algar), kaum hitam dan kaum perempuan sedang menggeliat melawan tekanan budaya dominan, budaya pusat tersebut. Dalam rangka geliat perlawanan itulah, perlu ada kesadaran akan keberbedaan budaya; kesadaran bahwa dalam kenyataan sosial, budaya-budaya yang berbeda berada dalam kondisi tak-saling-imbang, sehingga perlu ada semangat keberpilihan dan ke-lain-an (otherness).
Bukan berarti Indonesia aman dari masalah yang diungkapkan Bhabha. Beda memang dengan Inggris, Indonesia tak memiliki budaya nasional yang sudah ‘jadi’. Tak ada sebuah budaya nasional yang secara tegas menjadi tuan rumah di negeri ini. Di sisi lain, kemajemukan adalah sesuatu yang akrab dengan kita — lebih dari Inggris dengan problem multikulturalnya yang baru menguat belakangan ini saja.
Toh jawaban kita terhadap problem kemajemukan begitu tipikal. Kita menyandarkan diri pada ide keragaman budaya: bahwa kemajemukan (budaya) tersebut dibiarkan, diakomodir, sepanjang berada dalam sebuah common ground bernama budaya nasional. Padahal kita tahu, “budaya nasional” masih merupakan bayang-bayang yang belum terpegang (bahasa halus-positifnya: masih cita-cita).
Maka demikianlah, budaya nasional adalah sebuah pretensi.
Ironi, potensi
Seorang pengamat yang membandingkan problem kultural di Amerika dan Indonesia, William H. Frederick, pernah mengungkapkan hal menarik: ide nation atau “kepribadian nasional” menurut sifatnya adalah samar-samar, idealistis dan romantis; pada saat orang terlalu keras mencoba mendefinisikannya, ia menghilang. (Prisma, 1982).
Upaya terlalu keras mendefinisikan nation bisa jadi dilakukan dua pihak yang berbeda (bahkan berlawanan) sisi: mereka yang ketat dan rigid bersikap konservatif-konvensional dalam memandang masalah kebangsaan; dan mereka yang terlalu ingin kritis, sehingga terjebak menjadi ‘oposan kronis’ (yang penting beda dan protes!) dalam berkebangsaan.
Yang imbang mungkin mendengar kembali suara menyejukkan Soedjatmoko, misalnya, yang berkata bahwa nasionalisme adalah learning process. (Soedjatmoko, 1988) Nasionalisme kebanyakan kita kini mungkin saja masih nasionalisme seolah-olah, yaitu nasionalisme yang masih terlalu menyandarkan diri pada pretensi dan ilusi. Tapi nasionalisme adalah juga sebuah niat. Dan agama mengajarkan bahwa niat mesti selalu diperbarui –supaya tetap segar dan konsisten.
YANG LISAN, YANG LIYAN
#Arsip Ulasan saya atas novel Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Dimuat di majalah Tempo edisi 10 Agustus 2015. Saya unggah di sini, yang belum diedit oleh redaksi, semata karena memang ini file yang saya punya. Silakan menikmati.
Hujan Bulan Juni: Novel, Karya: Sapardi Djoko Damono, Penerbit: Gramedia, 2015
Salah satu puisi yang sangat popular beralihwahana jadi novel. Sebuah pergulatan bahasa yang cukup mengesankan.
Penyair Sapardi Djoko Damano agaknya setabah hujan dalam puisinya yang terkenal itu. Setidaknya, dalam menghasilkan novel ini, sang penyair mendada dua keadaan yang sekilas tampak berada di luar wilayah nyamannya sebagai seorang penyair senior.
Pertama, novel Hujan Bulan Juni ini terjun bebas dan mungkin setengah nekad masuk ke pusaran deras bahasa lisan zaman kini yang pathing seliwer dengan bahasa slang dan alay yang pakemnya bergonta-ganti dengan cepat, serba-pesan teks (texting) dari gawai ke gawai, percakapan-percakapan gaduh di media elektronik dan media sosial, serta kepercayaan yang makin lama makin menjauh dari kata menuju permainan simbol-simbol visual macam emoticon dan meme.
Kedua, novel ini juga mencoba menyelami alam pikir zaman sekarang, khususnya kalangan mudanya. Sarwono, tokoh utama novel ini, adalah dosen muda Antropologi UI yang sering diledek “zadul” atau “zaman dulu” oleh Pingkan, pacarnya (ah, tak jelas benar apa betul ia “pacar” Sarwono, walau polah mereka jelas “pacaran” dan malah mau menikah segala). Pada Pingkan lah, sudut pandang dunia muda itu diwujudkan oleh novel ini.
Untuk soal kedua, soal gambaran “dunia muda”, Sapardi memanfaatkan benar keleluasaan novel untuk mencipta dunia rekaan yang pas dengan maksud sang pencipta/pengarang. Dalam perkembangan penulisan fiksi sekarang, tak penting benar kesesuaian mutlak dunia rekaan dengan dunia faktual di luar sebuah karangan. Apakah benar, atau benarkah nyata, dunia anak muda yang pembaca temui sehari-hari sama seperti gambaran dunia Pingkan dalam novel ini? Tak penting.
Yang penting adalah apakah sang pengarang mampu menggambarkan dunia rekaannya dengan tuntas, dan logis di dalam dirinya sendiri. Sapardi memilih cara membangun ketuntasan dunia Hujan Bulan Juni bukan bertumpu pada plot, adegan, atau deskripsi dunia eksterior yang detail, melainkan pada kelincahan petualangan interior atau pergolakan batin para tokohnya. Dengan kata lain, Sarwono adalah tokoh yang lebih banyak bertanya-tanya, berpikir, sibuk menanggapi kejadian-kejadian di luar dirinya atau yang menimpa dirinya secara internal.
Tak ada kejadian luar biasa dalam novel ini. Atau, novel ini memperlakukan berbagai kejadian penting dalam hidup tokohnya sebagai biasa-biasa saja. Bukan berarti Sarwono, Pingkan, serta tokoh-tokoh pelengkap lain dalam cerita ini, cuma sibuk melamun saja di dalam kamar. Mereka aktif. Sarwono peneliti yang andal, berbulan-bulan pergi ke Timur Indonesia untuk penelitian Antropologi. Pingkan pun aktif, juga dalam berhubungan dengan lelaki. Malah gadis campuran Menado-Solo itu seakan jadi perebutan cinta di Solo, Jakarta, Manado, Kyoto. Mereka juga aktif bercakap, lewat lisan, lewat khayalan, lewat pesan-pesan WA (Whatsapp, aplikasi komunikasi gratis yang popular di ponsel).
Demikianlah, maka dunia Hujan Bulan Juni adalah dunia persilangan kata –yang diucapkan atau yang dipikirkan para tokohnya, yang terlintas pada diri para tokohnya atau pun yang memintas sebagai suara narator entah siapa yang di beberapa bagian nyelonong saja. Maka, di sinilah kita gamblang melihat penghadapan sang pengarang dengan soal pertama di atas: sebuah dunia babel digital, dunia kelisanan sekunder sebagaimana pernah ditulis oleh Sapardi dalam buku esainya yang sangat penting, Alih Wahana (Editum, edisi revisi, 2014).
Sapardi (2014) mengurai tentang dunia kelisanan primer dan kelisanan sekunder. Kelisanan primer ada ketika zaman manusia berbahasa lisan tanpa terikat pada tulisan. Kelisanan sekunder terjadi ketika dunia bahasa sudah terpaku pada keaksaraan, pada dunia tulisan. Tapi, meminjam sedikit dari Marshall McLuhan, Sapardi menekankan bahwa di masa bangkitnya media elektronik, kelisanan sekunder menjadi langgam komunikasi yang semakin utama.
Dalam kasus Indonesia, terjadi kemusykilan bahasawi yang menghadang para pengampu budaya tulisan –termasuk pengarang novel dan penyair modern kita. Saat ini, kita mengalami masa ketika bahasa lndonesia yang dipraktikkan secara lisan dalam masyarakat kita seakan berjalan semakin jauh dari bahasa tulisannya. Malah, yang kita lihat dalam novel-novel remaja, chic-lit, dan metro-pop, bahasa tulisan fiksi arusutama kita kini tunduk patuh pada yang lisan.
Bayangkan dilema pengarang kita sekarang yang hendak menjunjung bahasa Indonesia yang baik: rentan sekali ia dituduh berbahasa “kaku” dan “tak sesuai kenyataan”. Pernah ada siasat seperti yang tampak dengan mahir digunakan oleh SM. Ardan pada 1960-1970-an untuk menangkap otentisitas kelisanan masyarakat Betawi dalam cerpen-cerpennya: menjaga narasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan membiarkan dialog-dialog dalam bahasa Betawi “jalanan”. Kini, siasat macam itu seperti tak dianggap memadai lagi oleh penerbit dan editor novel-novel popular kita.
Di dunia fiksi popular kita saat ini, tulisan lah yang tampak lebih banyak terikat oleh kelisanan. Dan Sapardi, terasa benar lewat novel ini, mencoba menanggapi kemusykilan itu dengan tanpa penghakiman dan angkuh. Ia lebih mencoba menjadi setabah, sebijak, dan searif hujan dalam puisi terkenalnya itu dalam menghadapi kemusykilan itu.
Novel Hujan Bulan Juni merengkuh saja kata-kata lisan yang biasa diucap dalam keseharian WA dan ngobrol kita saat ini. Sapardi menjajarkan begitu saja kosa kata slang, campuran bahasa asing, dengan khasanah kata dalam dunia tulisan yang telah lama jadi bahan kepenyairannya. Dengan rendah hati, dengan kehendak memahami. Novel ini tak berat hati membaur ungkapan seperti “Garing banget” atau “Aku crop nanti” dalam aliran naratifnya.
Aneka bahasa hadir selayak dunia lisan sejati Indonesia kita masa kini: bahasa slang, bahasa Inggris-campuran-Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Menado, bahasa resmi, bahasa ledekan, rujukan-rujukan budaya pop (seperti Shrek atau selfie), semua setara, semua (dianggap) bermakna. Yang manis gombal dan yang cendekia memikir budaya, sama saja tempatnya di novel ini.
Di beberapa tempat, sang penyair menyatakan diri lewat litentia poetica-nya: tiba-tiba saja, misalnya, di halaman 44-45 dan 124-125, narasi menggumamkan kata demi kata dalam kalimat demi kalimat tanpa titik tanpa koma dan memuncak di ujung-ujung paragraf. Kadang, bahasa percakapan sehari-hari menyeberang begitu saja jadi bahasa dongeng (halaman 52-55).
Novel ini semacam peta kata yang berkerumuk, rekaman sebuah pikiran yang cemas dan dikerubuti keberlimpahan rujukan dari seluruh penjuru dunia, yang menyamar sebagai sebuah cerita yang enteng dan cengeng. Dalam kerumuk dan cemas itu, sebuah motif berulang. Sarwono selalu risau oleh kenyataan liyan. Pingkan adalah liyan (“the other“) karena dia Solo sekaligus Menado, sekaligus bukan-Solo dan bukan-Menado. Begitu juga ibu Pingkan, begitu juga ternyata ayah Pingkan.
Lalu Pingkan ke Kyoto, menikmati sajian dunia liyan sebagai liyan. Apakah di zaman sirkulasi orang, barang, dan gagasan secara global begitu mudahnya, kita menjadi begitu mudah pula saling me-liyan-kan orang lain? Sarwono lebih ajeg sebagai orang Jawa, tapi pun ia tak lagi yakin akan apa itu “Jawa”. Ia memelajari budaya liyan di seluruh pelosok Indonesia. Ia sendiri pun, yang mengimani puisi, sering merasa diri liyan. Apakah ini dunia kita kini? Kita saling me-liyan-kan, sehingga kita selalu berisiko saling mengasingkan? Apakah lantas cinta adalah jawaban? Atau persoalan?
Novel ini agaknya tak hendak memecahkan persoalan-persoalan itu dengan tuntas. Ada memang sebuah iman pada puisi, seperti tampak dengan wagu dinarasikan Sarwono, di bagian awal novel ini. Puisi pun jadi klimaks novel Hujan Bulan Juni. Paling tidak, puisi tak sekadar diletakkan di ujung cerita, tapi juga diperlakukan sebagai sebuah puncak cerita. Seakan sebuah pernyataan dari sang pengarang, bahwa setelah ia berupaya memahami gebalau bahasa zaman kini, ia akhirnya menyimpul bahwa pada puisi lah bahasa-bahasa akan pulang.
Mungkin pula novel ini menyiratkan, tanpa menyuratkan, bahwa dalam puisi, sebuah Diri tak perlu lagi merisaukan takdir liyannya. Dalam puisi, cinta yang selalu wagu dan cemas akan menemukan pengungkapan finalnya. Dalam puisi, yang lisan dan yang liyan tak perlu dirisaukan lagi. Ini, sekali lagi, semacam iman. Ini pula yang membuat novel ini rentan menjadi liyan dalam dunia literasi Indonesia masa kini.
Misalkan novel ini dianggap gagal sebagai novel, ia mengandung kegagalan-kegagalan yang menarik. ***
TIGA MIX-TAPE
1985
Angkot biru ke arah Pondok Labu, dan radio di dashboard buluk, bersuara serak menggunting tak rapi selimut malam yang baru saja membungkus Pasar Minggu.
Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja
Selalu tersipu, rawan sikapmu di balik kemelutmu
Di remang kabutmu, di tabir mega-megamu
Ku melihat dua tangan di balik punggungmu
Satu orang penumpang, bapak kurus berkumis hampir Jampang duduk di kursi depan. Dua penumpang di belakang, selain aku, seorang pemuda kerempeng sepertinya mahasiswa (lengan kemejanya di linting sampai hampir ketiak, dua kancing atas dibiarkan terbuka, membawa dua buah buku bacaan tebal yang lecek), mukanya tampak bosan. Dan seorang lelaki berkopiah dengan wajah sepertinya selalu di ambang nyengir mengangguk-angguk mengikuti lagu yang telah kelamaan ngetop itu.
Aku yang paling kecil di angkot itu, jelas. Anak seusiaku, apalagi berkacamata cukup tebal (minus 3,5 kanan dan kiri) dengan bingkai kotak, kurus dan tirus, pantasnya sedang mengerjakan PR Matematika. Ini hari Minggu, besok adalah hari upacara. SMP-ku favorit di daerah Pasar Minggu. Artinya, peraturan sekolah yang galak. Dan, benar juga, ada PR Matematika. Terserahlah. Aku tak bisa berpikir.
Madu, di tangan kananmu. Racun, di tangan kirimu
Aku tak tahu mana yang akan kauberikan padaku
Madu, atau racun? Di benakku, aku menyanyikan bait itu untuk Reni. Sialan. Lagu Bill & Brod itu mulai masuk ke otakku. Aku penggemar musik hard rock, agak nista lah hapal, apalagi sampai merasa tersuarakan, oleh lagu itu. Tapi, ah, aku memang merasa lagu itu adalah perasaanku saat ini kepada Reni.
Dia manis. Reni. Dia bahkan cantik. Tapi, dia tak manja. Gadis berambut panjang, hingga bagian pantat lebih sedikit. Selalu dikuncir. Senyumnya menerbitkan lesung pipit. Dia tak manja, tapi dia bisa membuat bocah lelaki macamku merasa lelaki –ia gadis yang bisa kubayangkan sebagai perempuan. Hm. Apa sih, yang kupikirkan ini.
“Cilandak! Cilandak!” Sopir angkot berteriak, menawarkan jasa. Baru sampai SMA 28, angkot berjalan perlahan.
Reni adalah gadis pertama yang kuajak menonton. Betapa gemetar, waktu aku mengajaknya lewat telepon umum. Nonton film Witness, yang bintangnya Harrison Ford. Acara Prambors Putar Film di bioskop Kartika Chandra. Dengan merasa nekad, aku beli tiket di tempat jualan tiket Ibu Dibyo, Blok M. Tanpa tahu, apa Reni mau kuajak menonton. Ternyata dia mau, lepas dari suaraku yang sedikit gemetar sewaktu meneleponnya.
Lalu, aku jadi berani main ke rumahnya, beberapa kali. Termasuk tadi. Tapi, tadi, aku rada canggung. Reni yang manis. Kudengar dia dekat dengan temanku, Tedi. Waduh. Mana bisa aku bersaing dengan Tedi? Aku jadi kehilangan obrolan dengan Reni, mengingat kabar ini. Mau tanya, tapi tak berani. Kenapa aku tak berani? Ini Tedi. Dia gitaris rock, tampangnya kayak Amy Search.
Yang paling tak bisa kusaingi, dia anak yatim piatu, tinggal di Rumah Yatim di daerah Pasar Minggu, tak jauh dari rumah Reni. Mencari uang dengan main band di Ancol, dan membetulkan gitar listrik atau sistem suara buat panggung. Tapi, mengapa Reni kemarin-kemarin mau menerimaku bertamu, ngobrol berjam-jam? Apa dia sedang mempermainkanku? Tangan di belakang punggungnya, ada madu dan ada racun kah? Aku tak tahu mana yang akan kauberikan padaku….
Tapi radio serak itu sudah beralih ke lagu lain. Lagu Iwan Fals. 22 Januari. “Cilandak, Labu! Cilandak, Labu!” Seorang perempuan paruh baya naik. Sopir ikut menyanyi di bagian yang bagiku terasa sangat lelaki itu:
Jalan berdampingan
tak pernah ada tujuan
Apakah Reni pernah jalan tanpa tujuan dengan Tedi? Mungkin saja. Aku cemburu. Ini racun. Aku sesak napas. Aku ingin memegang tangan Reni, menggenggamnya lama-lama, sekali saja. Tidak cuma bicara-bicara. Apa yang dilakukan Reni dengan Tedi jika mereka berduaan? Aku sungguh kurang lelaki. Aku tak berani mengatakan perasaanku. Aku masih bocah, padahal aku banyak membaca bacaan dewasa.
Memangnya, apa perasaanku?
“Labu, Labu!” Sopir yang serak, menimpa radio serak yang sedang mengudarakan sapaan penyiar. Ada permintaan pendengar, kiriman lagu dari Dedi di Kalibata untuk Neti di Gang Klingkit, Saharjo, dengan ucapan, “kapan ke air terjun lagi?” Sudah sampai Cilandak Dua, sebentar lagi aku harus turun.
“Depot Es, Bang! Kiri!”
Aku turun. Membayarkan seratus rupiah, merasa wajib menerangkan, “Pelajar, Bang!” Aku masuk gang. Dekat rumah Pak Haji Sanih, yang punya warung nasi uduk dan depot es batu, Pak Joko dan Pak Warso sedang asyik mengobrol di bangku kayu warung. Pak Joko menyapaku, “Dari mana malem-malem…pacaran, ya?” Lalu ia ketawa. Aku cuma menggumam, “Ah, enggak, Om….” Pak Joko dan Pak Warso (dia marinir, hampir pensiun) lanjut ngobrol soal mayat yang diduga korban Petrus (Penembakan Misterius) di Ragunan kemarin malam.
Di rumah, hanya ada Mamah. Adikku, Rusdi, sedang menginap di rumah Uwak Dedi, di Jalan Radio Dalam, ingin bermain dengan para sepupu kami dari Uwak. Papap pasti sedang di rumah istri mudanya, di Condet. Ada kesepakatan diam-diam di rumahku, untuk pura-pura tak tahu bahwa Papap sudah kawin lagi. Mamah menyuruhku makan, dan mandi. Sayur bening pakai jagung manis, dengan lauk ikan tongkol balado. Aku makan, Mamah sholat. Aku malas mandi, jadi langsung ke kamarku (Papap mengontrak dua petak sekaligus jadi rumah kami), langsung masuk ke rutinku selama 2-3 bulan belakangan: melamun.
Radio kunyalakan. Radio yang tak akan memutar Madu & Racun. Sudah kubilang, seleraku hard rock. Sebetulnya, ya segala macam musik rock sih. Tapi, tak ada radio yang memutar musik rock jam segini. Harus pasang kaset di tape deck. Hanya, ini sudah malam. Dinding rumah petak kami batako yang kopong di tengah. Suara mudah melewati dinding, ke tetangga. Sebaliknya, tetangga pun jika sedang berisik menyetel kaset Eddy Silitonga atau Panbers atau, ya, Bill & Brod, akan merembes ke kamarku.
Pilihan kedua, putar radio. Musik pop Barat. Musik Jazzy Indonesia. Atau, diam-diam aku suka juga setel radio bermusik Adult Contemporary. Malam begini enak juga, tak perlu disetel kencang volume radio. Kalau sudah dini hari, dengar radio putar kelenengan wayang kulit juga senang. Malam ini, aku merasa lagu pop. Reni, bisa kuajak bicara apa saja. Waktu seperti terbang. Lalu, seluruh ekspresinya terbawa-bawa ke kamar ini. Aku coba membaca, apa saja yang terjangkau dari serakan buku, majalah, koran, komik, dan buku-buku gambar. Dan kaset-kaset.
Koran kemarin memuat berita tersangka pembom Borobudur. Ada yang bilang, itu terkait peristiwa Priok tahun lalu. Ada yang bilang, itu terkait dengan Revolusi Iran. Macam bahan cerita buat seri petualangan dari Bung Smas atau Jokolelono saja. Aku menelusuri huruf-huruf berita dengan malas. Aku tak hendak mengkhayal bertualang melawan penjahat. Aku ingin mengkhayalkan si manis Reni, tangannya seperti awan, menggamitku di tepi kali yang jernih. Ih. Bersentuhan dengan kulit perempuan selalu hal besar buatku. Aku belum menyentuh Reni. Baru berkhayal saja.
Apa Reni dan Tedi pernah bergenggaman tangan? Duh. Aku tak pernah nyaman bersaing. Apalagi soal beginian. Aku pasti kalah. Pasti. Tedi. Anak band. Anak yatim piatu. Macam tokoh di film roman saja, ia. Tapi, aku ingin menggenggam tangan Reni. Sekali saja. Kulihat koleksi kaset-kasetku. Ah, ya. Jika tak bisa bicara, kukirim saja pesan cintaku lewat lagu-lagu. Jelas aku kalah dalam soal musik dari Tedi. Aku cuma pendengar musik, dia pemain musik. Pemain.
Tapi, lewat musik, setidaknya perasaanku pada Reni bisa lebih berbunyi, ketimbang lewat kata-kata yang tak juga terucap. Aku bangkit dari kasurku yang kisut. Pukul 8.12. PR Matematika biarlah besok kusalin dari Anggia pas istirahat pertama. Atau, pas pelajaran Geografi, gurunya toh cuma gemar mencatatkan pelajaran di papan tulis untuk kami salin. Malam ini aku akan menyusun rekaman lagu-lagu untuk Reni. Kamis, sepulang sekolah, akan kubawa susunan itu ke Aldiron, minta direkamkan jadi kaset.
Aku jadi bersemangat. Aku menyusun lagu-lagu agar pas untuk kaset C-60, enam puluh menit. Biasanya dua belas lagu, pas. Enam sisi A, enam sisi B. Kira-kira begitu. Tak bisa kususun berdasarkan seleraku. Musti kubayangkan apa yang cocok bagi Reni, si manis si cantik. Lagu pop. Sesekali kusisipkan yang seleraku, lagu cinta dari grup rock. Yang Barat saja.
Karena sepertinya semua seluk beluk cinta sudah ada lagunya, aku tak pernah kekurangan lagu untuk menyusun perasaanku kepada Reni. Tapi, aku lebih dituntun oleh musik sebuah lagu, bukan oleh syairnya. Aku lamban untuk hafal syair lagu.
Baiklah. Riangnya cinta. Hasrat bercampur heran. Melayang. Berenang dalam perasaan. Banyak lagu bisa menggambarkan itu. Kenapa aku menulis Mermaid (Tatsuro Yamashita)? Bukannya Head Over Heels (Tears for Fears) saja yang lebih keren? Atau, lagu-lagu cinta yang gagah lainnya macam dari The Police atau Led Zeppelin, atau Without Your Love-nya Roger Daltrey. Eh, boleh juga, Daltrey. Mungkin juga Rod Stewart, First Cut is The Deepest? Hm. Kok pahit ya, judulnya. Aku membayangkan Reni. Dan Tedi. Baiklah, Rod Stewart masuk.
Tentu saja sebuah mixtape untuk mengungkapkan perasaanku pada Reni harus memuat Deborah dari Jon Anderson dan Vangelis. Bukan soal liriknya. Aku toh tak terlalu ngeh, atau perduli, apa liriknya. Musiknya yang kurasa mewakili cinta. Malam dengan gelembung sabun dan pelangi, ruangan dengan lagu itu akan terasa enteng, melayang.
Aku melayang. Menembus atap seng rumah petakku. Terus ke atas, panorama Cilandak yang sedang lelap. Tukang sekoteng lewat di gang depan rumahku. Malam memekat, bulan ngumpet di balik awan. Udara yang tipis. Aku seperti layangan tanpa benang, mencari-cari arah ke rumahnya. Lagu-lagu kenangan ayahku melintas. Melody Fair, Bee Gees. Atau In The Morning? Dan gambaran pagi kota modern di Inggris dalam film Melody. Tapi, ini malam, bukan pagi. Dan malam ini, aku suka seluruh lagu di album duet Barbara Streissand dan Barry Gibb. Streissand aroma Bee Gees era kiwari. Gitar listrik ringan, vokal falsetto lelaki brewok. Malam ini aku suka Run Wild.
I wandered into your wonderland
With eyes open wide
You turned me into your yesterday
Entah mengapa, aku yakin sekali bahwa aku tak akan bisa mendapatkan Reni.
1998
Mei
Aku terbangun mendadak di kamar kos dengan keringat kuyup. Jakarta sedang mimpi buruk. Aku tidur dengan berita penembakan mahasiswa Trisakti kemarin. Aku ingin menulis sesuatu, tapi kata-kata tak ada yang cukup. Insting wartawanku mengendus sesuatu yang mengerikan. Tapi, aku tak bisa mengikuti instingku itu jadi penyelidikan jurnalistik yang memadai, aku cuma wartawan kesenian.
Kesenian rasanya tak berguna dalam cekam ini. Semalaman Jakarta sudah diselimuti penantian yang cemas. Sesuatu akan terjadi. Perlahan, matahari yang merembes lewat jendela kos menjamah kesadaranku. Kulihat jam di dinding, pukul 10.16. Petak-petak kos terasa sunyi. Tak ada suara orang mandi, tak ada musik keroncong dari kamar Bachrul. Semua sudah berangkat kerja, atau mengajar, atau kuliah, agaknya.
Tita. Aku ingin sekali mengobrol lagi dengan Tita, walau semalam sudah menelponnya selama hampir satu jam. Satu jam hanya sebentar. Selama beberapa bulan ini, aku sering menelpon sampai dua atau tiga jam. Sekarang saat yang tepat ke telepon umum terdekat dari kos. Biasanya, kosong. Aku menggapai celana jeans-ku yang teronggok di lantai. Kurogoh kantong kanan dan kiri. Enam koin seratus rupiah, tujuh koin lima puluh rupiah. Cukuplah. Dan masih ada enam belas ribu rupiah, masih cukup juga untuk makan di warung Indomie sebelah telepon umum.
Aku cuci muka sebentar. Air terasa tiris di wajahku. Hampir pukul sebelas. Aku keluar pagar kos. Kugembok, soalnya sudah tak ada orang dari sepuluh kamar kos-kosan itu. Sepuluh kamar yang mengelilingi taman kecil, sekaligus tempat menjemur pakaian. Empat kamar mandi di luar kamar kos. Dua sudut untuk dapur bersama. Satu pagar tembok dengan pintu besi. Seperti penjara.
Di luar, matahari yang meninggi memijat dan mencubit kulitku. Kulewati warung rokok Mas Jo. Radio diputar keras, Mas Jo dan seorang pembeli yang duduk di bangku kayu tampak menyimak. Kudengar sekilas. Penyiar membahas penembakan mahasiswa Trisakti kemarin, sambil terasa takut-takut terbawa suasana jadi protes. Penyiar itu terasa agak terlalu berusaha agar semua pihak menenangkan diri.
Sampai ke telepon umum, segera kutekan nomor telepon rumah Tita. Tak ada jawaban. Dua kali aku mencoba. Hanya dengung teratur di telingaku yang berarti dering nun di ujung sana. Seorang bertampang mahasiswa berdiri di belakangku. Aku mulai gelisah. Ketika percobaan kedua tak disahut pula, aku menyisih dari telepon umum, dan ke warung mie instan. “Bang, rebus satu, ya. Rasa soto. Ya, pakai telor.” Semalam, Tita tak berkata akan pergi ke mana-mana. Ini bukan hari dia ke kampus. Kuperhatikan si tampang-mahasiswa masih menelepon.
Dua orang lain duduk di warung. Yang satu minum kopi, yang satu asyik makan gorengan. Bang Rosid pemilik warung menyiapkan mie instan rebusku sambil ngobrol dengan dua orang itu. “Saya denger tadi, udah ada yang rame-rame tuh. Pasar Minggu ada yang bikin rusuh. Lempar-lempar batu. Malah katanya sudah ada yang ngejarah. Ini, Bang,” Bang Rosid memberiku pesananku. “Katanya juga, tempat laen rusuh juga. Si Hamid bilang, di Jatinegara juga….”
Setelah tandas mie instan rebusku, aku mencoba lagi menelepon. Koin masuk, dengung nada panggil di telingaku. Tak juga ada jawaban. Aku matikan, ceklek, koinku keluar. Aku mondar-mandir dengan gelisah. Jam di warung tadi menunjuk pukul sebelas lebih dikit. Aku harus mencoba lagi.
Kali ini, dalam dengung nada panggil yang keempat, telepon di ujung sana segera diangkat. Bukan Tita. Ibunya, yang mengangkat teleponku. “Ke kampus, Tante? Oh, bukan yang Depok? Salemba? Dekat, ya, Tante. Saya nanti telepon lagi, boleh?”
Ada apa di Salemba? Aku bisa menduga ada apa di situ hari ini. Salemba masih jadi tempat simbolik perlawanan mahasiswa. Tapi, semalam, Tita tak berkata apa-apa soal akan pergi ke Salemba. Aku merasa harus menyegarkan diri. Aku berjalan ke kos, melewati warung Mas Jo. Penyiar yang cemas itu masih bersuara di radio Mas Jo, menyarankan agar semua pendengar selalu berhati-hati dan menahan diri. Di kos aku segera mandi, mengguyur perlahan kepalaku dengan air dingin.
Ya, aku cemas. Tita telah mengisi hari-hari sepiku dengan obrolan-obrolan menyenangkan. Dia tujuh tahun lebih muda dariku. Sangat belia. Tapi, dia mampu mengimbangiku dalam percakapan-percakapan panjang kami. Maaf saja, mungkin aku memang sedikit sombong dalam soal ini. Aku seorang penulis. (Aku lebih menganggap diriku sebagai seorang penulis, dan pekerjaan sebagai wartawan hanyalah alat bagiku untuk tetap menulis.) Boleh jadi, ini salah satu pekerjaan dengan risiko kesepian paling tinggi.
Salah satu sebabnya adalah, sukar bagi seorang penulis untuk bicara biasa-biasa saja. Bisa saja, tapi sukar –bicara hal-hal remeh seperti cuaca, harga-harga sayur, tagihan-tagihan, hasrat ingin membeli mobil merk terbaru, kisah perceraian bintang sinetron, banyak hal, bisa saja kuobrolkan, tapi selalu dengan sedikit rasa palsu. Lebih baik, menghindari percakapan sama sekali. Paling tidak, itu yang kurasakan.
Apa yang pernah dirasakan oleh para penulis modern sejak Sutan Takdir, Asrul Sani, Sitor Situmorang, Seno Gumira Ajidarma, hingga Afrizal Malna, rasa asing di tengah masyarakatnya sendiri, ternyata karib juga kurasakan –aku, seorang penulis gurem yang hanya mampu jadi wartawan kesenian sebuah majalah nasional dengan oplag tak sampai 20 ribu tiap edisi.
Itulah mengapa ketika aku menemukan Tita, seorang mahasiswi jurusan Sastra Prancis, teman dari temanku (seorang perempuan berjilbab aktivis Islam kampus yang gemar bergaul dengan para senior), dan merasakan dia bisa diajak ngobrol apa saja tanpa jadi menjemukan, aku merasa senang sekali. Kami bisa bersama menertawakan dunia. Dalam tiris air kamar mandi yang mengguyur kepalaku, aku makin merasakan betapa berharganya obrolan-obrolan kami selama ini.
Sesudah segar, aku nyalakan televisi. Berita siang. Ada kerusuhan di beberapa tempat yang mulai terpantau. Aku harus menelpon Tita. Aku semakin mencemaskannya. Ke mana Tita?
Pertanyaan itu tak juga terjawab ketika aku menelepon rumah Tita lagi. Ibunya bilang, Tita belum pulang. Aku semakin gelisah. Kamar kos semakin terasa jadi penjara. Aku harus pergi. Ke mana? Ke Salemba? Apa bisa aku menemukan Tita dalam keramaian yang kuduga sedang terjadi? Atau… Ya, bagaimana jika aku ke radio Delta saja. Dekat Salemba. Seminggu sekali, aku siaran di situ, membicarakan kesenian Indonesia. Para penyiar dan awak radio itu praktis telah jadi temanku juga. Pukul satu lewat. Naik kereta, mungkin akan tiba di Cikini dalam waktu kurang lebih sejam.
Di stasiun UI, para calon penumpang ke arah Bogor tampak agak menumpuk. Tampak wajah-wajah mereka gelisah. Atau itu bayanganku saja? Pandanganku pada orang lain bukankah lebih sering cerminan perasaanku saja terhadap dunia? Yang ke arah Kota, agak lebih sepi. Hm. Apa itu, pengumuman di pengeras suara dari awak stasiun. Agak tak jelas. Ada kebakaran di Pasar Minggu? Di sekitarku, para calon penumpang yang menunggu kereta terdengar mendengung bercakap-cakap dan suara saling timpa, tak jelas di telingaku. Yang kurasa jelas, wajah-wajah yang tampak berubah cemas. Apa yang terjadi? Tita, apakah kau tak apa-apa?
Pengumuman lagi. Kereta ke arah Bogor akan tiba. Dan kulihat dari arah utara: kereta dengant tumpukan manusia di atapnya. Aneh. Ini bukan jam pulang kerja. Kenapa penuh sampai ke atas atap kereta? Makin dekat, nyatalah bahwa kereta bukan sekadar berisi penumpang biasa. Banyak dari mereka tampak sedikit kesurupan, berteriak-teriak, menunjuk-nunjuk para calon penumpang di peron. Banyak yang membawa barang-barang. Ada satu remaja botak dan dekil memegang sebuah sepeda gunung yang masih dalam plastik, tertawa-tawa dan berteriak, “Oy, ke Pasar Minggu sana! Niih…Niiih! Gue dapet ini!”
Lalu pengumuman lagi, seruan agar para penumpang menjaga ketertiban, dan kereta dari arah Bogor akan tiba sebentar lagi. Kedua kereta berpapasan, lalu kereta ke Kota berhenti. Aku naik gerbong keempat dari gerbong masinis. Para penumpang saling bicara, bertukar heran, kabar-kabar bersimpang-siur di udara, menggumpal dan memberai.
“Matahari kebakaran…”
“Yang di Pasar Minggu?”
“Di Jatinegara juga, katanya…”
“Cikini tuh, banyak yang bakar-bakaran…”
“Saya denger, Klender juga tuh, Pak….”
Kereta berjalan dengan memikul cemas. Stasiun Universitas Pancasila. Stasiun Lenteng Agung. Stasiun Tanjung Barat. Begitu kereta melintasi jalan Tanjung Barat menuju stasiun Pasar Minggu, tiba-tiba ada bunyi berderak. Sekali. Dua kali. Kami kaget. Ada jendela kereta yang retak kacanya. Kami segera merunduk ramai-ramai. Teriakan panik, seorang anak meletup tangisnya. Rupanya ada yang melempari kereta kami dengan batu atau entah apa. Di kanan dan di kiri. Ketegangan menjalar ke sekujur gerbong. Tapi kereta, syukurlah, tetap melaju.
Lalu, lajunya menjadi perlahan. Sebagian kami mengangkat kepala, melihat-lihat ke luar jendela. Stasiun Pasar Minggu? Udara yang panas tiba-tiba semakin menyesakkan. Seseorang menjerit. Beberapa orang menunjuk ke sebelah kiri. Perlahan, seperti adegan slow motion dalam film, kami melewati pemandangan yang menggetarkan: mal Matahari di Pasar Minggu terbakar. Asap hitam, panas bara, aroma kekerasan meruap mencemari oksigen yang kami hirup. Kereta tak berhenti, meneruskan laju secara perlahan.
Selepas stasiun, bahkan udara lebih panas lagi. Hatiku tercekat. Ada bangunan terbakar, dan apinya seakan bersiap menghadang kereta. Kereta terus melaju. Para penumpang merunduk di lantai kereta, tegang seakan sedang dalam perang. Ini memang perang. Walau pihak-pihaknya bagi kami, para penumpang kereta yang terjebak melintasi kerusuhan Jakarta, adalah siluman: tak jelas siapa, dan apa maunya –hanya mengancam, dan menakutkan. Kereta melintasi api. Beberapa penumpang menjerit, berteriak. Allahu Akbar, kata seseorang penuh perasaan.
Kereta lolos dari api. Dan melaju, stasiun demi stasiun. Ketegangan di gerbong mereda, tapi masih ada. Hingga aku turun di Cikini. Turun ke dari kereta, kulihat beberapa orang di stasiun memandang ke bawah, ke jalanan. Dari peron di tingkat dua stasiun Cikini, tampak suasana yang absurd tapi sekaligus masuk akal bagi Indonesia saat ini: suasana chaos, orang-orang menjarah, ada ban yang terbakar, sebuah kerusuhan sisa. Suasana kacau yang tak membuatku takut untuk turun ke jalan, lanjut ke studio radio Delta.
Di jalanan Cikini, suasana terasa semakin sureal. Penjarahan berlangsung dengan riang dan penuh tawa. Banyak ibu-ibu, agaknya dari kampung sekitar, datang bersama anak mereka, kelihatannya berdandan, seperti hendak datang ke sebuah acara alun-alun. Sebuah motor dikendarai oleh seorang lelaki, membawa (sepertinya) keluarganya, istri dan seorang anak perempuan, lalu berhenti di depan sebuah gedung apartemen dengan toko dan supermarket yang dijarah. Lalu keluarga di motor itu menonton penjarahan, seperti menonton pertunjukan.
Masuk ke jalan Borobudur, beberapa anak kampung berjalan membawa kursi dari McDonald. Dua orang anak, sambil cengar-cengir malah membawa meja putih bundar dari McDonald, digelindingkan sepanjang jalan seperti sedang bermain roda. Aku berjalan di antara para penjarah seperti hantu, seakan melayang.
Tita, di mana kamu?
Agustus
“Mau nginep lagi, Mas,” tanya Mas Anto, satpam radio tempatku kini menyambi bekerja sebagai perancang program. “Iya, Mas,” kataku.
Mas Anto tertawa ramah, dan kami mengobrol ngalor ngidul sejenak, tentang Mbak Retno, penyiar senior kami, yang tadi siang marah-marah karena ada penggemar yang sudah jadi penguntit lolos dari halangan satpam dan sempat menjumpai Mbak Retno. Tentang Habibie yang ngomong-nya lucu, dengan mata bulat mendelik-delik. (“Tapi, dia ngomooong melulu, ya, Mas,” kata Mas Anto.) Tentang Amin Rais. Tentang IMF, bagaimana urusannya. Tentang Timor Timur. Tentang Mas Jan, direktur kami yang baik, tapi tak mau menaikkan gaji.
Lalu, Mas Anto meninggalkan ruang studio. Sudah lebih dari setengah jam berlalu dari tengah malam. Aku menginap tak sepenuhnya buat bekerja. Aku ingin menyusun mix-tape untuk Tita. Sudah sedikit tersusun di kepalaku, daftar lagu-lagunya. Kupilihkan dari koleksi radio ini. Banyak vinyl dan kaset lawas masih terpelihara baik di sini. Alat perekam pun kelas satu. Aku bisa membuat banyak mix-tape. Malam ini, satu saja.
Aku ingin menyatakan perasaanku pada Tita. Sejak mix-tape yang kubuat untuk Reni dulu, sewaktu SMP dulu (aku selalu sedikit tersenyum jika benakku mengenang Reni), aku seperti mentradisikan mix-tape sebagai pernyataan cintaku. Sejak Reni, tak sering aku menyusun mix-tape cinta. Aku memang jarang melakukan langkah lanjut untuk menyatakan cintaku. Aku memang mudah jatuh cinta. Tapi, jatuh cinta itu murah. Mencintai, itulah yang susah.
Mei lalu, mataku tiba-tiba terbuka. Sejak kerusuhan itu, aku jadi sadar bahwa Tita bukan teman biasa. Aku ternyata tak bisa kehilangan dia. Ketika di tengah kerusuhan itu aku merasa dunia sedang jungkir balik, aku merasa, siapakah yang kuinginkan berada di sisiku ketika dunia runtuh? Ternyata, aku ingin sekali Tita di sampingku. Pikiran bahwa waktu itu Tita mungkin celaka, sungguh membuatku merana. Ini memang klise. Jatuh cinta dan bahkan mencintai yang kuanggap musykil itu, memang sebetulnya hal yang biasa saja.
Baiklah. Aku harus selesai merekam mix-tape buat Tita sebelum subuh tiba. Susunan lagu harus terasa imbang antara mood yang ringan dan yang sedikit berat. Jangan blues amat, aku toh hendak menyampaikan harapan. Kurasa, aku tak bisa membuka kaset ini dengan When It Hurts So Bad-nya Lauryn Hill. Itu lebih cocok di tengah. Juga Adam Ant, Wonderful, sebaiknya dipasang sesudah suasana sudah meningkat. Apalagi Head Over Heels-nya Tears for Fears.
Apakah sebuah lagu Style Council untuk pembuka Side A? Aku masih bimbang apakah akan memilih Shout to The Top atau My Ever Changing Mood versi akustik piano. Lirik yang pertama tak mencerminkan soal cinta kepada perempuan, tapi musiknya menggambarkan kegirangan perasaanku setiap habis bertemu Tita. Tapi, lagu kedua, sungguh lembut. Menyiratkan perasaan yang lebih dalam.
Atau kubuka dengan lagu Fariz RM saja, Selangkah Ke Seberang, ya? Hm. Tidak juga sih. Begitu juga lagu Chrisye yang kuinginkan untuk mix-tape ini, Lestariku. Versi album Percik Pesona lebih pas kurasa, musiknya, untuk Tita. Tentang Kita dari KLA Project harus di tengah sih. Begitu juga When I’m Thinking About You dari The Sundays. Tapi, penutup untuk Side B, sudah kupastikan: You and Me Song, The Wannadies.
Kurang lebih tiga jam aku mengutak-atik susunan lagu untuk kaset C-60 yang akan jadi keramat bagiku. Merekamnya satu-satu. Aku juga sudah membayangkan bagaimana sampulnya. Sedikit desain pakai komputer, sepulang ke kos nanti. Subuh hampir mampir di luar sana. Aku lelah. Kupejamkan mata sejenak.
Aku sungguh ingin tumbuh tua bersama Tita.
2015
Zaman sekarang, mudah saja membuat mix-tape. Istilah itu sendiri jadi terasa agak dibuat-buat. Mediumnya pun bukan “tape” lagi, bukan kaset lagi. Umumnya, orang bikin mix-tape sekarang menggunakan file berjenis mp3. Lalu dicetak ke keping CD atau DVD. Atau langsung saja dialihkan ke i-Pod atau MP3 Player. Atau dipasang saja di situs yang sering kugunakan, 8tracks.com. Jumlah lagu bisa ratusan, tapi jadi kurang tajam untuk mengungkapkan perasaanku.
Ah, perasaan. Perasaan apa? Kulihat jam di ponselku, pukul 7.16 malam. Nanda sudah memberi pesan lewat Whatsapp, dia akan terlambat. Mataku menerawang ke sekeliling kafe ini. Suasana agak vintage Jakarta era 1960-1970-an, sebuah klise komodifikasi ceruk pasar hipster di Jakarta. Apalagi kafe ini membanggakan menu kopi khususnya. Tak apalah. Kucoba sedikit memberi kesan bahwa aku paham trend gaya hidup terkini, waktu aku mengusulkan tempat ini kepada Nanda untuk kencan ketiga ini.
Ah, Nanda agak kurang suka dengan istilah seperti “kencan”. Dia lebih suka istilah “ta’aruf“. Oke. Dia teman sekelasku sewaktu kelas tiga SMP, dan juga satu SMA denganku. Tapi, dulu, kami tak pernah dekat. Nanda Arianti adalah salah satu kembang sekolah. Hidung bangir, mata ndelak ndelok dengan bulu mata lentik sekali, salah satu langganan juara kelas. Aku tak pernah menaruh hati padanya. Aku selalu merasa bahwa jatuh cinta pada perempuan yang terlalu cantik itu klise. Kecantikan seringkali menghalangiku melihat isi si perempuan.
Mungkin karena aku dulu memang selalu cenderung minder, sehingga kecantikan yang terlalu kuat selalu menggangguku untuk bisa menyelami para perempuan cantik itu dengan wajar. Oh, aku selalu bisa ngobrol dengan para perempuan cantik. Tapi, jatuh cinta? Aku lebih suka yang manis-manis macam Reni. Ah, Reni. Cintaku hanya sebatas mix-tape. Sesudah kuberikan, aku malah mundur teratur. Mungkin sedikit terbirit. Persaingan terlalu musykil buatku. Urusan cinta, aku sukar mengendalikan diri. Pikiranku selalu kacau jika sedang jatuh cinta. Diriku sewaktu SMP dulu, mana mampu mengatasi kekacauan itu.
Dan kini, aku terdampar di kafe hipster ini, menanti Nanda. Puji Tuhan, internet mampu membuka banyak kemungkinan. Teman-teman yang dulu tak terlacak, tiba-tiba nongol begitu saja di media sosial, lalu tahu-tahu nyambung ke ponsel lewat aplikasi-aplikasi komunikasi yang sungguh membikin kecanduan. Nanda tahu-tahu muncul di timeline Facebook-ku. Makin cantik. Kematangan perempuan, kadang bisa sangat mengagumkan. Kami seusia, 45. Dia janda cerai. Aku juga, telah cerai.
Sejak perpisahanku dengan Tita sembilan tahun lalu, aku beberapa kali mencintai perempuan. Sekali aku menjalin hubungan yang dalam, empat tahun kira-kira. Putus. Seperti ada lubang hitam di dalam jiwaku sejak itu. Aku kadung mencandu jatuh cinta, tapi perlahan aku curiga bahwa aku sebetulnya telah agak merasa sia-sia jika hendak mencintai lagi dalam-dalam seorang perempuan. Atau takut? Entahlah. Mungkin.
Tahun ini, aku berpikir sungguh-sungguh tentang usiaku. Waktu yang semakin terasa terlalu cepat berlari. Aku belum punya anak. Aku ingin punya anak. Sudahkah terlambat? Nanda janda yang matang, cantik nian, dan punya dua orang anak remaja. Dari obrolan kencan (ah, maaf, ta’aruf) kedua minggu lalu, Nanda masih membuka kemungkinan punya bayi lagi. Kalau sudah tak bisa melahirkan sendiri, dia berpikir mengangkat anak, begitu katanya sambil membetulkan jilbabnya.
Aku sedang mencoba keluar dari wilayah nyamanku dalam soal cinta. Membidik Nanda, dan mencoba tak berhitung dalam-dalam soal perasaan. Nanda jelas sedang mencari suami lagi. Aku mencoba lebih berhitung segi kepraktisan jika kami memang akhirnya berpasangan. Kepraktisan dalam memenuhi keinginanku punya anak, maksudku. Dari segi ini, Nanda sungguh prospek yang baik sekali. Walau, dunia kami berbeda cukup jauh.
Yang mencolok, soal keagamaan. Nanda gemar mengutip Felix Siauw, ustadz muda yang gemar berjualan ajakan Khilafah Islamiyah dan beberapa kali menampakkan sikap yang bisa dianggap misoginis. Waduh. Dinding Facebook Nanda penuh kata motivasi dari beberapa ustadz televisi yang saat ini sedang popular. Dobel waduh-ku.
Tapi, aku merem saja deh. Mungkin pengetahuan agamaku sebagai mantan aktivis dakwah sewaktu SMA dan kini jadi penulis dan aktivis kesenian, bisa perlahan melunakkan Nanda. Bukankah jika sudah jadi istri, Nanda percaya bahwa dia harus sepenuhnya menuruti suami? Aku tertawa dalam hati. Ini bukan pikiran-pikiran orang yang sedang jatuh cinta.
Aku memang belum jatuh cinta pada Nanda. Aku ingin mencari istri lagi. Maka, malam ini, aku bersiap melangkah lebih jauh dengan Nanda. Aku telah membawa mix-tape yang kurekam di DVD, sampulnya telah kurancang agar memikat Nanda. Ini mix-tape yang sungguh menantang. Bagaimana seseorang yang sangat religius macam Nanda, bisa kurayu dengan sekumpulan musik? Ya, Nanda tak mengharamkan musik. Dia gemar banyak lagu pop dari dalam dan luar negeri. Tapi, aku kan hendak merayunya?
Aku ingin membuat dia terkesan, bahwa aku adalah seorang yang punya religiositas tersendiri. Maka demikianlah, aku merasa harus menyusun album musik religius yang lain dari yang lain! Bukan berisi nasyid, bukan dipenuhi oleh lagu Ebiet dan Bimbo, atau Maher Zein.
Kubuka mix-tape “Islami” ini dengan lagu Alhamdulillah dari musisi hiphop Malaysia, Too Phat, yang juga menampilkan suara Dian Sastro membaca sebuah sajak religius. Ada dua belas lagu. Kusertakan lagu dari Pandai Besi, Debu-Debu Berterbangan. Juga dari Kantata Takwa, Paman Doblang. Juga lagu Iwan Fals dari album Hijau, hanya dicantum berjudul Lagu Satu. Dalam kepalaku, lagu itu terdengar.
Berlomba kita dengan sang waktu
Jenuhkah kita jawab sang waktu
Bangkitlah kita tunggu sang waktu
Tenanglah kita menjawab waktu
Suara Iwan Fals dalam benakku, bersaing dengan suara Bruno Marz menggenangi kafe yang gayeng borjuis ini. Deraan Sang Waktukah yang menyebabkan aku merasa harus buru-buru menyusun mix-tape ini dan hendak memberikannya kepada Nanda malam ini? Kecemasan bahwa waktuku tinggal sedikit lagi?
Hidupku berkelebat, sejenak. Cukup membuat ada yang sedikit nyeri di salah satu ceruk dadaku –sebuah tempat imajiner bagi sesuatu yang secara agak aneh disebut “hati” dalam bahasa Indonesia. Walau ceruk itu imajiner, rasa sakit itu cukup nyata bagiku. Waktu demi waktu telah berlari dalam hidupku. Cinta demi cinta lepas dari jemari tanganku. Sebersit gelisah merayapi gumpalan lunak otakku.
“Assalamu ‘alaykum! Kok melamun begitu?”
Nanda. Sungguh cantik, dia. Apakah aku bisa bahagia dengannya?
Tiba-tiba aku ragu, apakah aku akan memberikan mix-tape di dalam tas ranselku ini kepada Nanda. ***
Jakarta, Juni-Juli 2015
CAK NUR MENYARANKAN FILM
[#arsip : ini esai saya untuk urun esai dalam buku ALL YOU NEED IS LOVE, CAK NUR DI MATA ANAK MUDA (disunting oleh Ihsan Ali Fauzi dan Ade Armando, diterbitkan Yayasan Wakaf Paramadina, 2008). Alhamdulillah, ya, mata saya dianggap masih mata anak muda. #salahfokus Oke. Serius dulu. Yang saya arsip di sini, adalah versi panjang tulisan saya. Yang di buku, sudah dipendekkan, demi ruang. Jika Tuan dan Puan sudi membaca, selamat menikmati.]

Foto diambil dari koleksi pribadi Dwii Setiyawan, di https://dwikisetiyawan.wordpress.com/2009/07/16/nurcholish-madjid-memorial-pictures/
Zaman sekarang, sangat biasa orang merekomendasikan sebuah film. Tapi, di mimbar khutbah Jumat? Itulah yang membuat saya terkesan secara pribadi oleh Cak Nur (Nurcholis Madjid). Suatu ketika pada pertengahan 1990-an, saya shalat jumat di toko buku Wali Songo. Toko buku yang khusus menjual buku-buku Islam ini berada di bilangan jalan Kwitang, dekat Pasar Senen, Jakarta. Ada area khusus untuk shalat Jumat di toko buku ini. Dan pada suatu ketika itu, saya sedikit kaget: di atas mimbar Jumat, Cak Nur dengan kalem menyarankan jemaat Jumatan saat itu untuk menonton sebuah film Barat, The Name of the Rose.
Film ini dibuat oleh sutradara Prancis, Jean Jaques Anaud, dengan bintang utama Sean Connery dan Christian Slater. Film ini merupakan adaptasi dari novel mahakarya filsuf semiotika Umberto Eco. Novel ini banyak dipuji oleh para kritikus sastra dunia, walau pada saat filmnya dibuat dan direkomendasikan oleh Cak Nur, novel dan nama Umberto Eco belum terlalu akrab di kalangan pembaca buku Indonesia. The Name of The Rose mengisahkan misteri serangkaian pembunuhan di sebuah biara Katolik Abad Pertengahan. Rangkaian pembunuhan itu terjadi pada saat pelaksanaan konvensi teologi tahunan.
William of Bakersville dan muridnya, Adso,yang sedang bertamu di biara itu mendekati misteri itu tidak dengan takhyul dan mistik, tapi dengan pendekatan yang pada waktu itu sangat kontroversial dan diharamkan oleh arusutama Kristiani: empirisme dan penalaran rasional. Ternyata, pembunuhan itu terkait dengan sebuah buku klasik terlarang, dan pembongkaran misteri pembunuhan itu juga berarti pembongkaran sendi-sendi ortodoksi Katolik Eropa Abad Pertengahan. “Anda harus menonton film ini,” kata Cak Nur dalam khutbahnya, “film ini bagus sekali.”
Sebelum kita bahas ini lebih jauh, saya ingin bercerita dulu soal shalat Jumat di toko buku Wali Songo.
Keistimewaan shalat Jumat di toko buku Wali Songo adalah mereka sering mengundang tokoh cendekiawan Islam terkemuka untuk jadi khatib. Cak Nur hanya salah satu dari sekian banyak tokoh yang cukup rutin menjadi khatib di situ. Saya ingat Jalaluddin Rakhmat dan Imaduddin Abdurrahim pernah jadi khatib di sana, dan saya hadiri. Saya tak tahu pasti yang lain, tapi rasanya Deliar Noer, Yusril Ihza Mahendra, dan AM. Saefudin pun pernah jadi khatib di situ. (Mungkin sekali ingatan saya keliru tentang Deliar dan Yusril, tercampur dengan pengalaman mendengar mereka sebagai khatib Jumat di masjid UI, Depok.)
Dengan pilihan Khatib para cendekiawan itu (biasanya, masjid toko itu sudah punya jadwal hingga beberapa bulan ke depan), shalat Jumat di Wali Songo jadi menarik. Biasanya, shalat Jumat di masjid umumnya jadi pengalaman yang membosankan. Khatib-khatib Jumat di banyak masjid nyaris tak memberi apa-apa pada saya, selain sederet ayat yang disampaikan tanpa sistematika atau kerangka pikiran yang jelas. Yang disampaikan para khatib konvensial itu biasanya truism belaka dalam beragama: jangan menyimpang dari al-Qur’an dan hadis, harap berakhlak mulia, jangan maksiat, bla-bla-bla. Biasanya, khutbah demikian jadi obat tidur yang manjur buat saya.

Foto diambil dari http://www.djangkarubumi.com/2013/03/toko-buku-wali-songo-senen.html
Nah, beberapa kali saya “memburu” shalat Jumat yang berkhatib pemikir macam Cak Nur. Jadi, sebelum “khutbah The Name of The Rose” yang mengesankan saya itu, pastilah saya sudah punya ketertarikan pada Cak Nur. Terus terang, saya tak pernah mengenal Cak Nur secara pribadi, tak pernah bercakap langsung, dan saya hanya mengenalnya lewat buku atau mimbar. Khutbah Jumat dari Cak Nur itu adalah hal terdekat yang saya punya dengan Cak Nur. Kalau dipikir-pikir, saat dan tempat “khutbah The Name of The Rose”`yang mengesankan saya itu mengandung jejaring makna dan alur sejarah pribadi yang berlapis-lapis.
Pertama, tempat shalat itu, toko buku Wali Songo, adalah sebuah tempat yang lahir dari impian pengusaha buku terkenal, Haji Masagung. Dia adalah pemilik jaringan toko buku Gunung Agung, yang bermula dari sebuah toko kecil di Senen dan pada masa 1980-an tumbuh menjadi jaringan toko buku nasional saingan Gramedia, yang juga mengembang ke dunia penerbitan. Masagung adalah seorang mu’alaf. Ia pernah menarik perhatian nasional ketika membiayai pembuatan film Wali Songo pada 1980-an. Film yang antara lain dibintangi oleh Deddy Mizwar itu sempat bikin heboh karena Masagung mengaku pembuatan film itu dibimbing wangsit.
Memang, sosok para wali yang sembilan dalam film itu (ditambah “wali kesepuluh”, Syekh Siti Jenar, yang digambarkan bak dukun sesat, menganut “mistik hitam”) lebih banyak digambarkan mengandung klenik. Dakwah dan perseteruan yang terjadi, juga berbagai pencerahan pribadi para wali itu, digambarkan sebagai penuh kejadian mistis dan ajaib. Para wali itu digambarkan bukan memiliki pencerahan spiritual, tapi memiliki kesaktian.
Kegandrungan Masagung pada Wali Songo yang mistis itu hadir dalam pemberian nama toko buku khusus Islamnya itu. Di dalam toko buku itu sendiri, pilihan buku Islam yang dijajakan merentang dari buku-buku ibadah praktis, terjemah kitab-kitab klasik, pemikiran Islam yang akademis, sastra Islam, hingga mujarobat dan teori konspirasi Yahudi. Semangat sembilan wali yang sinkretik mewujud dalam pilihan buku yang eklektik. Eklektisme serupa itu lah yang agaknya mendasari pilihan para khatib dan penceramah di toko buku itu (setiap Minggu pagi, mungkin untuk menyaingi misa Gereja, ada acara ceramah Islam di toko buku Wali Songo).
Toko buku khusus Islam ini cukup memengaruhi wajah industri buku Islam di Indonesia. Paling tidak, sejak kehadirannya, industri buku Islam menjadi sebuah subindustri buku nasional yang tegas membedakan diri dari jenis-jenis buku “umum”, menciptakan dunia dan logikanya sendiri. Toko buku ini juga hadir pada saat penerbit buku Islam Mizan sedang ada di puncak kemapanannya dari segi perannya dalam membentuk khasanah pemikiran di Indonesia. Pada saat itu, Mizan punya brand yang baik sekali karena (a) terjemahan buku-buku dari cendekiawan Islam kelas dunia, dan (b) seri Cendekiawan Islam-nya, yang memetakan sekaligus mencuatkan khasanah kecendekiaan Islam di Indonesia. Banyak dari nama cendekiawan muslim yang pernah masuk seri itu menjadi khatib di toko buku Wali Songo.
Semua eklektisme dan “keterlibatan” dalam medan pemikiran Islam di tingkat nasional itu sungguh jadi godaan bagi saya, yang waktu itu adalah seorang aktivis harakah. Sebagai aktivis harakah, tentu saja saya “mengenal baik” nama Cak Nur: dia adalah seorang pemikir yang dianggap telah menyesatkan umat dengan ajaran sekularisasinya.
Di tengah suasana ideologisasi yang penuh semangat, dan terus terang memang jadi “rumah” saya waktu itu dalam beragama, saya mengembangkan hubungan khusus dengan pemikiran Cak Nur. Pada waktu saya kuliah, 1989, saya sudah tertarik dengan pemikirannya ketika membaca pengantar buku yang ia sunting, Khasanah Intelektual Islam. Buku itu adalah antologi cuplikan karya para pemikir Islam sejak Al-Kindy hingga zaman modern. Dan pengantar Cak Nur memberi sebuah kesan yang menantang saya yang sangat harakah waktu itu: orang yang dianggap “antek” Barat/Yahudi ini sama sekali bukan orang bodoh! Pikirannya jernih, bahasanya runut dan logis, dan gagasan-gagasanya penting untuk dipikirkan.
Karena posisi sebagai “lawan tanding” itulah, saya beruntung untuk sejak semula membaca tulisan-tulisan Cak Nur dengan kesadaran kritis. Dan memang, Cak Nur adalah sparring partner yang sangat baik untuk pemikiran Islam. Pikiran-pikiran modernisasi Cak Nur, misalnya (termasuk gagasan sekularisasinya), membuat saya juga berpikir keras dan tergugah mencari bacaan-bacaan tandingan dari khasanah ilmu-ilmu sosial yang waktu itu saya geluti. Saya, misalnya, kemudian tertarik pada berbagai kritik terhadap modernism dan sekularisme, terutama dalam gagasan-gagasan Peter Berger. Sampai sekarang, pemikiran Berger masih menjejakkan pengaruhnya pada saya: khususnya, gagasan tentang demodernisasi dan desekularisasi – di samping gagasannya tentang konstruksi sosial atas kenyataan (yang membantu saya untuk selalu kritis terhadap apa yang dianggap kenyataan oleh arusutama dalam masyarakat).
Ketika saya membaca buku yang mengumpulkan surat-menyurat Cak Nur dengan Mohammad Roem tentang (tidak adanya) konsep Negara Islam, saya pun lantas berkutat dengan berbagai teori tentang Negara dan pemerintahan. Hasilnya? Bukannya saya menyalahkan mutlak Cak Nur, saya malah terhanyut oleh teori-teori kritis tentang Negara, dan membawa saya hingga sekarang meyakini kebutuhan untuk merelatifkan Negara. Walau, sempat juga saya menulis sebuah risalah pendek tentang makna Negara Islam yang saya anjurkan, yakni dengan pendekatan kultural sebagai alternatif dari pemaknaan teologis dan politis terhadap makna dan operasi gagasan Negara Islam.
Singkatnya, jarang saya bersetuju dengan Cak Nur, tapi dalam arti yang bagus –sebuah percakapan gagasan yang hangat. Sikap ini membuat saya tak keberatan menerima berbagai percik ilmu dan anjuran moral dari Cak Nur yang menurut saya sangat memikat. Dan agaknya sikap ini juga menyumbang pada perasaan tak puas terhadap gagasan-gagasan dalam harakah sendiri. Apa yang dilakukan oleh sebagian unsur harakah dalam mencerca, bahkan mencaci dan memfitnah Cak Nur membuat saya merasa tak nyaman.
Setidaknya, ada dua peristiwa dalam hubungan antara harakah dan Cak Nur pada awal 1990-an yang membuat saya bertanya-tanya tentang kelayakan harakah menjawab masalah-masalah modern. Peristiwa pertama (ini bukan urutan kronologis), dalam seminar Percakapan Cendekiawan Tentang Islam (PEDATI –saya lupa yang keberapa) di balairung UI. Di situ, ada pembicara bernama Anis Matta, yang waktu itu dipromosikan oleh banyak teman-teman harakah sebagai cendekiawan yang bisa “meng-counter” Cak Nur. Ternyata, dalam seminar itu, yang dilakukan oleh Anis Matta hanyalah membacakan kalimat-kalimat terseleksi dari tulisan-tulisan Cak Nur dan kemudian membenturkan dengan dalil-dalil (terseleksi juga) dari “logika”, hadis, dan al-Qur’an. Sangat tak sepadan dengan jihad (upaya penuh kesungguhan dan total) akademis Cak Nur dalam merumuskan sebuah gagasan.
Peristiwa kedua, lebih menohok hati saya. Pada awal 1990-an itu terbit sebuah buku kecil dari pengarang dengan identitas tak jelas, yang berisi daftar cendekiawan Islam Indonesia yang dianggap sesat. Cak Nur, Gus Dur, dan Kang Jalal masuk sebagai tokoh utama. Mereka dilabel “budak kuffar”. Dengan sembrono, penulis menciptakan sebuah kategori teologis baru, agar bisa memberi pengukuhan teologis dalam menganggap Cak Nur dan pemikir lainnya sebagai sesat.
Penulis itu rupanya berangkat dari kesadaran bahwa tak dapat dibenarkan (atau, mungkin, kurang strategis) untuk mengafirkan orang yang nyata-nyata bersyahadat dan shalat macam Cak Nur. Maka, ia menciptakan kategori itu: ada orang-orang yang mengaku muslim dan mempraktikkan ibadah Islam, bahkan sebetulnya masuk kategori ulama, menjadi antek kaum kafir. Mereka mengembangkan mentalitas budak terhadap para tuan kafir mereka, membawa-bawa pikiran-pikiran dan agenda kafir ke tengah masyarakat muslim untuk menyesatkan “kita” dari jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan “syariah”. Dalam buku itu, yang beredar di kalangan aktivis musholla di kampus-kampus dan SMA-SMA, kebencian terhadap para “budak kuffar” itu malah lebih terasa daripada kebencian terhadap “kaum kuffar”.
Kedua peristiwa itu membuat saya tak betah lagi berkutat dengan kancah pemikiran harakah yang ada. Tentu, bukan hanya karena kedua peristiwa itu saya tak betah lagi pada pemikiran-pemikiran harakah. Ada beberapa praktik harakah yang tak membuat saya nyaman. Tapi dua peristiwa yang terkait Cak Nur itu termasuk yang paling membuka mata saya, mendesak saya untuk mencari horison pemikiran yang lebih luas.
Bukannya saya lantas jadi pengikut setia Cak Nur dan kaum modernis Islam lainnya. Saya berterimakasih dan menerima “warisan” gagasan harakah yang membuat saya kritis terhadap kenyataan sosial dan keterpurukan umat Islam masa kini. Saya juga tak sepenuhnya bisa menerima gagasan-gagasan modernisme Cak Nur. Tapi, paling tidak, saya menyadari bahwa butuh lebih dari sekadar cacian dan impian akan masa silam untuk menghadapi fakta keras dan gagasan kuat modernisme. Dan pada 1990-an itu, saya mulai lebih berkonsentrasi mengembangkan pemikiran-pemikiran saya sendiri, tak lagi terlalu peduli pada arahan-arahan dan batasan-batasan yang diberikan harakah terhadap dunia pemikiran dan kepenulisan yang saya geluti.
Dan setelah keputusan untuk mengabaikan batas-batas pemikiran harakah itulah saya jadi leluasa mengejar minat-minat pribadi saya, khususnya minat di bidang budaya populer. Apalagi pada pertengahan 1990-an mulai terbit dalam bahasa Indonesia, kumpulan tulisan tentang studi kebudayaan (yang lazimnya banyak membahas ranah budaya pop dalam masyarakat modern) seperti yang diterbitkan oleh Penerbit Bentang (buku Hegemoni Budaya). Dan pada masa inilah saya mendalami lebih serius berbagai bacaan seputar film dan sastra.
Keduanya adalah minat masa kecil saya. Saya waktu itu mulai merasakan bahwa lembaga-lembaga modern seringkali memiliki efek samping membuat pengetahuan-pengetahuan tertentu yang jadi unsur pembentuk jatidiri kita menjadi tidak sah. Misalnya, pengetahuan-pengetahuan tentang musik, film, komik, dan berbagai narasi kecil lainnya, termasuk berbagai kearifan lokal yang diwarisi secara turun-temurun. Pengetahuan-pengetahuan itu paling-paling ditempatkan sebagai “hobi” atau “mitos”. Lembaga-lembaga modern yang saya maksud, mencakup juga dunia harakah (yang hemat saya memiliki ciri modern sangat kuat dalam hal keorganisasian) dan dunia perguruan tinggi di Indonesia saat itu. Nah, pada masa itu, saya juga mulai menulis berbagai hal tentang film dan sastra.
Maka, sungguh terasa segar bagi saya ketika mendengar Cak Nur, di mimbar Jumat, menganjurkan jemaah menonton sebuah film. Sebetulnya, saya tak terlalu kaget Cak Nur menganjurkan film The Name of a Rose (saya terutama kaget karena mimbarnya). Film ini, dan tentu novelnya, adalah (antara lain) sebuah sebuah simulasi pluralisme dan kebebasan berpikir. Umberto Eco membuat sebuah kisah yang mengambil tempat yang tepat untuk itu: sebuah biara di jantung kejumudan berpikir Kristen-Eropa Abad Pertengahan. Digambarkan betapa salah satu topik panas pertemuan teologi tahunan itu adalah apakah Yesus menggunakan dompet (ini penting, kata konvensi itu, untuk menetapkan status kehalalan dompet bagi orang Kristen waktu itu).
William dari Bakersville sendiri adalah sebuah perwujudan sosok Francis Bacon. Ia adalah seorang pastor yang progresif, yang meyakini sepenuhnya bahwa rasionalitas dan empirisme adalah sejalan belaka dengan kehendak Tuhan yang mengaruniai manusia dengan akal. Ia dengan dingin memandang fakta-fakta kematian di biara itu dari segi ilmiah dan motif-motif manusiawi di balik segala pembunuhan itu. Pada akhirnya, ia berhadapan dengan sang pembunuh, dan ia harus berhadapan dengan sebuah kekerasan paham yang tak ingin menerima kemanusiawian manusia (tepatnya, dalam cerita itu, tak ingin menerima humor –ah, Anda bacalah sendiri novelnya; atau, seperti dianjurkan Cak Nur, tontonlah filmnya). Kekerasan paham itu mengangankan sebuah dunia yang suci, yang tunggal dan penuh pembentengan iman.
Dan sesungguhnya, inilah warisan yang paling relevan dari Cak Nur, untuk masa kini. Ia adalah suara intelektual dan suara moral yang kuat untuk pluralisme. Saat ini, pluralisme sedang jadi kata kotor bagi sebagian umat Islam di Indonesia. Banyak kesalahpahaman yang membentuk sikap jijik (atau takut?) terhadap kata dan gagasan ini. Apalagi setelah MUI menfatwakan haramnya pemikiran Sekulerisme, Pluralisme, dan Liberalisme –kata “pluralisme” seolah sinonim dengan kata kafir.
Yang patut disayangkan adalah betapa makna “pluralisme” itu pun jadi tunggal karena fatwa itu. Para penghujat kata ini tak mau lagi menerima horison makna kata ini selain “paham yang menganggap semua agama sama” (pencarian sederhana lewat google.com atau Wikipedia saja akan menunjukkan bahwa pemahaman tunggal ini salah kaprah) –dan dengan ketunggalan makna itu, percakapan pun ditutup. Lebih dari itu, seperti dalam akhir kisah The Name of a Rose, sang penutup percakapan itu merasa amatlah pantas untuk membunuh.
Maka ia pun (berusaha) membunuh sebuah kata, membunuh sebuah pengetahuan, dan akhirnya, membunuh manusia juga. Kemudian, ia merasa harus membunuh sebuah peradaban.***
*versi teredit tulisan ini, ada di buku ini:
MENEMUKAN “LOCHNESS” DI POSO
Catatan: Sebuah arsip lagi, tulisan saya pada 2005. Itu saat saya mulai sering melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia, untuk kepentingan pelatihan dan ceramah.
=====
Saya benci ketinggian. Saya benci terbang. Dan pada 33.000 kaki di atas laut perjalanan saya ke Palu (untuk kemudian ke Poso), saya menatap keluar jendela pesawat, memaki dalam hati, “kalau bukan gara-gara komik, saya nggak bakal di sini!”
Perasaan itu pulalah yang mengendap di benak saya sepanjang saya di Poso (tepatnya di Siuri, kompleks cottage di Tentena), 6-7 jam dari Palu. Saya di sana pada 15-18 Mei 2005, dan pada 19 Mei 2005 pagi, saya pulang ke Jakarta –lagi-lagi dengan pesawat (arrgh!). Kalau bukan gara-gara komik, saya mungkin tak bakal ke daerah konflik macam Poso, atau ke Madura tahun lalu.
Saya ke Poso diundang oleh Common Ground Indonesia (CGI) untuk menjadi salah satu fasilitator dalam workshop “Media dan Transformasi Konflik”. Sebetulnya workshop ini adalah pembekalan para calon pendamping dalam program komik pendidikan CGI, seri Poso. CGI adalah salah satu LSM yang punya program serius sehubungan dengan komik. Di tengah lesunya produksi komik Indonesia, komik-komik “proyek” pesanan LSM lumayan jadi fenomena menarik.
Selain CGI, paling tidak ada 2 komik “proyekan” yang menurut saya bagus dan fenomenal. Petualangan Wening dkk., Selalu Ada Jalan Pulang (terbitan ICMC), sebuah komik pendidikan/pembekalan untuk para TKW, terutama fenomenal karena jumlah eksemplarnya 100.000 –mungkin cetakan terbanyak untuk komik Indonesia. Semuanya dibagikan gratis kepada para calon TKW. Komiknya, digambar oleh M. Ariv Russanto & Didi Purnomo, sendiri lumayan bagus (gambarnya, maupun ceritanya), dicetak berwarna, dan lumayan tebal.
Yang kedua, komik tentang pengungsi dari LSM Baris Baru, berjudul Mereka Yang Mengungsi. Barangkali, ini salah satu novel-grafis Indonesia mutakhir yang terbaik dari segi gambar (oleh Chedarr). Dalam warna hitam putih, tarikan garisnya sangat kuat dan penggambaran setting serta pengadegannya terhitung luar biasa. Ceritanya pun cukup dramatis dan nyastra –hampir tak terasa sebagai komik “proyekan”. Sayang komik ini tak dijual untuk umum, dan saya belum mendengar komikusnya bikin komik lain.
CGI sendiri terhitung paling serius meluncurkan program komiknya. Yang pertama meluncur adalah seri Gebora, untuk para remaja di Kalimantan dan Madura. Seri ini sudah terbit 12 judul, masing-masing setebal 48 halaman, dicetak berwarna, dengan format seukuran komik Amerika, tapi dengan sampul dan kertas yang lebih tebal. Kalau tak salah, masing-masing terbit 12.000 eksemplar. Sebagian dari komik itu dibagikan sebagai ujicoba di Poso-Tentena.
Perang Agama, Damai Etnik
Kita tahu, Poso-Tentena adalah salah satu wilayah konflik agama paling keras di Indonesia pascareformasi. Konflik itu sudah merupakan perang agama. Saya dan rombongan kecil dari Jakarta datang dari Palu tiba di Poso larut malam. Di pos perbatasan Poso-Parigi, kami distop dan diperiksa oleh aparat keamanan yang jaga (dari kesatuan Brimob).
Kira-kira semenit setelah meninggalkan pos, listrik di Poso (di sebagian besar wilayah kabupaten itu) mati. Wah! Rupanya sih ini peristiwa biasa, karena jatah PLN terbatas (kayak Jakarta pada awal 1980-an saja). Tapi buat saya yang terbiasa pada terang Jakarta dan terhantui cerita-cerita perang di Poso, kan mencekam juga menyusuri jalan gelap dan pos demi pos jaga itu.
Toh perjalanan lancar. Rata-rata orang Tentena-Poso yang saya temui selalu meyakinkan saya bahwa Poso telah aman. Kalau dikorek-korek sedikit, beberapa mengakui memang kadang masih terjadi pemboman dan pembunuhan atau aksi massa provokator. Tapi konflik antara Muslim di Poso dan Kristen di Tentena, secara umum, telah mencapai titik damai. “Kami sudah capek, perang terus!” kata Jimi, mantan combatan dan salah satu komandan elite milisi Kristen yang kini aktif di Crisis Centre dan bekerja untuk proses perdamaian.
Tentu saja perdamaian ini masih dalam proses. Saat ini terjadi segregasi atau pemisahan wilayah antara penduduk Muslim (di Poso) dan penduduk Kristen (di Tentena), yang masih sukar dicampurkan. Fadian, seorang aktivis perdamaian dan pegawai pemda, bercerita tentang Taman Anggrek di Tentena yang sebelum konflik selalu ia kunjungi –seringkali bersama rekan-rekan peneliti dari Jawa (ia rupanya berlatar pendidikan biologi). Taman Anggrek itu lahan penelitian botani dan hewani yang luas –di sana, misalnya, ada anggrek hitam yang hanya ada di Indonesia/Sulawesi. Tapi sudah empat tahun ini ia tak pernah lagi ke sana. “Setelah konflik, tak ada muslim berani ke sana,” katanya. Ia tak tahu apakah Taman Anggrek yang merupakan kekayaan dunia itu masih terpelihara atau tidak.
Toh proses itu ada. Sekarang, Jimi dan beberapa mantan combatan Kristen lain duduk bersama Ibrahim, mantan combatan Islam (salah satu komandan juga), tertawa-tawa bertukar cerita tentang perang. Kalau sudah ngobrol begini, mereka bisa begadang semalaman. Dasarnya orang Poso-Tentena rupanya adalah para periang dan pelawak. Mereka alamiah saja melucu, melontar anekdot, dan tertawa terbahak-bahak. Rupanya perang yang mengerikan itu menyimpan banyak juga cerita lucu.
Di antara mereka, tampak Alex, aktivis crisis centre GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah), memakai kaos bertuliskan Arab Laa Ilaha Illallah. Para peserta workshop bercampur antara mereka yang menggunakan kalung salib dan berjilbab. Seperti kata Jimi, mereka (para aktivis perdamaian) kini sudah amat kompak: “Kalau ada aparat sedang mencari Ibrahim, misalnya, ia akan kami sembunyikan. Demikian juga kalau aparat yang mencari saya, Ibrahim akan menyembunyikan saya di daerah muslim.”
Baik para aktivis, para mantan combatan, maupun mantan pengungsi yang kini jadi penduduk biasa yang hidup dalam segregasi itu, rata-rata kini merasa bahwa perang agama itu dibikin oleh pihak ketiga dari luar. Sekarang, berbagai simpul damai sedang diikatkan kembali. “Kami lihat, budaya kami, etnik kami, bisa menyatukan kami lagi,” kata Jimi. Makanya acara-acara seni macam pentas Tari Dero (sejenis tari gaul ajang cari jodoh) dan festival budaya Poso September nanti bakal terus dihidupkan lagi.
Monster (semacam) Lochness?
Salah satu milik bersama rakyat Poso adalah Danau Poso. Di tepi danau inilah festival budaya seringkali diadakan. Danau ini memberi sensasi unik bagi rombongan kecil kami dari Jakarta. Di tepi danau, kami menatap debur ombak menghantam pantai dengan keras. Kami datang di saat musim ombak. Ombak? Pantai? Ya, danau ini bak laut saja tampaknya. Tapi begitu angin tenang, ombak reda, dan saya memberanikan diri masuk danau –airnya tawar! Maka percayalah kami, ini memang danau.
Ternyata danau ini menyimpan legenda besar. Orang sekitarnya menyebut itu legenda “lampu danau”. Heh, rasanya culun memang nama ini. Setiap malam, selalu ada cahaya yang hilang timbul sepanjang malam, yang berjalan cepat di beberapa bagian danau. Cahaya itu kecil saja. Saya melihatnya, dan kalau tak diberitahu Jimi, pasti saya mengira itu lampu kapal nelayan. Jimi menerangkan mengapa itu tidak mungkin. Kebetulan memang saat saya menyaksikan itu, ombak sedang besar dan hujan membungkus danau. Gerak-geriknya juga, menurut Jimi, tak serupa dengan gerak-gerik boat. Lagipula kadang cahaya itu berpendar kuning, kadang berpendar biru.
Dalam bahasa awam orang sekitar, “lampu” itu dipercaya bagian tubuh seekor naga. Entah matanya yang menyala, atau mungkin kulit tubuhnya yang barangkali terlapis fosfor. Lho, apa hubungannya cahaya itu dengan naga? Apa ada penampakan? Saya banyak disaran untuk mengobrol dengan orang-orang tua yang tinggal di kampung-kampung sekitar danau. (Sayang saya tak punya waktu banyak di sana!) Penampakan terakhir, kata Jimi, pada 1986.
Waktu itu, penduduk salah satu kampung di tepi danau Poso melihat sesuatu yang berenang melintas danau di siang bolong. Mereka mengira itu kijang, karena kijang dikenal sebagai perenang yang tangguh. Dengan antusias mereka ramai-ramai ke perahu motor mereka, mengejar “kijang” itu. Sekitar 20 m. dari si makhluk (perahu paling depan malah hanya sekitar 10 m. dan awaknya sudah bersiap menombak makhluk itu), terlihatlah oleh mereka bahwa makhluk itu sama sekali bukanlah kijang!
Makhluk itu, kata sebagian orang, berkepala seperti kuda. Tubuhnya menjulur seperti ular raksasa, hilang timbul meliuk-liuk di permukaan danau. Para penduduk kampung itu pun bubar dengan panik, terbirit-birit kembali ke tepi. Untuk beberapa saat, sang makhluk itu berenang dengan gemilang di siang bolong itu.
Saya tentu saja terpana. Apalagi ketika Jimi bilang bahwa salah satu cara untuk memancing “lampu danau” agar menampakkan cahayanya adalah dengan menyalakan lampu motor dan menderamkan mesin motor kita ke arah danau. Saya teringat pada sesuatu yang saya baca sewaktu kecil: monster danau Lochness! Seingat saya, salah satu yang konon memancing keluar si Nessie (panggilan akrab sang monster) adalah memang lampu dan deram mesin motor.
Dari sejumlah karakter danau Poso yang saya dapati saat itu, memang banyak persamaannya dengan danau Lochness. Danau Poso terletak di pulau dengan kontur berbukit-bukit seperti lingkungan Lochness di Skotlandia sana. Luas danau Poso adalah 39 X 12 km. Volume airnya lebih besar daripada danau Toba, karena danau Poso tak punya pulau di tengahnya seperti Toba. Menurut Fadian, ada penelitian yang mencatat bahwa di danau Poso ada palung dengan kedalaman mencapai 1300 m.
Salah satu teori tentang monster Lochness adalah ia/mereka merupakan makhluk yang tinggal di laut dalam, dan sesekali masuk ke danau karena ada semacam terowongan di kedalaman danau itu yang menghubungkan Lochness dan laut. Saya tanya kemungkinan itu kepada Jimi. Ia bilang, mungkin saja. Ia ingat, kakaknya pernah membuat skripsi tentang temuan sejenis ikan purba di danau Poso. Penduduk setempat menyebutnya ikan Bongo, berbentuk seperti ikan gabus.
Kakak Jimi mendapati info tentang ikan Bongo (dan mendapati bahwa ini sejenis ikan purba) dari sumber yang jauh dari Poso: di perpustakaan IPB, dan dari sebuah dokumen penelitian yang dikirim dari Jepang. Menurut dokumen itu, ikan Bongo sama dengan ikan Putri (terjemahan dari nama Jepangnya) yang di Jepang sendiri telah punah. Nah, pernah ketika sebuah gunung di dekat laut meletus, ikan-ikan Bongo di danau Poso tampak bermatian karena panas. Jangan-jangan, kata Jimi, memang ada semacam terowongan di kedalaman danau Poso yang terhubung ke laut.
Wah! Ini sebetulnya bisa jadi bahan penelitian yang menarik. Saya ingat, legenda Lochness ternyata bukan eksklusif milik danau Lochness. Di seluruh penjuru dunia, di danau-danau dengan karakter serupa Lochness, penampakan serupa Nessie memang sering dilaporkan. Saya lupa, apakah dulu danau Poso disebut-sebut juga dalam soal ini. Teman saya serombongan dari Jakarta, Indrajati dari Yayasan ARTI, mengomel akan tiadanya di Indonesia minat meneliti danau sedahsyat Poso ini. Saya mendesah, dan sepakat.
Saya pun melamun: paling tidak, danau ini –juga seluruh Poso dengan segala pengalamannya sebelum, selama, dan sesudah konflik– bisa jadi bahan menarik untuk cerita komik.
Komik untuk Poso
Program komik untuk Poso dari CGI masih di tahap penjajagan. Edisi pilot atau no. 0 yang telah dibuat memang bagus, menurut saya, jauh lebih bagus dari seri Gebora. Baik ceritanya, maupun (terutama) gambarnya yang cenderung pada gaya clear line. Tapi itu pendapat saya sebagai pembaca Jakarta, yang punya banyak referensi bacaan komik.
Ternyata di Poso, komik praktis hilang sebagai bacaan umum sejak sekitar 1995. Dulu, akses pada komik didapat dari taman-taman bacaan. Kini taman-taman bacaan itu telah hilang. Kalau mau beli komik, mesti ke Palu dulu, ke toko buku Ramedia (bukan Gramedia). Itupun yang tersedia paling jenis manga. Walhasil, komik kini adalah bacaan elitis. Kebanyakan penduduk Poso tak lagi akrab dengan komik, atau buku secara umum. Bukannya lantas mereka kini miskin info. Satu-satunya akses media mereka kini adalah antene-antene parabola yang bisa menangkap baik siaran TV nasional maupun siaran internasional macam CNN atau Channel 5 dari Prancis.
Dengan kenyataan ini, saya harus mengubah penilaian saya. Walau komik pilot berjudul seri Perjalanan Mencari Sahabat itu memang bagus, tapi ia mengandung banyak konvensi pembacaan komik yang mungkin telah asing bagi para pembaca anak di Poso. Misalnya penyusunan panel dan urutan membacanya, atau idiom-idiom komik macam sound effect, atau penyusunan balon kata dan bagaimana membacanya. Jadilah saya lebih menekankan pada konvensi-konvensi pembacaan itu. Saya juga mempromosikan medium komik mini-fotokopian 8 halaman, yang saya uraikan dalam bentuk komik-mini fotokopian 8 halaman.
Dalam perjalanan pulang, di ketinggian (kali ini) 34.000 kaki di atas laut, saya menatap keluar jendela pesawat. Saya masih benci terbang. Tapi saya semakin mencintai komik, yang telah membuat saya mengalami ini semua.***