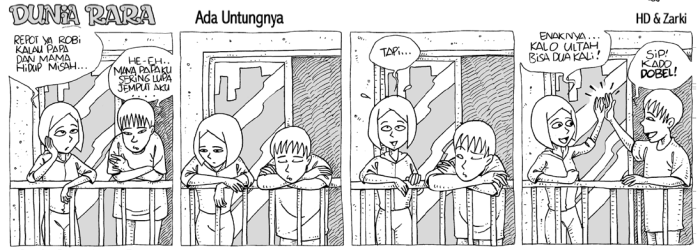Archive for the ‘Uncategorized’ Category
Masjid dan Keretakan Bangsa
#arsip Ini tulisan saya, kalau tak salah, pada 1997. Saya tak yakin juga ini pernah dimuat di mana. Membaca tulisan ini, saya jadi mesem-mesem sendiri: saya “anak musholla” banget ya 🙂
Pasar murah sembako di masjid? Transaksi jual beli di rumah Allah? Secara iseng, orang bisa bilang bahwa itu versi harfiah dari ungkapan Akbar S. Ahmed dalam Posmodernisme dan Islam : masjid bersaing dengan mal!
Tentu saja maksud Ahmed bukan itu. Ia kurang lebih menyoroti betapa mal menjadi kuil manusia modern dalam memusatkan hidupnya. Dalam masyarakat muslim, masjid memiliki sejarah panjang sebagai pusat sosial, dan kini tergerus oleh mal-mal.
Mal adalah kuil pemaknaan manusia modern terhadap hidup mereka yang didefinisikan oleh ekonomi. Bukan kebetulan jika kita, Indonesia Orde Baru (dengan mengambil Jakarta sebagai pusatnya), menampakkan gairah belanja luar biasa yang ditandai maraknya mal-mal.
Menurut MEDIA INDONESIA (16/1/1997), total tanah untuk area mal-mal di Jabotabek yang telah maupun akan dibangun adalah 4.132.480 m2. Sebelum krisis, sedang antri pembangunan mal di Ancol, Bintaro dan BSD, masing-masing seluas 200.000 m2 atau lebih. Semua itu lahir dalam suatu Orde yang menjadikan ekonomi sebagai panglima dalam melakukan nation building menjelang milenium ketiga.
Dan justru ekonomi lah yang mengkhianati Indonesia Orde Baru!
Reformasi = pertanyaan
Krisis telah (selalu) membawa hikmah luar biasa. Siapa sangka, krisis yang semula ‘sekedar’ jatuhnya rupiah di bulan Agustus akan membuka jalan bagi desakan amat kuat untuk reformasi ekonomi-politik (juga sosial, dan akhirnya – atau mulanya? – budaya) yang telah lama diidamkan, dan disuarakan, oleh sebagian orang berakal sehat di negeri ini sejak lumayan lama.
Reformasi bermula dari pertanyaan, dari ketidakpuasan pada apa yang ada – pada status quo. Jika suatu pertanyaan dibiarkan tumbuh secara wajar, reformasi akan tumbuh, insya Allah, secara wajar pula. Jika pertanyaan muncul karena paksaan keadaan, reformasi bisa jadi juga akan tumbuh secara ogah-ogahan, merasa terpaksa, dan bisa jadi menuntut biaya (amat mahal, malah).
Di samping itu, pertanyaan yang lahir dari keadaan yang mendesak bisa jadi akan berujud pertanyaan-pertanyaan panik. Maka pertanyaan-pertanyaan salah kaprah bisa tumbuh subur, menyesatkan, mengarahkan pada reformasi yang seolah-olah saja. Tercakup dalam “pertanyaan salah kaprah” adalah pertanyaan yang benar, tapi diutamakan lebih dari porsi seharusnya.
Secara kasar, pertanyaan dasar dalam krisis kita bisa disederhanakan jadi soal “siapa” dan “kapan”, atau “apa” dan “bagaimana”. Dalam panik karena pukulan krisis moneter yang tak habis-habis, banyak yang bertanya “siapa” (padahal lebih penting bertanya “apa”) dan “kapan” (padahal lebih penting bertanya “bagaimana”).
Pada awal krisis, misalnya, populer pertanyaan “siapa yang jadi biang keladi krisis”? Mencari kambing hitam sempat jadi keasyikan nasional: sebagian menunjuk para spekulator, dengan mengikuti suara galak Mahathir yang menghujat Soros. Sebagian lain menunjuk para konglomerat. Hingga kini pun, kambing hitam masih laku.
Dalam talk show Liputan Khusus SCTV, 25/2/97 lalu, Ekky Syahrudin sang wakil rakyat masih yakin membatu bahwa krisis moneter akibat ulah spekulator. Ia percaya CBS, karena agaknya yakin ungkapan “jurus yang akan mematikan para spekulan”.
Beberapa waktu sebelumnya, ramai soal Sofjan Wanandi dan CSIS. Dalam acara peluncuran program KAUM di Masjid Sunda Kelapa, 27/1/97 lalu, Syarwan Hamid menyebut “tikus-tikus” yang menyebabkan krisis sedemikian parah begini. Di beberapa tempat, masyarakat memutuskan bahwa “Cina”-lah masalahnya. Pers juga ikut disalahkan karena dianggap memperparah situasi dengan “menyebarkan berita-berita yang tak benar dan membingungkan”. Mungkin sebentar lagi, para ahli yang meragukan CBS atau orang-orang yang skeptis pada calon wapres pun akan ditunjuk sebagai penyebab rupiah tak stabil.
Kita terus berkutat pada pertanyaan “siapa”. Apalagi saat krisis ekonomi bergeser menjadi tuntutan reformasi politik demi efektifnya reformasi ekonomi. Ramailah orang menyoal siapa pemimpin bangsa untuk masa depan, siapa wapres (yang dianggap jabatan strategis untuk reformasi politik ke depan). Jelas, dalam politik praktis, “siapa” adalah soal amat penting. Tapi di tengah euphoria pertanyaan “siapa”, ada bahaya masalah reformasi ekonomi dan politik tergemboskan maknanya. Semua orang bicara “reformasi”, semua merasa mengerti, tapi tanpa sadar meluputkan soal “apa” di balik reformasi.
Padahal, mementingkan “apa” dalam agenda reformasi akan memberi kerangka kerja yang lebih tahan lama dan fleksibel. Siapapun wapres atau presiden kita, agenda reformasi yang jelas mestinya tetap berjalan dan dijalankan. Siapapun yang berkuasa, sistem ekonomi kita mestilah diupayakan selalu produktif dan bersih dari korupsi, kolusi dan manipulasi; siapapun pemimpin bangsa, sistem politik harus diupayakan selalu partisipatif dan transparan. (Memang ada saat “siapa” jadi pertanyaan penting, khususnya dalam politik; tapi saya ragu apa Indonesia sudah sampai ke titik itu?)
Sejalan dengan itu, pertanyaan “kapan” tak sepenting “bagaimana”. Ya, penting memang soal kepastian kapan rupiah stabil. Tapi soal kurs cuma kulit dari masalah ekonomi, apalagi jika masalah ekonomi itu sudah bermatra politik-sosial, bahkan budaya, seperti di Indonesia kini. Tak ada formula ajaib untuk seluruh masalah itu. Setiap pilihan punya konsekuensi yang mesti ditanggung bersama oleh bangsa Indonesia (dan itu biasanya berarti lebih banyak ditanggung oleh rakyat kebanyakan).
Tapi desakan “kapan” mungkin akan menendang jauh-jauh soal “bagaimana”. Keinginan mendapat hasil segera bisa membuat kita dengan panik “menjual jiwa kepada iblis”: pakai apa sajalah, yang penting rupiah stabil besok!
Retak, rekat
Kepanikan tersebut amat terasa pada saat ikatan kebersamaan runtuh, saat semua orang merasa tak bisa mengandalkan orang lain dan harus menyelamatkan diri sendiri. Kiamat belum tiba, tapi psikologi “ibu melupakan anak yang disusuinya” sudah terhidang di depan kita.
Saat rush belanja beberapa waktu lalu, sesuatu yang dahsyat terjadi: “orang lain” (mencakup orang-orang Irian yang mati kelaparan, orang-orang kampung yang sama butuhnya pada susu dan sembako tapi tak punya duit, para penganggur korban krisis moneter) jadi demikian abstrak bagi para pelaku rush, hingga derajat tiada. Saat orang tarik urat berebut minyak goreng, tak ada “Indonesia”, yang ada hanya perut sendiri.
Bangsa ini memang telah retak sejak lama. Senjang demi senjang telah membelah bangsa ini: senjang antara yang kaya dan yang miskin, senjang antara yang berkuasa dan yang tidak, antara elite dan rakyat alit; belum senjang antara idealitas kenegaraan dan praktek birokrasi di lapangan, senjang antara cita-cita/harapan dengan kenyataan, antara yang simbolik dengan yang keseharian.
Contoh mutakhir dari senjang antara yang simbolik dengan yang realistik adalah gerakan cinta rupiah dan cinta tanah air. Masyarakat, kita tahu, kini menderita ketakpercayaan yang akut pada Pemerintah (nyaris setiap ada kebijakan pemerintah soal krisis moneter, respon pasar adalah rupiah jatuh atau capital flight ). Tapi apa respon kita? Tipikal: bikin stiker, bikin acara jor-joran, bikin slogan – simbol, simbol dan simbol! Sementara mal-mal tetap ramai, dan valentine night di kafe-kafe tetap penuh.
Masyarakat, bangsa, yang retak perlu direkatkan kembali. Masyarakat jangan dibiarkan jadi keping-keping yang terserak tak berdaya. Disintegrasi jadi soal yang krusial untuk kita saat ini: kita tak ingin nasib Lebanon, Yugoslavia, Aljazair (dan, kalau mau jujur, negeri kita di jaman PKI) menimpa kita; kita tak ingin antar tetangga jadi musuh dan masyarakat terjerumus dalam kegelapan teror. Itu tak bisa diupayakan sekedar lewat simbol dan upacara. Dan itu juga tak bisa melalui keasyikan Pemerintah mengupayakan sendiri semuanya, mengasyiki penjagaan kemapanan perannya sebagai pusat, termasuk dalam menyelesaikan soal krisis kini.
Berhentilah mengidentikkan stabilitas pemerintahan sama dengan stabilitas masyarakat. Berilah ruang seluas mungkin pada masyarakat untuk mengupayakan sendiri kebersamaan mereka – ajak masyarakat berdialog soal apa saja yang mungkin menimpa mereka, dan bagaimana mengatasinya; jangan tetap membudayakan “bermain dalam gelap”, yang bertumpu pada keharusan pasifnya masyarakat.
Community centre
Di situlah perlunya community centre (pusat kemasyarakatan) yang aktif dan efektif. Dalam situasi normal pun selalu perlu ada lembaga-lembaga yang bisa jadi perantara individu dengan Negara. Ruang bagi masyarakat untuk mengupayakan kebersamaan perlu dilembagakan. Dan untuk Indonesia, masjid-masjid bisa berperan demikian.
Sebetulnya, bukan cuma masjid, tapi pusat-pusat ibadah. Masjid menjadi strategis karena memang umat Islam adalah mayoritas. Lebih strategis lagi jika, seperti ajakan Amin Rais dan Adi Sasono dalam peluncuran KAUM (Komite Aksi Untuk Masyarakat korban krisis moneter), masjid tak membatasi aksi sosialnya hanya pada umat Islam saja, tapi juga pada umat agama lain. Betapapun, rakyat adalah rakyat, korban adalah korban dan pertolongan mesti selalu diberikan.
Secara teoritis, masjid, atau pusat ibadah, akan menjadi lembaga yang efektif untuk memberi kubah pemaknaan bagi individu-individu, anggota masyarakat, yang kehilangan orientasi dalam realitas yang retak seperti kini. Saat semua yang stabil, taken for granted, tak bisa diandalkan lagi, seseorang perlu membangun lagi pemaknaan baru, atau menyegarkan kembali pemaknaan yang telah ia miliki. Dan melalui pemaknaan bersama, kata “Indonesia” akan kembali berarti, kongkrit dan hadir dalam keseharian. Masjid/pusat ibadah bisa mengakomodir proses itu.
Secara praktis, tentu saja banyak masalah. Orang, misalnya bisa menyorot risiko primordialisme yang bisa berkembang jadi tribalisme yang populer di jaman globalisasi ini. Dalam hal masjid, di lapangan masih muncul kendala warisan lama: “masjid NU” atau “masjid Muhammadiyah” masih jadi kategori kerja para aktifis masjid. Belum lagi soal-soal SDM, soal-soal kemampuan organisasional dan manajerial yang di kebanyakan masjid bagai makhluk dari planet lain: asing dan cenderung dimusuhi (atau setidaknya tak dianggap penting).
Ya, banyak masalah. Tapi itu tak mengurangi nilai strategis masjid/pusat ibadah dalam situasi krisis kini. Bermula dari penyaluran sembako, masjid-masjid bisa mengembangkan diri jadi pusat kegiatan masyarakat yang aktif dan efektif: jadi penyalur dana masyarakat, pusat pertemuan, kegiatan makan bersama, bahkan tempat memupuk ketrampilan dalam rangka mempersiapkan diri menyongsong wajah ekonomi yang berubah akibat bantua IMF dan globalisasi.
Dalam bahasa seorang rekan: daripada para pengangguran (yang notebene banyak yang intelektual) itu turun ke jalan, kan lebih baik kumpul-kumpul di masjid…. ***
Pelajaran Kebangsaan Baru
#arsip Ada masanya, saya mengkliping (dengan secara fisik menggunting koran dan menyimpannya) tulisan-tulisan saya yang dimuat di media massa. Sekarang, entah di mana kliping-kliping itu. Awal saya menulis di media massa, kebanyakan membahas soal-soal kebudayaan dengan fokus masalah Negara-Bangsa, dan politik Islam, atau mengulas buku-buku sastra dan kebudayaan secara umum. Ini salah satunya, tulisan tahun 1997, saya lupa dimuat di mana. Waktu itu, terasa ada yang sedang mematang, seperti akan terjadi sesuatu yang besar, di Indonesia. Kekuasaan sudah busuk, semua terasa sedang was-was menunggu entah apa. Sekarang, kita tahu apa yang terjadi kemudian.
Eep Saefullah, dalam acara buka puasa Lembaga Studi Ilmu Sosial 18 Januari 1997, mengungkapkan beberapa pendekatan dalam menyikapi kasus-kasus kerusuhan baru-baru itu. Eep memisalkan kasus-kasus tersebut sebagai “bom waktu” – dan ada dua sikap terhadap “bom waktu” itu: yang pertama – yang lebih populer dalam sikap-sikap resmi Pemerintah dan ekspos media massa – adalah mencari siapa “penyulut bom” tersebut; yang kedua, mencari penyebab adanya “bom” itu dan siapa (atau apa) pembuatnya.
Menurut Eep, sikap kedua lebih penting dilakukan. “Sang penyulut” hanyalah meledakkan “bom” yang telah tersedia belaka. Sementara pertanyaan utamanya adalah: mengapa Indonesia menjadi lahan yang begitu subur bagi “bom-bom waktu” tersebut?
Jika sikap kedua diambil, masih menurut Eep, maka ada dua penjelasan yang mungkin dikemukakan: penjelasan teologis dan penjelasan ekonomi-politik. Penjelasan teologis beranggapan bahwa terdapat unsur-unsur yang potensial radikal dalam doktrin dan sistem keimanan agama yang tersangkut kerusuhan. Eep mencontohkan penelitian oleh Kompas tentang “agama protes” di Pesisir Timur Jawa untuk penjelasan pertama. Sedang penjelasan kedua – yang menjadi pilihan Eep – beranggapan bahwa soalnya terletak pada masalah struktural.
Keberbedaan, identitas
Yang masih luput dibicarakan adalah penjelasan problem identitas. Barangkali tak ada hubungan langsung antara amuk massa di Situbondo, Tasik dan Kalimantan dengan problem identitas. Tapi sentimen (krisis) identitas – dibahasakan atau tidak – sesungguhnya lebih mudah kita temui dalam keseharian kita. Bahkan seringkali penjelasan identitas menjadi penjelasan common sense dalam “analisa warung kopi” tentang berbagai gejala ketegangan sosial di sekitar kita (misalnya pengaitan kerusuhan dengan isu Kristenisasi; atau kebencian terhadap etnis Cina). Karena itulah – karena ia ‘sekedar’ sebuah “analisa warung kopi”, mungkin, problem identitas menjadi penjelasan yang kalah pamor dibanding penjelasan lain. (Agaknya yang paling aman adalah tidak menggunakan/memaksakan suatu pendekatan tunggal)
Tapi problem identitas lah benang merah yang membuat kerusuhan di Situbondo, Tasik dan Kalimantan relatif unik dibanding kerusuhan 27 Juli: jika pada kerusuhan 27 Juli alasan yang dikemukakan oleh para pelaku kerusuhan adalah politik, pada tiga kerusuhan di daerah tersebut terangkat alasan yang berbeda. Di Situbondo dan Tasik: pelecehan agama (di Tasik, tidak langsung menyangkut pelecehan agama – tapi penganiayaan aparat polisi/Negara terhadap “aparat” agama). Di Kalimantan: konflik etnis, antara Dayak dan Madura. Kerusuhan di Timor Timur beberapa waktu lalu juga mengangkat soal (pelecehan) agama.
“Agama” dan “etnis”, adalah kata yang merujuk pada keberbedaan yang primordial. Kenyataan bahwa perbedaan tersebut bisa meletupkan kekerasan massal menunjukkan bahwa sekedar retorika anti-primordialisme saja tidak cukup. “Primordialisme” telah menjadi kata yang bersifat rapalan, sedemikian rupa, sehingga bobot persoalannya menjadi diremehkan dan dientengkan. Seolah, seseorang (atau suatu masyarakat) dengan pilihan terhadap modernitas akan dengan mudah meninggalkan kenyataan-kenyataan primordialnya.
Kenyataan primordial adalah sesuatu yang menghujam dalam pada diri seseorang. Kenyataan primordial adalah sebuah rujukan akan keberbedaan yang mendasar. Ketika nasionalisme – sebagai representasi proyek modernisme – datang, ia ingin menggusur keberbedaan itu, menggusur segala yang dinisbatkan sebagai “alam dan warisan tradisional”, dan menggantikannya dengan sebuah “alam” baru, entitas baru. Nasionalisme menginginkan keberbedaan primordial jadi tak relevan – loyalitas seseorang terhadap bangsa dan negara lah yang penting.
Apakah “bangsa”? Sebuah imagined community, “komunitas yang dibayangkan” (Anderson, 1983). Apakah “Negara”? Organisasi yang menaungi dan mengkoordinasi imagined community tersebut.
Cara nasionalisme menangani keberbedaan primordial mengalami evolusi. Pada mulanya keberbedaan ditangani dengan menyodokkan sikap yang secara naif memandang nasionalitas sebagai sebuah entitas yang bulat, sebuah gestalt, yang utuh dan tanpa kompromi mensubordinasi kenyataan-kenyataan primordial. Itulah nasionalisme-nya Mohammad Yamin dan Soepomo (dengan model negara integral-nya). Nasionalisme macam itu masih populer – tentu dengan berbagai adaptasi dan modifikasi agar tetap up to date (paling tidak secara retoris).
Penanganan keberbedaan yang kedua menghadirkan nasionalisme yang lebih halus dan apresiatif terhadap keberbedaan primordial. Pendekatan itu relatif belum melembaga di Indonesia, walau mulai populer setelah sekian lama hanya dikenal di kalangan budayawan dan ilmuwan sosial saja. Pendekatan itu sering diistilahkan sebagai multikulturalisme.
Sayangnya, multikulturalisme belum bisa keluar dari perangkap gestalt. Ia dibangun berdasarkan asumsi adanya sebuah budaya pusat. Seperti kata James Donald dan Ali Rattansi: dalam praktek, multikulturalisme gagal mengenali hirarki kekuasaan dan legitimasi sehubungan dengan keberbedaan yang masih terus berlanjut; multikulturalisme mendefinisikan budaya lain (yang bukan pusat atau bukan ”budaya nasional”) dengan oposisi A : bukan-A, ketimbang pembedaan A : B, A : C, atau A : n …(Donald & Rattansi, 1992). “Bukan-A” adalah berarti – dalam praktek – adalah subordinat, perlu “disesuaikan”, “dididik” dan “dibina”.
Pandangan gestalt memerangkap karena ia luput menangkap kenyataan partikular. Individu, dengan segala kenyataan primordial dan non-primordial yang melekat dalam dirinya, adalah kenyataan partikular. Nasionalisme membawa orang-orang Madura ke Kalimantan. Di sana, atas nama Nasionalisme gestalt, orang Dayak dan orang Madura dituntut untuk meniadakan sentimen kesukuan. Tapi ketika terhampar masalah kongkret berupa jurang sosial-ekonomi, seorang Dayak awam – hampir secara instingtif – menengok kepada sesuatu yang ia rasa bagian dari dirinya sejak lahir: ke-“Dayak”-annya. (Barangsiapa beranggapan sentimen etnis, dan agama, sebagai “warisan lampau”, cobalah lihat bahwa massa yang terbakar di Situbondo, Tasik dan Kalimantan adalah kebanyakan kaum muda…)
Sentimen macam itulah yang dengan mudah dibakar, terutama ketika dikombinasikan dengan problem sosial-ekonomi-politik yang nyata, plus hadirnya “penyulut” yang pandai. Keberbedaan (primordial) akan lebih rawan jika ia ditekan-tekan, disembunyikan, atau secara naif dianggap minimal – bahkan dianggap tak ada – peran dan fungsinya dalam masyarakat. Itulah problem identitas yang menggayut di udara, dan sewaktu-waktu bisa meledak, baik di tingkat individu maupun di tingkat sosial.
Menerima keberbedaan
Bukannya saya menyarankan primordialisme. Tapi manusia (individu, komunitas) selalu membutuhkan identifikasi dalam modes of being-nya. Kenyataan primordial adalah subyek identifikasi yang asasi, dan merupakan modal untuk membangun identitas. Identifikasi adalah sebuah titik berangkat bagi seseorang atau suatu masyarakat/komunitas dalam perjalanan untuk menemukan “Siapa dirinya?”
Dalam identifikasi tersebut, keberbedaan (difference) menjadi bagian yang penting. Pembedaan adalah cara yang paling mula untuk menegaskan garis dan warna identitas. Barulah setelah kontras garis dan warna itu ditemukan, harmonisasi antara berbagai difference, berbagai garis dan warna itu, bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bagaimanakah harmonisasi warna ada jika yang tersedia hanyalah satu warna belaka? Nasionalisme gestalt menuntut kita untuk meloncati aneka garis dan warna, lantas hidup dalam seragam.
Cara kita menangani difference akan menunjukkan kesiapan kita untuk hidup sebagai sebuah bangsa. Sudah saatnya kita mengevaluasi kembali hidup berkebangsaan kita. Jika “bangsa” diikat oleh kesatuan-kesatuan khusus (misalnya, kesatuan geo-politis dan bahasa), sejauh mana kesatuan/penyatuan itu dapat bekerja; dan bagaimana kesatuan/penyatuan itu dilakukan? Apakah dengan menekan difference sekeras mungkin? Atau justru dengan mengapresiasinya? Lalu jika “bangsa” diikat oleh tujuan bersama, apakah “tujuan bersama” itu? Masih relevankah pengertian kita akan hal itu? Dan, lagi-lagi, bagaimana tujuan tersebut kita capai?
Pendidikan dasar kita adalah karikatur tentang betapa kaburnya materi kebangsaan kita bagi kebanyakan orang, dan betapa kekaburan itu menggagalkan hadirnya manusia-manusia dengan jati diri yang kuat. Kekaburan itu hanya menghasilkan sosok-sosok yang identitas mereka sebatas nomor KTP, sosok-sosok massa yang begitu rentan terhadap berbagai perubahan.
Lembaga pendidikan resmi kita mengajari anak-anak bangsa dengan seragam. Di sekolah umum mereka dilucuti dari kenyataan-kenyataan primordial mereka. Mereka diseragamkan: pakaian, cara berpikir, bahkan target-target (jangka pendek) pendidikan mereka – mereka ditempatkan dalam situasi di mana kepandaian matematika, misalnya, akan membuat seseorang dianggap lebih baik (mekanisme “juara kelas”), sedangkan kepandaian bermain suling tak berarti apa-apa. Kenyataannya adalah: tidak semua orang bisa menjadi “juara kelas”. Tapi karena itu satu-satunya nilai utama, maka berarti, secara realistis, lembaga pendidikan kita telah menghasilkan sekumpulan besar (mayoritas) anak-anak yang bukan juara kelas, anak-anak yang kalah.
Dalam situasi serba seragam, serba terpusat itu maka nasionalisme berhenti sebatas hafalan dan basa-basi. Ia tak lagi menyentuh masalah-masalah kongkrit manusia pelakunya. Dan ketika wacana-wacana lokal menggeliat ingin bangkit, nasionalisme menjadi serba canggung.
Saya kira sudah saatnya nasionalisme kita menerima difference apa adanya. Perlu ada pergeseran tekanan dari “Tunggal” menjadi “Bhineka”. Biar kita bersepakat untuk sama dalam hal-hal yang mendasar saja (misalnya, dalam hal geo-politis di pelataran internasional; atau kesamaan lingua franca bahasa Indonesia). Aneka warna kultur, ekspresi, dibiarkan beragam. Masalah nasionalisme kontemporer bukanlah bagaimana menghilangkan difference, tapi bagaimana mengatasi inequalities (ketaksetaraan/ketakmerataan) dan injustice.
Tentu saja, untuk masalah itu ada banyak sekali yang mesti kita lakukan.
Renungan
Masalah kerusuhan massa bukan cuma terletak pada sisi “kerusuhan” saja, tapi juga pada sisi “massa”-nya. Dan saya percaya bahwa “massa” seharusnya diperhadapkan dengan “identitas”: sosok individu – dengan jati diri yang kuat – adalah benteng kuat untuk menghadapi “massa”.
Di sisi lain: “Identitas tak pernah merupakan sebuah pusat yang tetap,” kata Avtar Brah (dalam Donald & Rattansi, 1992). Ia selalu berproses. Demikian juga dengan nasionalisme, jika ia ingin menjadi bagian dari identitas manusia-manusia pelakunya.
Nasionalisme Seolah-olah
#arsip Pertama kali saya menulis untuk rubrik Opini media massa, dan dimuat, adalah pada 1993-1994. Saat itu, saya banyak menulis esai dan opini masalah kebudayaan, dengan fokus pada wacana kritis tentang Negara-Bangsa, Identitas, dan juga Islam dari sudut pandang kebudayaan. Yang ini, tulisan 1995, dimuat di rubrik Opini Republika. Tanggal, lupa. Jadi sedih mikir Republika saat ini. Juga: wah, ini tulisan waktu saya usia 25, ya. Sekitar 20 tahun lalu. Banyak yang telah berkembang, tentu.
Tahun ini (1995), Indonesia semarak dengan peringatan 50 tahun kemerdekaannya. Menurut saya, lebih tepat jika dikatakan bahwa 50 tahun itu adalah usia “Indonesia” memiliki jasad wadag (yaitu, negara-bangsa Republik Indonesia). Sedangkan “Indonesia” sebagai sebuah konsep, telah lahir ketika terjadi konsensus kesatuan nasional pada Sumpah Pemuda 1928. Sementara pada tanggal 20 Mei 1908, yang biasa kita rujuk sebagai hari Kebangkitan Nasional, “Indonesia” belumlah lahir. Yang ada pada masa itu adalah kesadaran sekelompok (kecil) orang, di bumi Nusantara, bahwa kaum pribumi terjajah perlu memiliki sebuah identitas yang berbeda dari sosok identitas yang telah diterakan oleh kaum kolonial. Tapi justru di situlah semua ini bermula: pada kebutuhan akan identitas (kolektif maupun individual), yang merentang menjadi kebutuhan akan bangsa dan negara.
Maka nasionalisme memanglah masalah identitas sejak semula. Dan saat ini, masalah identitas terasa semakin sulit.
Identitas kebangsaan seringkali kita lekatkan pada dua hal: pada keberadaan negara-bangsa; dan pada budaya bangsa. Dalam kenyataan, pelekatan itu sesungguhnya ilusif, lebih merupakan pretensi yang diterapkan secara tendensius. Kedua konsep kunci tersebut tidaklah innocent, pemaknaan dan penggunaannya perlu dipersoalkan kembali.
Negara-bangsa
Ungkapan “saya orang Indonesia” umumnya, pertama-tama, berarti “saya warga negara Republik Indonesia”. Artinya, sebuah pelekatan identitas/identifikasi seseorang dengan sebuah negara-bangsa (nation state).
Tapi konsep negara-bangsa sedang menghadapi gugatan dari dua jurusan: dari jurusan konseptual dan jurusan kenyataan global kontemporer. Negara-bangsa adalah sebuah konsep pola organisasi politik modern. Negara-bangsa adalah sesuatu yang historis — ia hadir untuk menstrukturkan eksistensi orde internasional, yang dasar-dasarnya diletakkan sejak abad XVI di Eropa (Dorodjatun Kuntjoro-jakti, 1991). Orde internasional itu sendiri bermula dari sebuah asumsi teori ekonomi klasik mengenai kebutuhan akan adanya pembagian tugas ekonomi di dunia, agar terjadi pertukaran ekonomi antar negara (Arief Budiman, 1995).
Perkembangan ilmu-ilmu sosial kini berusaha semakin memahami nature negara-bangsa. Dalam usaha pemahaman tersebut, semakin tampak bahwa “bangsa” adalah sebuah simbol, ide, yang difungsikan untuk sebuah kebutuhan pragmatis: memberikan batasan, lokasi, bagi sebuah organisasi politik bernama negara. “Negara” sendiri, dalam kenyataan, tumbuh menjadi sebuah kekuatan yang otonom, umumnya bercirikan birokrasi dan penguasaan kekuatan pemaksa (militer).
Negara amat berkepentingan untuk melestarikan eksistensinya. Satu hal lagi, negara juga amat berkepentingan dengan penguatan kapital. Secara historis, ini logis. Bukankah asumsi awal kehadiran negara adalah kebutuhan akan adanya orde internasional untuk memudahkan pengembangan ekonomi? Dalam praktek, khususnya di dunia ketiga, tampak pula bahwa negara sering menjadi partner kekuatan-kekuatan kapital internasional (seperti, berbagai korporasi multinasional dan negara-negara maju yang mendesakkan kepentingan-kepentingan industrialnya ke negara-negara kurang maju/berkembang dan terbelakang).
Maka negara tampil membedakan diri dengan masyarakat sipil (civil society). Kepentingan negara berhadapan dengan kepentingan masyarakat sipil. Jika kita paralelkan masyarakat sipil dengan sosok bangsa (personifikasi bangsa sebagai masyarakat), negara tampak berposisi dominan mengatasi bangsa.
Di sisi lain, ada perubahan mendasar yang sedang bergerak di dunia. Pola ekonomi internasional sedang berubah menjadi pola ekonomi global. Demikian juga pola-pola politik-sosial-budaya turut bergerak secara serius. Akibatnya, tumbuh saling ketergantungan di dunia. Ada yang menyebut fenomena ini dengan gejala desa buana (global village). Dunia seolah mengerut karena jarak-jarak terlampaui. Kenichi Omahe, kita tahu, malah menyebutkan bahwa tapal-tapal batas negara telah terlampaui.
Di titik inilah konsep negara-bangsa mengalami tantangan hebat. Globalisasi banyak membawa hal ‘aneh’: di satu sisi, penguatan sentimen dan fanatisme etnis, kebangkitan wacana lokal, post colonial (geliat penolakan/perlawanan terhadap wacana dominan) dan plural; di sisi lain, penguatan perasaan global dalam keseharian kita (misalnya lewat suguhan MTV, CNN, atau persoalan ekologi dan hak asasi manusia) telah menggamangkan wacana kebangsaan — tepatnya, telah menggamangkan identifikasi nasionalitas kita pada negara-bangsa..
Ironis. Kesadaran, kebutuhan, akan nasionalitas dalam upaya mengkonstruksikan sebuah identitas, menjadi mula perjalanan kelahiran sebuah negara-bangsa. Tapi dalam perkembangannya kemudian, pelekatan identitas pada negara-bangsa menjadi problematis dan ilusif.
Budaya bangsa
Masalah identitas budaya bangsa adalah persoalan yang lebih populer dari persoalan negara-bangsa. Untuk Indonesia, persoalan ini agaknya masih dihantui debat klasik polemik kebudayaan. Perbincangan tentang kebudayaan nasional (khususnya di kalangan birokrat dan para intelektual mapan) masih banyak berputar pada debat Ki Hadjar-Takdir: ke manakah kita arahkan orientasi kebudayaan nasional kita — ke Barat, atau ke Timur; modern, atau tradisional? Umumnya orang percaya bahwa jawaban terbaik adalah gabungan unsur terbaik keduanya; bahwa Barat-Timur bukanlah soal benar; bahwa modernisasi bukanlah westernisasi.
Tapi yang sering dilupakan orang adalah bahwa “kebudayaan nasional” dipandang secara taken for granted sebagai sebuah entitas yang utuh dan total. Dalam kenyataan, adakah entitas semacam itu? Bisakah kita menunjuk dengan pasti dan tegas, apakah “kebudayaan nasional Indonesia”? Tentu saja kita juga akrab dengan jargon Bhinneka Tunggal Ika. Kita sepakat, ini juga secara taken for granted, bahwa keragaman adalah kekayaan kita. Toh dalam konteks “budaya nasional”, kita cuma ingin mengambil “puncak-puncak kebudayaan daerah”. Puncak-puncak. Ada asosiasi “pusat” dalam konsep ini — mungkin karena pengaruh wacana negara yang hegemonik.
Homi Bhabha, seorang pemuka wacana pascakolonial, melontarkan pembedaan menarik antara cultural diversity (keragaman budaya) dan cultural difference (keberbedaan budaya). Keragaman budaya adalah konsep yang dibangun dari asumsi tradisi liberal, khususnya relativisme filosofis dan asumsi-asumsi antropologis, bahwa kebudayaan adalah beragam dan keragaman adalah baik serta mesti dipentingkan.
Dalam praktik, menurut Bhabha, konsep keragaman budaya mengandung dua masalah: pertama, ia diterapkan sambil membangun sebuah aturan main yang ditetapkan oleh masyarakat ‘tuan rumah’ atau budaya dominan; aturan main yang kurang lebih berbunyi, ‘budaya-budaya lain ini memang baik, tapi mesti bisa ditempatkan dalam jaring budaya kita.’ Artinya, (konsep) keragaman budaya diciptakan, sementara keberbedaan budaya dikurung. Masalah kedua, pada banyak masyarakat yang menganjurkan multikulturalisme, rasisme masih hadir dalam berbagai bentuk. Hal ini karena, menurut Bhabha, konsep keragaman budaya menopengi norma-norma, nilai-nilai dan berbagai kepentingan etnosentris.
Bhabha tentu saja melontarkan pandangannya dalam konteks Inggris, tempat ia tinggal kini. Di Inggris, masyarakat dan budaya Anglikan — ‘Inggris putih’ — adalah tuan rumah, dominan dan menekan. Kaum migran (seperti Bhabha, Salman Rushdie dan Hamid Algar), kaum hitam dan kaum perempuan sedang menggeliat melawan tekanan budaya dominan, budaya pusat tersebut. Dalam rangka geliat perlawanan itulah, perlu ada kesadaran akan keberbedaan budaya; kesadaran bahwa dalam kenyataan sosial, budaya-budaya yang berbeda berada dalam kondisi tak-saling-imbang, sehingga perlu ada semangat keberpilihan dan ke-lain-an (otherness).
Bukan berarti Indonesia aman dari masalah yang diungkapkan Bhabha. Beda memang dengan Inggris, Indonesia tak memiliki budaya nasional yang sudah ‘jadi’. Tak ada sebuah budaya nasional yang secara tegas menjadi tuan rumah di negeri ini. Di sisi lain, kemajemukan adalah sesuatu yang akrab dengan kita — lebih dari Inggris dengan problem multikulturalnya yang baru menguat belakangan ini saja.
Toh jawaban kita terhadap problem kemajemukan begitu tipikal. Kita menyandarkan diri pada ide keragaman budaya: bahwa kemajemukan (budaya) tersebut dibiarkan, diakomodir, sepanjang berada dalam sebuah common ground bernama budaya nasional. Padahal kita tahu, “budaya nasional” masih merupakan bayang-bayang yang belum terpegang (bahasa halus-positifnya: masih cita-cita).
Maka demikianlah, budaya nasional adalah sebuah pretensi.
Ironi, potensi
Seorang pengamat yang membandingkan problem kultural di Amerika dan Indonesia, William H. Frederick, pernah mengungkapkan hal menarik: ide nation atau “kepribadian nasional” menurut sifatnya adalah samar-samar, idealistis dan romantis; pada saat orang terlalu keras mencoba mendefinisikannya, ia menghilang. (Prisma, 1982).
Upaya terlalu keras mendefinisikan nation bisa jadi dilakukan dua pihak yang berbeda (bahkan berlawanan) sisi: mereka yang ketat dan rigid bersikap konservatif-konvensional dalam memandang masalah kebangsaan; dan mereka yang terlalu ingin kritis, sehingga terjebak menjadi ‘oposan kronis’ (yang penting beda dan protes!) dalam berkebangsaan.
Yang imbang mungkin mendengar kembali suara menyejukkan Soedjatmoko, misalnya, yang berkata bahwa nasionalisme adalah learning process. (Soedjatmoko, 1988) Nasionalisme kebanyakan kita kini mungkin saja masih nasionalisme seolah-olah, yaitu nasionalisme yang masih terlalu menyandarkan diri pada pretensi dan ilusi. Tapi nasionalisme adalah juga sebuah niat. Dan agama mengajarkan bahwa niat mesti selalu diperbarui –supaya tetap segar dan konsisten.
#NotaCinta 01
Agaknya, salah satu hasrat terbesar dalam mencintai adalah hasrat ingin dikenali.
Ya, kita semua cenderung melekatkan perasaan mencintai dengan kehendak memiliki. Itu wajar, alamiah. Tapi, saya berpikir tentang sebuah cerita tentang Tuhan. Sebuah upaya menjawab misteri, tepatnya. Kenapa Tuhan mencipta semesta alam dan, terutama, kita, manusia? Seseorang menjawab: karena Tuhan ingin dikenali.
Dalam mitologi keagamaan yang lazim, Tuhan adalah Sang Maha. Ia bisa hidup sendiri saja. Tapi, kesendirian yang lebih besar dari alam semesta itu akhirnya memunculkan sesuatu –yang dalam keterbatasan akal saya, adalah semacam kehendak, hasrat. Ia mencipta manusia, kita, agar ada yang dapat mengenali-Nya –Sang Maha Sendiri.
Mungkin, itu lebih menggambarkan kita, manusia, yang selalu terlahir sendiri, hidup dalam risiko bersendiri setiap saat, lalu mati sendiri. Kita tumbuh, menjadi sebuah Diri yang unik. Kita menjadi individu, pribadi, seseorang yang bukan yang lain. Tapi, orang lain itu ada. Kita mencoba berjumpa, menyapa, mencoba mencari tempat di antara orang-orang lain.
Kita pun membelah diri. Ada Diri yang ditampilkan untuk orang lain, muncul di permukaan, “panggung depan”. Ada Diri yang diam-diam surut ke belakang, ke ruang privat, bersendiri, menjadi inti Diri. Tapi, siapa yang mengenalinya?
Diri yang di dalam itu, mungkin selalu berdiang dalam hangatnya ruang dalam jiwa, tak ingin dilihat oleh sembarang orang. Harus seseorang yang sangat khusus, seseorang yang istimewa, yang bisa melihatnya. Mengenalinya. Mengenali bahwa ia tak selamanya seperti Diri yang manggung di permukaan. Mengenali, dan menerimanya. Mengenali bahwa Diri yang di dalam itu punya banyak titik rapuh, dan orang lain yang istimewa itu menatap seolah berkata, tak apa, tak ada yang salah denganmu, kau sungguh tak apa.
Ataukah begini: karena sang orang lain itu mampu berkata, kau sungguh tak apa itulah, maka si orang lain menjadi seseorang yang khusus, yang istimewa? Karena ia mengenalimu, ia menjadi seseorang yang kaucintai –begitukah?
Seseorang yang mau menemanimu duduk berdiang dalam ruang dalam jiwa…. ***
Soundtrack:
Himbauan Jiwa – Pahama
Unusual Way – Griffith Frank
MENCARI CERITA, MENCARI BANGSA, MENCARI CINTA (2)
(Bagian kedua repost orasi budaya saya pada 2001 di panggung EKI (Eksotika Karmawibhangga Indonesia), sebagai hadiah kecil untuk teman-teman PLOTPOINT yang sedang mencanang motto: “Kita Bercerita, Apa Ceritamu?”.)
2
Saudara-saudara,
Ranggawarsita III, pada pertengahan abad ke-19, menyusun sebuah kitab yang terhitung sebagai salah satu buku terpanjang di dunia hingga saat ini. Kitab itu adalah Pustaka Raja Purwa (Kitab Raja-raja Kuna), terdiri dari sekitar enam juta kata, ditulis oleh Ranggawarsita III yang sedang prihatin melihat identitas “pribumi” di sekelilingnya sedang tergerus oleh pengaruh kolonialisme Belanda. Ia menulis proyek raksasa Pustaka Raja Purwa dengan niatan untuk menciptakan kembali bagi zamannya sebuah “sejarah nasional”. Ia menciptakannya dalam bentuk prosa – sebuah pembaharuan, karena kitab-kitab sejarah Jawa sebelumnya selalu dituliskan dalam bentuk puisi. Ia menyusun kitabnya berdasarkan empat sumber utama: pertama, dari sejumlah besar folklor, drama rakyat serta tradisi oral di Jawa dan Sumatera pada waktu itu; kedua, informasi yang kemungkinan didapat oleh Ranggawarsita dari para intelektual Barat, kemungkinan dari Belanda, yang ia kenal; ketiga, dugaan-dugaan dan imajinasi Ranggawarsita sendiri – yang lebih merupakan educated guess; dan keempat, dari sejumlah besar manuskrip Jawa kuno di daun-daun lontar yang ia atau kontak-kontaknya temukan, atau telah diwariskan turun-temurun pada keluarga Ranggawarsita selama beberapa abad.
Ranggawarsita III melawan kolonialisme dalam keadaannya yang sedang tak terlawankan. Ranggawarsita III melawan dengan karya, dan mungkin karena itu jarang yang menempatkannya sebagai seorang pahlawan. Padahal kemungkinan besar ia mewarisi kepahlawanan ayahnya, Ranggawarsita II, juga seorang pujangga istana, yang mengakhiri hidupnya sebagai “orang hilang”, diculik dan kemungkinan dibunuh oleh aparat keamanan Belanda. Ranggawarsita III harus hidup dan mengabdi pada raja yang kooperatif terhadap kolonial Belanda. Ia “hanya” bisa melakukan sebuah perlawanan kultural. Dan ia melakukannya dengan optimal.
Dengan menuliskan Pustaka Raja Purwa, Ranggawarsita III sesungguhnya melakukan dua hal: pertama, ia memberdayakan cerita sebagai elemen pembangun identitas nasional. Ia menciptakan sebuah laut cerita, yang darinya setiap orang Jawa dapat menjala cerita-cerita warna-warni untuk dibawa pulang, diwariskan secara lisan maupun tulisan, untuk jadi cermin pematut diri, cermin yang memandu seorang Jawa untuk menjadi seorang Jawa yang “benar”. Yang kedua, dengan menulis salah satu kitab terpanjang di dunia itu secara prosaik, Ranggawarsita III melakukan kontemporerisasi cerita-cerita lama yang beredar di masyarakat, melakukan tafsir baru, dan karenanya memberikan kesegaran baru bagi cerita-cerita itu, sehingga kembali menjadi inspiratif dan menggugah.
Saudara-saudara,
para juru cerita di jaman kita jarang sekali yang memiliki ambisi sebesar Ranggawarsita III. Baik ambisi dalam visi bercerita – seperti Ranggawarsita III yang ingin “mencipta-ulang sejarah bangsanya”. Maupun ambisi dalam berkarya – seperti Ranggawarsita III yang mengolah sumber cerita yang massif menjadi sebuah kitab yang juga massif dengan enam juta kata di dalamnya.
Kita adalah generasi yang lahir di seberang jembatan emas kemerdekaan. Kita lahir, hidup dan bercinta di wilayah yang dulu hanya bisa diimpi-impikan. Kita belajar, mencari uang, berkelahi dan saling bunuh di wilayah yang dulu dijanji-janjikan. Jaman telah menciptakan banyak sekali alat bercerita yang baru. Buku telah menjadi hal yang biasa, walau entah kenapa tak juga jadi kebutuhan sehari-hari. Novel modern, film, komik, animasi, sinetron, bahkan iklan dan klip video musik telah menjadi alat-alat tutur cerita yang baru. Tapi kenapa masih sulit bagi kita untuk menemukan cerita tentang Indonesia? Kenapakah begitu banyak alat cerita yang baru, tapi yang melimpah adalah cerita-cerita tentang Indonesia yang terasa dibuat-buat dan tak meyakinkan?
Saat ini terus terang saya lebih mudah mencintai Amerika ketimbang Indonesia. Ini bukan masalah “rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput kita sendiri”. Ini hanyalah konsekuensi logis dari begitu sehari-harinya eksposur saya terhadap cerita-cerita Amerika. Lewat film, musik, novel, komik, majalah, koran, internet. Saya lebih akrab dengan seluk beluk kota New York, walau tak pernah ke sana, daripada seluk beluk kampung Jakarta tempat saya tinggal. Saya lebih mengerti duka perang Vietnam ketimbang duka perang revolusi Indonesia tahun 1945-49. Saya lebih mampu membayangkan situasi sehari-hari para pionir Amerika di abad ke-19 hingga awal abad ke-20, lewat film seri Little House on The Praire, The Waltons atau film Legend of The Falls, ketimbang membayangkan masa kecil kakek saya di jaman yang sama dengan gambaran film-film itu. Saya lebih mudah mendapatkan dan membaca teks-teks klasik Amerika dari abad-abad yang telah lewat seperti Civil Disobidience dari Henry David Thoreau, Paradise Lost dari Milton, atau puisi-puisi Ralph Waldo Emerson dan Emmily Dickinson, ketimbang karya-karya Ranggawarsita atau Hamzah Fansuri. Ini bukan keluhan atau penyesalan, tapi semata-mata kenyataan.
Kadang memang saya merasa bersalah. Saya jarang pergi keluar Jakarta, tapi biasanya ketika saya pergi keluar Jakarta akan berbekas dalam. Saya hanya pernah ke Bandung, ke Lampung, ke kota Kuningan, ke Yogyakarta, ke Garut, ke Malingping menginap di sebuah hotel tua peninggalan Belanda dan mengunjungi desa nelayan yang miskin dan kering, dengan rumah-rumah mereka yang berjendela tapi tanpa kaca. Di tengah hamparan sawah menguning dan langit lazuardi, di tengah terpaan angin laut dan panas pasir putih, saya sering tercenung: kenapakah cerita-cerita dari benua jauh di seberang samudera sana terasa lebih nyata ketimbang kenyataan alam negeri sendiri?
Kita ini adalah warga dari sebuah negara yang miskin juru cerita. Tukang cerita barangkali banyak, tapi juru cerita, apalagi yang punya ambisi seperti Ranggawarsita III, sungguh sedikit. Dan cerita jelas banyak, tapi tanpa juru cerita yang mempu mengontemporerisasi cerita-cerita itu, bangsa ini tetap akan kehilangan khasanah ceritanya. Maka herankah kita jika semakin lama, kata bangsa di negeri ini semakin hampa?
Sebab, saudara-saudara, ada hubungan yang erat antara bangsa dan cerita. Bahkan sampai pengertian tertentu, bangsa adalah cerita. Bukankah bangsa, menurut Ben Anderson adalah “imagined community”, komunitas atau ikatan kebersamaan yang dibayangkan, yang diimajinasikan? Seperti kata Ignas Kleden suatu ketika, bangsa sesungguhnya adalah fiksi, yang demi fiksi itu banyak orang rela kehilangan harta bahkan nyawa. Hal ini sekarang sudah nyaris jadi truism, kebenaran klasik yang hampir menjadi klise.
Apa artinya “bangsa adalah cerita, adalah fiksi”? Apakah itu artinya bangsa adalah sebuah kebohongan? Tidak. Pernyataan bahwa bangsa adalah cerita hanyalah menyatakan kapasitas non-faktual dari bangsa. Di dalam cerita, terdapat kebenaran yang mengatasi kebenaran faktual atau kebenaran sehari-hari. Sejenis kebenaran yang jika ditiadakan akan membuat berbagai kebenaran faktual dan kebenaran sehari-hari menjadi kehilangan arti.
Saudara-saudara,
Ben Okri, seorang sastrawan Afrika yang menulis dalam bahasa Inggris, pernah menyatakan, “untuk meracuni suatu bangsa, racunilah cerita-cerita mereka.”
Kita saat ini hidup dalam udara yang penuh cerita beracun. Rumor, fanatisme, fitnah, kekaburan makna adalah racun bagi cerita. Kita sesungguhnya telah menghirup racun itu sejak lama. Sensor, kebohongan, tekanan penguasa, ambiguitas makna yang disengaja untuk menutup-nutupi kebenaran, adalah racun yang dipraktekkan sehari-hari rezim Orba. Dan ternyata, saat ini pun kita belum bebas dari racun-racun itu. Praktek-praktek buruk zaman Orba masih terus dilakukan. Jangan salah. “Orba” bukan hanya mereka yang berkuasa di zaman Orba dan kini bersembunyi dalam gelap mengatur ini dan itu, mengorkestrasi kekacauan dari balik gelap, seperti yang digambarkan oleh kelompok tertentu saat ini. Tapi Orba adalah cara berpikir, sebuah jaringan modus produksi yang telah menghasilkan makhluk-makhluk yang disebut Jalaluddin Rahmat sebagai “Homo Orbaicus”. Gus Dur, misalnya, di masa Orba adalah seorang yang selalu ditekan dan menjadi salah satu lawan politik terkuat Soeharto. Tapi justru karena itu kita lihat seluruh mekanisme survival politiknya sudah terbentuk oleh Orba, sehingga ketika meja berbalik, dan ia menduduki kursi kekuasaan, ia melakukan praktek yang sama saja dengan Orba.
Saudara-saudara,
saat ini kita berdiri di seberang jembatan emas kemerdekaan. Dan kita tak mampu berkata dengan bangga seperti George Bush Jr. berkata dalam pidato inauguralnya:
We have a place, all of us, in a long story. A story we continue, but whose end we will not see. It is the story of a new world that became a friend and liberator of the old, a story of a slave-holding society that became a servant of freedom, …
(Kita punya tempat, semua kita, dalam sebuah cerita panjang. Sebuah cerita yang kita lanjutkan, tapi akhirnya tak akan kita lihat. Sebuah cerita tentang suatu dunia baru yang menjadi sahabat dan pembebas dunia lama, sebuah cerita tentang suatu masyarakat yang mendukung perbudakan dan kemudian berubah menjadi hamba kebebasan….)
Bush dengan penuh percaya diri menutup kalimatnya, “It is the American story”, Itulah cerita Amerika. Cerita yang dengan segala variasi rumit selalu diceritakan lagi oleh VOA dan CNN ke seluruh penjuru dunia; oleh Tom Wolfe, Don DeLilo, Norman Mailer, atau Gore Vidal lewat novel-novel akbar mereka; oleh Bob Dylan, lewat kritisisme lagu-lagu baladanya yang lahir dari perut idealisme demokrasi ala Amerika; oleh Daniel J. Boorstin, lewat buku-buku sejarah populernya yang ketebalan mereka (rata-rata di atas 600 halaman) sungguh mengherankan kita, kok bisa masuk daftar best sellers ?; oleh Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Woody Allen, Martin Scorcesse, Spike Lee, hingga deretan sutradara muda populer seperti Michael Bay yang sukses besar menjual patriotisme Amerika gaya baru seperti lewat Con Air, Armageddon, dan Pearl Harbor; dan oleh sederet nama lagi, nama-nama Amerika, yang mungkin lebih dikenal generasi kita ketimbang Ranggawarsita III atau Hamzah Fansuri atau Nurrudin Ar-Raniry. Cerita yang selalu diceritakan kembali dalam berbagai variasi, dan selalu ada yang mendengarnya. Cerita Amerika. Cerita “mereka”, yang melalui media massa seringkali menjadi cerita kita.
Kita sendiri, bangsa Indonesia yang telah berdiri di seberang jembatan emas itu, apakah cerita kita? Sebuah cerita kesalahan demi kesalahan, kebodohan demi kebodohan, kejahiliyahan demi kejahiliyahan, itukah cerita kita? Sebuah cerita tentang angka pengungsian tertinggi di dunia, tentang orang-orang yang harus mengungsi di negeri sendiri? Sebuah cerita tentang horor yang jauh lebih seram dari semua film Wes Craven yang paling seram? Seperti cerita tentang kepala yang direbus, yang disaksikan teman saya; atau cerita seorang anak perempuan, yang bersama ratusan orang di desanya, dibantai di sebuah lapangan bola tempatnya bermain sehari-hari, di suatu malam jahanam di Kalimantan, seperti yang diberitakan oleh sebuah edisi majalah Times? Apakah nantinya cerita Indonesia adalah cerita-cerita hantu, arwah penasaran dari orang-orang yang mati dalam ketakadilan dan kebengisan yang tak terbayangkan?
Lebih dari itu, siapakah yang akan menceritakan cerita kita? Para ekonom? Bisa. Tapi haruskah cerita mereka jadi satu-satunya cerita, menyingkirkan cerita-cerita lain? Kemanakah kita mencari cerita Indonesia? Pada para politisi? Saya tidak anti para politisi. Kita memerlukan para politisi yang profesional, agar mekanisme demokrasi ini berjalan dan kita tahu bagaimana kita memperjuangkan kepentingan-kepentingan kita. Tapi bukankah udara di dunia politik sekarang penuh racun yang akan merusak cerita tentang Indonesia? Lalu kemana lagikah kita harus mencari cerita Indonesia, cerita bangsa kita? Kepada para cendikiawan? Para wartawan? Mungkin. Tapi kebanyakan cendikiawan dan wartawan yang saya temui sedang mabuk peran sebagai pahlawan reformasi. Cerita-cerita kebanyakan mereka tentang Indonesia hanyalah ceracau dan kecerewetan yang memekakkan telinga. Kemana kita harus mencari cerita tentang Indonesia, cerita tentang diri kita sendiri? Atau, apakah orang Indonesia jika ingin mencari cerita, yang ia dapati hanya derita?
Kita sedang dalam keadaan genting. Kita telah berjalan jauh dari jembatan emas itu, dan kita sedang tersesat di sebuah jalan buntu. Kita terjebak dalam sebuah dunia labirin yang dipenuhi oleh cermin-cermin tipu daya, dan kita kehilangan cermin yang dapat menampilkan diri kita apa adanya. Kita harus mencari cermin sejati itu, cerita sejati tentang Indonesia.
Keadaan sedang genting. Kebuntuan ini sungguh keterlaluan. Maka kita semua harus bekerja. Maka penulis harus menulis. Pelukis harus melukis. Komposer harus mencipta komposisi. Pencipta lagu harus mencipta lagu. Penari harus menari. Komikus harus membuat komik. Kartunis harus membuat kartun. Novelis harus melahirkan novel, melahirkan semesta baru, barangkali saja dengan demikian Indonesia bisa kita bayangkan kembali. Penyair harus mengorek kata hingga bertemu Indonesia, jauh di jantung bahasa.
Seperti kata Tardjie, dalam puisi Cari :
dari balik puing-puing ini
dari balik gosong nyeri
dari balik abu dan tulang-tulang ini
cepat temukan kata!
sebelum cuaca semakin memburuk
sebelum datang lagi El Nino
sebelum datang pula La Nina
agar tak kembali muncul El Dictador
Para juru cerita, bangkitlah, menyeruaklah mengatasi para tukang cerita yang hanya bisa menyampaikan ilusi berbisa. Para juru cerita, bangkitlah, ceritakan cerita di balik kuning padi di sawah yang menghampar luas. Ceritakan cerita di balik warna-warni ikan laut di terumbu karang yang hampir hilang. Ceritakan cerita di balik legam kulit nelayan, ceritakan cerita di balik tembok-tembok kusam kota-kota kecil dan tua. Ceritakan cerita di balik bunyi sendu seruling seorang anak angon kebo pada suatu senja, ceritakan cerita di balik bunyi keleneng sepi sebuah andong di sebuah siang yang sepi. Ceritakan juga cerita tentang semangat apa di balik kemauan anak-anak muda berkalang panas di jalanan, menuntut agar tak ada lagi kebohongan. Ceritakan, ceritakan semuanya.
Ceritakan cerita baru tentang Indonesia.
…BERSAMBUNG
Pi (2): Tuhan?
Saya ingat Maradona dengan kasus “Tangan Tuhan”-nya. Piala Dunia 1986, Argentina melawan Inggris. Gol pertama Maradona dianggap curang, karena sundulannya dibantu tangannya. Wasit tak melihat. Gol sah. Semua protes. Maradona seakan membayar kecurangan itu dengan salah satu gol terindah sepanjang masa di babak kedua: sendirian melewati 10 pemain Inggris, termasuk kiper, Maradona memberi gol telak.
Ditanya apakah ia menggunakan tangannya, jawaban Maradona begitu masyhur: “Itu tangan Tuhan!” Terus terang, gol pertama itu, bagi saya, sebuah gol curang, tapi sebuah kecurangan yang indah.
Seperti juga Yann Martel dengan Life of Pi. Ramai media Amerika dan Brazil menuduh Martel menjiplak novel dari seorang novelis Brazil, yang mengisahkan seorang yang terjebak di sekoci penyelamat bersama jaguar. Pi dalam novel Martel terjebak di sekoci penyelamat dengan seekor harimau Bengali, bertahan selama 227 hari, setelah kapalnya tenggelam di laut Pasifik.
Martel sejak semula, sebelum semua keributan itu terjadi (terpicu oleh kemenangannya di Booker Prize 2002), terbuka mengakui ia memang meminjam ide cerita itu. Betul, pinjam-meminjam soal biasa. Berapa banyak sih yang telah dikisahkan soal kisah jatuh cinta. Tapi jelas bahwa bagaimanapun ide seorang terjebak di sekoci penyelamat bersama seekor jaguar (atau binatang buas sejenis) adalah luarbiasa, sepenuhnya unik.
Martel mungkin curang. Toh ia telah menuliskan novelnya dengan luar biasa. Sebuah kecurangan yang indah. Life of Pi tetaplah sebuah cerita yang, seperti klaim salah seorang tokohnya, “akan membuat Anda percaya pada Tuhan.” Atau, seperti kata Lisa Jardine (ketua juri Booker Prize 2002), “paling tidak membuat kita bertanya-tanya, kenapa kita tak percaya Tuhan?”
Simak saja petikan ini, sebuah gelitik bagi benak atheis atau agnostik:
Aku sungguh dapat membayangkan kata terakhir seorang atheis: “Putih, putih! C-C-cinta! Tuhanku!”—dan sebuah lompatan iman di ranjang kematiannya. Sedang kaum agnostik, jika ia tetap setia pada jiwa penuh nalarnya, jika ia teguh pada faktualitasnya yang kering, tak bergandum, mungkin akan mencoba menjelaskan cahaya hangat yang menyelimutinya dengan berkata, “Mungkin sebuah oksigenasi yang g-g-gagal dari o-o-otak,” dan, hingga akhir hayatnya, kekurangan imajinasi serta kehilangan sebuah cerita yang lebih baik. (Life of Pi, terjemahan pribadi dari edisi Inggris, 2002)
Martel mungkin curang. Tapi bolehlah ia mengaku telah menulis dengan “Tangan Tuhan”.
— Januari, 2003
POJOK POP (1): SETELAH DEBUSSY MENDENGAR GAMELAN JAWA
Sudah jadi pengetahuan umum di kalangan pelajar musik bahwa komposer Eropa Claude Debussy terkesima ketika pertama kali mendengar musik gamelan Jawa di Paris Expo pada 1889, dan pengalaman itu memengaruhi karya-karyanya kemudian.
Seorang pengamat, David Toop, malah menegaskan bahwa baginya, hari ketika Debussy mendengarkan gamelan itu adalah awal dari musik abad ke-20. Toop, dalam Ocean of Sound (1995), mencirikan sifat dasar musik abad ke-20 adalah musik yang berpusat pada komunikasi yang bersicepat dan konfrontasi antarbudaya. Debussy, yang sedang tak puas pada pakem musik Barat semasanya, terpana mendengar sesuatu yang sama sekali lain dalam musik gamelan Jawa di Paris Expo itu.
Salah satu biografi Debussy menyebut bahwa gamelan yang didengar oleh Debussy malam itu mengiringi tari Bedaya. Toop menduga bahwa versi Bedaya yang dilihat Debussy adalah versi selain Bedaya Ketawang dan Semang yang sakral. Tapi, sepengetahuan Toop, semua Bedaya ditarikan secara perlahan-anggun dan bertema ke-air-an. Menurut Toop, tema itu memengaruhi karya-karya Debussy beberapa tahun sesudahnya, yang “likuid” dan bertema “ke-air-an” juga: La Mer, Reflets dans l’eau, Jardins sous la pluie, dan Poissons d’or.
Malam itu, pada kemeriahan Paris Expo 1889, Debussy yang resah terpajan pada liyan, suatu dunia musik selain musik Barat yang mengungkungnya, sebuah “dunia bunyi di luar aturan-aturan dan pakem-pakem ketat” (Toop, 1995). Tentu, sebelum dan sesudah malam itu, Debussy juga terpengaruh oleh warisan musik abad pertengahan dan juga drama Vietnam semasa hidupnya. Tapi, jika melihat betapa terkenal “insiden” Debussy dan gamelan, maka malam itu adalah titik balik musikalitas Debussy –dan, kalau kita percaya Toop, juga titik balik musik Barat.
Di satu segi, sifat komunikasi dan konfrontasi (tabrakan) antarbudaya musik Barat abad ke-20 menjelaskan kelahiran musik-musik seperti jazz dan rock, misalnya, yakni sebuah dialog cum tabrakan kreatif antara musik Barat dan musik blues yang berakar pada warisan musik kaum budak kulit hitam di Amerika. Bayangkan, misalnya, perjalanan dari blues jalanan di Amerika pada masa 1920-1930-an, hingga kemegahan progressive rock pada 1960-1970-an yang banyak diolah musisi Inggris dengan warisan Bethoven mereka. Betapa banyak dialog kebudayaan dalam perjalanan itu!
Gamelan sendiri, pada akhirnya bukan hanya gamelan Jawa. Ada gamelan Bali yang lebih dinamis. Dan kesemua gamelan itu telah banyak memikat para musisi Barat. Sebut saja komposer Collin McPhee, John Cage, Jon Hassel, Yes, hingga sampling band asal London, Loop Guru. Gamelan (Bali) juga yang mendominasi salah satu tonggak musik Indonesia: Guruh Gipsy, grup rock progresif 1970-an pimpinan Guruh Soekarno Putra dan beranggota antara lain Chrisye, Jocky S., Keenan Nasution, Fariz RM. Semua alumni Guruh Gipsy jadi tokoh penting penentu warna dan corak musik Indonesia pada 1980-an, dengan pengaruh yang masih terasa hingga kini.
Di sisi lain, gagasan dasar musikalitas Debussy setelah ia mendengar gamelan Jawa itu adalah “keterbukaan”,”intuitif”, dan “impresionisme”. Gagasan-gagasan ini kembali meruak dalam lanskap musik menjelang akhir millenium ke-2, lewat musik-musik ambient yang dipopularkan Brian Eno dan segerombol “seniman bunyi” beraliran musik yang dilabel macam-macam: environmental, deep listening, ambient techno, electronic, sound art, sound design, brainwave music, New Age, chill out, dsb., dsb.
Lain kali, kalau Anda ke lantai dugem, tenggelam dalam ekstase samudera bunyi yang dipaparkan para DJ, ingat-ingat bahwa Anda ada di sisi lain sebuah dunia bunyi yang sama dengan para penari Bedaya.***
Rekomendasi: Situs: untuk musik-musik ambient, electronic, dan semacamnya, silakan buka moteldemoka.com. Salah satu situs musik terbaik, lengkap dengan esai-esai pendek (seringkali puitis) pengiring daftar lagu, dan ilustrasi foto/lukisan yang oke.
Bangsacara & Ragapadmi, by Jan Mintaraga & Pak Man
With more than 17.500 islands and around 300 ethnicities, Indonesia is very rich with stories. In 1950s trough 1980s, this rich resources of stories was fully used by Indonesian comic writers and artists. This is just a small example.
This comics was a supplement in a 1980s children magazine, Ananda. The magazine routinely give comics, mining well-known Indonesian folklore or traditional stories from Wayang (Indian-influenced Javanese traditional puppet show). Bangsacara and Ragapadmi is a Maduranese love-legend, adapted here by a legendary comic artists Jan Mintaraga.
Jan, as you can see, heavily influenced by Warren Comics artists, in particular, those whose origin were Latin-America. Esteban Maroto was one of the biggest influence for Jan. Hence the westernized figures and faces of this Indonesian characters. He is often criticized because of this, but his fans didn’t mind at all. In fact, this westernized figures played some kind of escapism mechanics in his comics.
But other than the anatomy, Jan is quite rigorous in his research for stories like this. He usually took some historical materials, and interpreted them in the light of modern view.
In this story, Ragapadmi was a lovely wife (one among many, mind you) of King Bidarba of Madura island. But she caught a disgusting skin desease, and was expelled from His Majesty palace to the hand of his loyal (and heavenly good-looking in a Vogue magazine kind of way) servant, Bangsacara.
The-to-be-expected-recovery part of Ragapadmi was treated in a rather modern way: no divine intervention or hocus pocus treatment, just your usual herbal medicine in the forest where the mother of Bangsacara lived.
Jan also very kind to the King -it was not His Majesty fault that the two heavenly creatures met their tragic end (this is a traditional Romeo-Juliet story after all), but rather his too excited officer that came up with the hideous plan. Contemporary reader could not escape in wondering how the all-dominant Soeharto’s regime whose power was at peak in the time of the comic’s publication have something to do with it. At least, playing part in Jan’s choice to downplay the “evil” of the King.
The manner of how Jan ended the story was also rather modern -the bodies of those tragic lovers were found by some traveller and reported to the king, and the king pondering about the possibilities of the identity of those two bodies.
Over all, this 16 pages retelling of Bangsacara and Ragapadmi is too docile, told in a rather dated narratives, but contain a very high quality of visualization. This is Jan at the height of his techniques, doing some work-for-hire job. I imagine that Jan did this short comic with his eyes half-closed. It is but a tip, a very small tip, of a very large iceberg that is the unexplored Indonesian comics history.
Dead Pool Max no. 1, by David Lapham and Kyle Baker
Well, I tell you this: don’t give crazy character to crazy writer AND crazy artist. Or you’ll get a serious f**k-you-story like this one.
David Lapham has an uncanny ability to crawl under the membrane of madness in the minds of serial killers and psychos and makes them lovable altogether. He is also very good in, pardon the high word, narratology. His indy series, Stray Bullets, read as a whole, is a somewhat hardboiled version of exercise in narratives.
In this (blood-fest is an understatement) first episode of newest Max’s Dead Pool, the already sick-maniac antihero of the mainstream Marvel get even crazier.
And the narrative-strategy by Lapham is very effective. Readers who are familiar with Dead Pool’s antics are expecting the usual sick-but-funny inner dialog of personalities inside his head. Lapham chose different path.
He told the story of Dead Pool through the eyes of “Bob”, who is some kind of a secret agent, sentenced to be Dead Pool’s “handler”. We couldn’t “hear” any voices from inside Dead Pool’s head, but instead we are invited to experience the consequences of his craziness.
So we have “Bob” experiencing sadistic homosexuality from “Bruno”, a larger-than-life Mob’s big boss coming straight from Dick Tracy’s gallery of rogues, key in human excrement, heads rolling, mutilation, and more.
Oh, did I mention that this comic is drawn by that crazy Kyle Baker?