CAK NUR MENYARANKAN FILM
[#arsip : ini esai saya untuk urun esai dalam buku ALL YOU NEED IS LOVE, CAK NUR DI MATA ANAK MUDA (disunting oleh Ihsan Ali Fauzi dan Ade Armando, diterbitkan Yayasan Wakaf Paramadina, 2008). Alhamdulillah, ya, mata saya dianggap masih mata anak muda. #salahfokus Oke. Serius dulu. Yang saya arsip di sini, adalah versi panjang tulisan saya. Yang di buku, sudah dipendekkan, demi ruang. Jika Tuan dan Puan sudi membaca, selamat menikmati.]

Foto diambil dari koleksi pribadi Dwii Setiyawan, di https://dwikisetiyawan.wordpress.com/2009/07/16/nurcholish-madjid-memorial-pictures/
Zaman sekarang, sangat biasa orang merekomendasikan sebuah film. Tapi, di mimbar khutbah Jumat? Itulah yang membuat saya terkesan secara pribadi oleh Cak Nur (Nurcholis Madjid). Suatu ketika pada pertengahan 1990-an, saya shalat jumat di toko buku Wali Songo. Toko buku yang khusus menjual buku-buku Islam ini berada di bilangan jalan Kwitang, dekat Pasar Senen, Jakarta. Ada area khusus untuk shalat Jumat di toko buku ini. Dan pada suatu ketika itu, saya sedikit kaget: di atas mimbar Jumat, Cak Nur dengan kalem menyarankan jemaat Jumatan saat itu untuk menonton sebuah film Barat, The Name of the Rose.
Film ini dibuat oleh sutradara Prancis, Jean Jaques Anaud, dengan bintang utama Sean Connery dan Christian Slater. Film ini merupakan adaptasi dari novel mahakarya filsuf semiotika Umberto Eco. Novel ini banyak dipuji oleh para kritikus sastra dunia, walau pada saat filmnya dibuat dan direkomendasikan oleh Cak Nur, novel dan nama Umberto Eco belum terlalu akrab di kalangan pembaca buku Indonesia. The Name of The Rose mengisahkan misteri serangkaian pembunuhan di sebuah biara Katolik Abad Pertengahan. Rangkaian pembunuhan itu terjadi pada saat pelaksanaan konvensi teologi tahunan.
William of Bakersville dan muridnya, Adso,yang sedang bertamu di biara itu mendekati misteri itu tidak dengan takhyul dan mistik, tapi dengan pendekatan yang pada waktu itu sangat kontroversial dan diharamkan oleh arusutama Kristiani: empirisme dan penalaran rasional. Ternyata, pembunuhan itu terkait dengan sebuah buku klasik terlarang, dan pembongkaran misteri pembunuhan itu juga berarti pembongkaran sendi-sendi ortodoksi Katolik Eropa Abad Pertengahan. “Anda harus menonton film ini,” kata Cak Nur dalam khutbahnya, “film ini bagus sekali.”
Sebelum kita bahas ini lebih jauh, saya ingin bercerita dulu soal shalat Jumat di toko buku Wali Songo.
Keistimewaan shalat Jumat di toko buku Wali Songo adalah mereka sering mengundang tokoh cendekiawan Islam terkemuka untuk jadi khatib. Cak Nur hanya salah satu dari sekian banyak tokoh yang cukup rutin menjadi khatib di situ. Saya ingat Jalaluddin Rakhmat dan Imaduddin Abdurrahim pernah jadi khatib di sana, dan saya hadiri. Saya tak tahu pasti yang lain, tapi rasanya Deliar Noer, Yusril Ihza Mahendra, dan AM. Saefudin pun pernah jadi khatib di situ. (Mungkin sekali ingatan saya keliru tentang Deliar dan Yusril, tercampur dengan pengalaman mendengar mereka sebagai khatib Jumat di masjid UI, Depok.)
Dengan pilihan Khatib para cendekiawan itu (biasanya, masjid toko itu sudah punya jadwal hingga beberapa bulan ke depan), shalat Jumat di Wali Songo jadi menarik. Biasanya, shalat Jumat di masjid umumnya jadi pengalaman yang membosankan. Khatib-khatib Jumat di banyak masjid nyaris tak memberi apa-apa pada saya, selain sederet ayat yang disampaikan tanpa sistematika atau kerangka pikiran yang jelas. Yang disampaikan para khatib konvensial itu biasanya truism belaka dalam beragama: jangan menyimpang dari al-Qur’an dan hadis, harap berakhlak mulia, jangan maksiat, bla-bla-bla. Biasanya, khutbah demikian jadi obat tidur yang manjur buat saya.

Foto diambil dari http://www.djangkarubumi.com/2013/03/toko-buku-wali-songo-senen.html
Nah, beberapa kali saya “memburu” shalat Jumat yang berkhatib pemikir macam Cak Nur. Jadi, sebelum “khutbah The Name of The Rose” yang mengesankan saya itu, pastilah saya sudah punya ketertarikan pada Cak Nur. Terus terang, saya tak pernah mengenal Cak Nur secara pribadi, tak pernah bercakap langsung, dan saya hanya mengenalnya lewat buku atau mimbar. Khutbah Jumat dari Cak Nur itu adalah hal terdekat yang saya punya dengan Cak Nur. Kalau dipikir-pikir, saat dan tempat “khutbah The Name of The Rose”`yang mengesankan saya itu mengandung jejaring makna dan alur sejarah pribadi yang berlapis-lapis.
Pertama, tempat shalat itu, toko buku Wali Songo, adalah sebuah tempat yang lahir dari impian pengusaha buku terkenal, Haji Masagung. Dia adalah pemilik jaringan toko buku Gunung Agung, yang bermula dari sebuah toko kecil di Senen dan pada masa 1980-an tumbuh menjadi jaringan toko buku nasional saingan Gramedia, yang juga mengembang ke dunia penerbitan. Masagung adalah seorang mu’alaf. Ia pernah menarik perhatian nasional ketika membiayai pembuatan film Wali Songo pada 1980-an. Film yang antara lain dibintangi oleh Deddy Mizwar itu sempat bikin heboh karena Masagung mengaku pembuatan film itu dibimbing wangsit.
Memang, sosok para wali yang sembilan dalam film itu (ditambah “wali kesepuluh”, Syekh Siti Jenar, yang digambarkan bak dukun sesat, menganut “mistik hitam”) lebih banyak digambarkan mengandung klenik. Dakwah dan perseteruan yang terjadi, juga berbagai pencerahan pribadi para wali itu, digambarkan sebagai penuh kejadian mistis dan ajaib. Para wali itu digambarkan bukan memiliki pencerahan spiritual, tapi memiliki kesaktian.
Kegandrungan Masagung pada Wali Songo yang mistis itu hadir dalam pemberian nama toko buku khusus Islamnya itu. Di dalam toko buku itu sendiri, pilihan buku Islam yang dijajakan merentang dari buku-buku ibadah praktis, terjemah kitab-kitab klasik, pemikiran Islam yang akademis, sastra Islam, hingga mujarobat dan teori konspirasi Yahudi. Semangat sembilan wali yang sinkretik mewujud dalam pilihan buku yang eklektik. Eklektisme serupa itu lah yang agaknya mendasari pilihan para khatib dan penceramah di toko buku itu (setiap Minggu pagi, mungkin untuk menyaingi misa Gereja, ada acara ceramah Islam di toko buku Wali Songo).
Toko buku khusus Islam ini cukup memengaruhi wajah industri buku Islam di Indonesia. Paling tidak, sejak kehadirannya, industri buku Islam menjadi sebuah subindustri buku nasional yang tegas membedakan diri dari jenis-jenis buku “umum”, menciptakan dunia dan logikanya sendiri. Toko buku ini juga hadir pada saat penerbit buku Islam Mizan sedang ada di puncak kemapanannya dari segi perannya dalam membentuk khasanah pemikiran di Indonesia. Pada saat itu, Mizan punya brand yang baik sekali karena (a) terjemahan buku-buku dari cendekiawan Islam kelas dunia, dan (b) seri Cendekiawan Islam-nya, yang memetakan sekaligus mencuatkan khasanah kecendekiaan Islam di Indonesia. Banyak dari nama cendekiawan muslim yang pernah masuk seri itu menjadi khatib di toko buku Wali Songo.
Semua eklektisme dan “keterlibatan” dalam medan pemikiran Islam di tingkat nasional itu sungguh jadi godaan bagi saya, yang waktu itu adalah seorang aktivis harakah. Sebagai aktivis harakah, tentu saja saya “mengenal baik” nama Cak Nur: dia adalah seorang pemikir yang dianggap telah menyesatkan umat dengan ajaran sekularisasinya.
Di tengah suasana ideologisasi yang penuh semangat, dan terus terang memang jadi “rumah” saya waktu itu dalam beragama, saya mengembangkan hubungan khusus dengan pemikiran Cak Nur. Pada waktu saya kuliah, 1989, saya sudah tertarik dengan pemikirannya ketika membaca pengantar buku yang ia sunting, Khasanah Intelektual Islam. Buku itu adalah antologi cuplikan karya para pemikir Islam sejak Al-Kindy hingga zaman modern. Dan pengantar Cak Nur memberi sebuah kesan yang menantang saya yang sangat harakah waktu itu: orang yang dianggap “antek” Barat/Yahudi ini sama sekali bukan orang bodoh! Pikirannya jernih, bahasanya runut dan logis, dan gagasan-gagasanya penting untuk dipikirkan.
Karena posisi sebagai “lawan tanding” itulah, saya beruntung untuk sejak semula membaca tulisan-tulisan Cak Nur dengan kesadaran kritis. Dan memang, Cak Nur adalah sparring partner yang sangat baik untuk pemikiran Islam. Pikiran-pikiran modernisasi Cak Nur, misalnya (termasuk gagasan sekularisasinya), membuat saya juga berpikir keras dan tergugah mencari bacaan-bacaan tandingan dari khasanah ilmu-ilmu sosial yang waktu itu saya geluti. Saya, misalnya, kemudian tertarik pada berbagai kritik terhadap modernism dan sekularisme, terutama dalam gagasan-gagasan Peter Berger. Sampai sekarang, pemikiran Berger masih menjejakkan pengaruhnya pada saya: khususnya, gagasan tentang demodernisasi dan desekularisasi – di samping gagasannya tentang konstruksi sosial atas kenyataan (yang membantu saya untuk selalu kritis terhadap apa yang dianggap kenyataan oleh arusutama dalam masyarakat).
Ketika saya membaca buku yang mengumpulkan surat-menyurat Cak Nur dengan Mohammad Roem tentang (tidak adanya) konsep Negara Islam, saya pun lantas berkutat dengan berbagai teori tentang Negara dan pemerintahan. Hasilnya? Bukannya saya menyalahkan mutlak Cak Nur, saya malah terhanyut oleh teori-teori kritis tentang Negara, dan membawa saya hingga sekarang meyakini kebutuhan untuk merelatifkan Negara. Walau, sempat juga saya menulis sebuah risalah pendek tentang makna Negara Islam yang saya anjurkan, yakni dengan pendekatan kultural sebagai alternatif dari pemaknaan teologis dan politis terhadap makna dan operasi gagasan Negara Islam.
Singkatnya, jarang saya bersetuju dengan Cak Nur, tapi dalam arti yang bagus –sebuah percakapan gagasan yang hangat. Sikap ini membuat saya tak keberatan menerima berbagai percik ilmu dan anjuran moral dari Cak Nur yang menurut saya sangat memikat. Dan agaknya sikap ini juga menyumbang pada perasaan tak puas terhadap gagasan-gagasan dalam harakah sendiri. Apa yang dilakukan oleh sebagian unsur harakah dalam mencerca, bahkan mencaci dan memfitnah Cak Nur membuat saya merasa tak nyaman.
Setidaknya, ada dua peristiwa dalam hubungan antara harakah dan Cak Nur pada awal 1990-an yang membuat saya bertanya-tanya tentang kelayakan harakah menjawab masalah-masalah modern. Peristiwa pertama (ini bukan urutan kronologis), dalam seminar Percakapan Cendekiawan Tentang Islam (PEDATI –saya lupa yang keberapa) di balairung UI. Di situ, ada pembicara bernama Anis Matta, yang waktu itu dipromosikan oleh banyak teman-teman harakah sebagai cendekiawan yang bisa “meng-counter” Cak Nur. Ternyata, dalam seminar itu, yang dilakukan oleh Anis Matta hanyalah membacakan kalimat-kalimat terseleksi dari tulisan-tulisan Cak Nur dan kemudian membenturkan dengan dalil-dalil (terseleksi juga) dari “logika”, hadis, dan al-Qur’an. Sangat tak sepadan dengan jihad (upaya penuh kesungguhan dan total) akademis Cak Nur dalam merumuskan sebuah gagasan.
Peristiwa kedua, lebih menohok hati saya. Pada awal 1990-an itu terbit sebuah buku kecil dari pengarang dengan identitas tak jelas, yang berisi daftar cendekiawan Islam Indonesia yang dianggap sesat. Cak Nur, Gus Dur, dan Kang Jalal masuk sebagai tokoh utama. Mereka dilabel “budak kuffar”. Dengan sembrono, penulis menciptakan sebuah kategori teologis baru, agar bisa memberi pengukuhan teologis dalam menganggap Cak Nur dan pemikir lainnya sebagai sesat.
Penulis itu rupanya berangkat dari kesadaran bahwa tak dapat dibenarkan (atau, mungkin, kurang strategis) untuk mengafirkan orang yang nyata-nyata bersyahadat dan shalat macam Cak Nur. Maka, ia menciptakan kategori itu: ada orang-orang yang mengaku muslim dan mempraktikkan ibadah Islam, bahkan sebetulnya masuk kategori ulama, menjadi antek kaum kafir. Mereka mengembangkan mentalitas budak terhadap para tuan kafir mereka, membawa-bawa pikiran-pikiran dan agenda kafir ke tengah masyarakat muslim untuk menyesatkan “kita” dari jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan “syariah”. Dalam buku itu, yang beredar di kalangan aktivis musholla di kampus-kampus dan SMA-SMA, kebencian terhadap para “budak kuffar” itu malah lebih terasa daripada kebencian terhadap “kaum kuffar”.
Kedua peristiwa itu membuat saya tak betah lagi berkutat dengan kancah pemikiran harakah yang ada. Tentu, bukan hanya karena kedua peristiwa itu saya tak betah lagi pada pemikiran-pemikiran harakah. Ada beberapa praktik harakah yang tak membuat saya nyaman. Tapi dua peristiwa yang terkait Cak Nur itu termasuk yang paling membuka mata saya, mendesak saya untuk mencari horison pemikiran yang lebih luas.
Bukannya saya lantas jadi pengikut setia Cak Nur dan kaum modernis Islam lainnya. Saya berterimakasih dan menerima “warisan” gagasan harakah yang membuat saya kritis terhadap kenyataan sosial dan keterpurukan umat Islam masa kini. Saya juga tak sepenuhnya bisa menerima gagasan-gagasan modernisme Cak Nur. Tapi, paling tidak, saya menyadari bahwa butuh lebih dari sekadar cacian dan impian akan masa silam untuk menghadapi fakta keras dan gagasan kuat modernisme. Dan pada 1990-an itu, saya mulai lebih berkonsentrasi mengembangkan pemikiran-pemikiran saya sendiri, tak lagi terlalu peduli pada arahan-arahan dan batasan-batasan yang diberikan harakah terhadap dunia pemikiran dan kepenulisan yang saya geluti.
Dan setelah keputusan untuk mengabaikan batas-batas pemikiran harakah itulah saya jadi leluasa mengejar minat-minat pribadi saya, khususnya minat di bidang budaya populer. Apalagi pada pertengahan 1990-an mulai terbit dalam bahasa Indonesia, kumpulan tulisan tentang studi kebudayaan (yang lazimnya banyak membahas ranah budaya pop dalam masyarakat modern) seperti yang diterbitkan oleh Penerbit Bentang (buku Hegemoni Budaya). Dan pada masa inilah saya mendalami lebih serius berbagai bacaan seputar film dan sastra.
Keduanya adalah minat masa kecil saya. Saya waktu itu mulai merasakan bahwa lembaga-lembaga modern seringkali memiliki efek samping membuat pengetahuan-pengetahuan tertentu yang jadi unsur pembentuk jatidiri kita menjadi tidak sah. Misalnya, pengetahuan-pengetahuan tentang musik, film, komik, dan berbagai narasi kecil lainnya, termasuk berbagai kearifan lokal yang diwarisi secara turun-temurun. Pengetahuan-pengetahuan itu paling-paling ditempatkan sebagai “hobi” atau “mitos”. Lembaga-lembaga modern yang saya maksud, mencakup juga dunia harakah (yang hemat saya memiliki ciri modern sangat kuat dalam hal keorganisasian) dan dunia perguruan tinggi di Indonesia saat itu. Nah, pada masa itu, saya juga mulai menulis berbagai hal tentang film dan sastra.
Maka, sungguh terasa segar bagi saya ketika mendengar Cak Nur, di mimbar Jumat, menganjurkan jemaah menonton sebuah film. Sebetulnya, saya tak terlalu kaget Cak Nur menganjurkan film The Name of a Rose (saya terutama kaget karena mimbarnya). Film ini, dan tentu novelnya, adalah (antara lain) sebuah sebuah simulasi pluralisme dan kebebasan berpikir. Umberto Eco membuat sebuah kisah yang mengambil tempat yang tepat untuk itu: sebuah biara di jantung kejumudan berpikir Kristen-Eropa Abad Pertengahan. Digambarkan betapa salah satu topik panas pertemuan teologi tahunan itu adalah apakah Yesus menggunakan dompet (ini penting, kata konvensi itu, untuk menetapkan status kehalalan dompet bagi orang Kristen waktu itu).
William dari Bakersville sendiri adalah sebuah perwujudan sosok Francis Bacon. Ia adalah seorang pastor yang progresif, yang meyakini sepenuhnya bahwa rasionalitas dan empirisme adalah sejalan belaka dengan kehendak Tuhan yang mengaruniai manusia dengan akal. Ia dengan dingin memandang fakta-fakta kematian di biara itu dari segi ilmiah dan motif-motif manusiawi di balik segala pembunuhan itu. Pada akhirnya, ia berhadapan dengan sang pembunuh, dan ia harus berhadapan dengan sebuah kekerasan paham yang tak ingin menerima kemanusiawian manusia (tepatnya, dalam cerita itu, tak ingin menerima humor –ah, Anda bacalah sendiri novelnya; atau, seperti dianjurkan Cak Nur, tontonlah filmnya). Kekerasan paham itu mengangankan sebuah dunia yang suci, yang tunggal dan penuh pembentengan iman.
Dan sesungguhnya, inilah warisan yang paling relevan dari Cak Nur, untuk masa kini. Ia adalah suara intelektual dan suara moral yang kuat untuk pluralisme. Saat ini, pluralisme sedang jadi kata kotor bagi sebagian umat Islam di Indonesia. Banyak kesalahpahaman yang membentuk sikap jijik (atau takut?) terhadap kata dan gagasan ini. Apalagi setelah MUI menfatwakan haramnya pemikiran Sekulerisme, Pluralisme, dan Liberalisme –kata “pluralisme” seolah sinonim dengan kata kafir.
Yang patut disayangkan adalah betapa makna “pluralisme” itu pun jadi tunggal karena fatwa itu. Para penghujat kata ini tak mau lagi menerima horison makna kata ini selain “paham yang menganggap semua agama sama” (pencarian sederhana lewat google.com atau Wikipedia saja akan menunjukkan bahwa pemahaman tunggal ini salah kaprah) –dan dengan ketunggalan makna itu, percakapan pun ditutup. Lebih dari itu, seperti dalam akhir kisah The Name of a Rose, sang penutup percakapan itu merasa amatlah pantas untuk membunuh.
Maka ia pun (berusaha) membunuh sebuah kata, membunuh sebuah pengetahuan, dan akhirnya, membunuh manusia juga. Kemudian, ia merasa harus membunuh sebuah peradaban.***
*versi teredit tulisan ini, ada di buku ini:
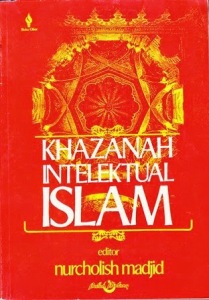


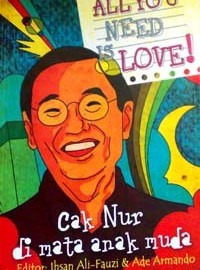
mantap sekaleee…kang hikmat
dodi0pdip
June 21, 2015 at 11:51 pm
Film yang sangat bagus Cak…..saya pernah nonton sekali itu. Kapan peluncuran film terbarunya….?
Jual Wallpaper Dinding Jogja
September 11, 2015 at 8:53 am